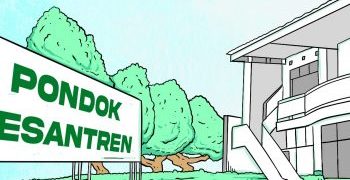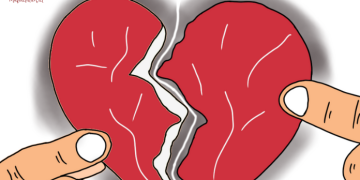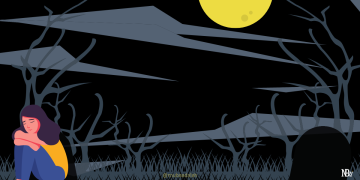Mubadalah.id – Sebagai manusia yang berkeadilan, bersosial, dan memiliki sifat humanis terhadap makhluk sekitarnya, sudah seharusnya memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Terlebih dengan merambahnya era modern yang ditandai dengan munculnya teknologi canggih, menyisakan pesan untuk mempertanyakan kembali posisi kita sebagai manusia sejati.
Era modern menjadi alternatif yang praktis tanpa mikir panjang, bahkan hanya satu kali klik untuk membuktikan apa yang kita inginkan. Kondisi demikian menunjukkan sifat menubuhnya teknologi modern dalam jiwa manusia dan berpotensi bersifat individual yang tak berkepedulian.
Kemudian teknologi memaksa kita agar fokus terhadap hal-hal yang bersifat data dan kalkulatif. Tentu peran kita akan menjadi dominan dalam mengaplikasikan hal itu. Namun, bagaimana jika ada yang tidak mampu? bisakah kita menghampiri dan membantunya? ataukah sikap apatis menjadi raja?
Ketika kemanusiaan dikerdilkan menjadi statistik dan empati digantikan oleh data, quo vadis humanisme? Humanisme tak lagi menjadi gagasan moral, melainkan menjadi landasan perjuangan antara nilai, identitas dan kemajuan.
Meskipun humanisme terdengar dalam kehidupan sehari-hari, namun makna dan penerapannya kerap belum terpenuhi dalam lelaku sosial. Terbukti dengan liarnya kasus pembunuhan, pemerkosaan, pengkuburan moral, berita pahit tentang kebijakan pemimpin sehingga kaum minoritas terhimpit nasib.
Hal demikian merepresentasikan kaburnya rasa humanisme dalam diri manusia. Anehnya kekaburan itu terus menerus terjadi pada kalangan yang berpendidikan, sesekali tercerahkan, namun bersifat peyoratif.
Humanisme Inklusif
Karena artikel ini sebuah tawaran, maka langkah awal akan menjelaskan apa itu humanisme dan inklusif secara deskripti-kritis. Humanisme berasal dari kata humanus dalam bahasa Latin yang berarti manusia, dan pada umumnya merujuk pada pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, dengan fokus pada nilai, martabat, dan potensi manusia.
Sementara Inklusif berarti bersifat menyertakan, tidak membedakan atau mengesampingkan pihak manapun; menerima dan menghargai keberagaman dalam berbagai aspek seperti budaya, ras, agama, gender, dan lain-lain.
Secara definitif Humanisme inklusif adalah pandangan atau pendekatan yang menempatkan nilai dan martabat manusia sebagai pusat, sekaligus mengakui dan menghargai keberagaman manusia tanpa diskriminasi. Humanisme ini menekankan bahwa semua manusia memiliki hak, nilai, dan potensi yang sama, serta harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang latar belakang, identitas, atau perbedaan apapun.
Dengan kata lain, humanisme inklusif adalah bentuk humanisme yang tidak hanya menempatkan manusia sebagai pusat, tetapi juga secara aktif mengakomodasi dan menerima seluruh keragaman manusia, sehingga menciptakan sikap terbuka, penghormatan, dan kesetaraan bagi semua orang.
Humanisme inklusif ini menekankan dan mengajak kita untuk melihat manusia bukan hanya sebagai individu otonom, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan sosial yang kompleks dan saling bergantung. Dalam konteks ini, humanisme inklusif tidak hanya relevan dalam bidang filsafat atau etika, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam pendidikan, politik, ekonomi, dan hubungan antarumat beragama.
Oleh karena itu, pembahasan mengenai humanisme inklusif menjadi sangat penting sebagai fondasi bagi masyarakat yang adil, setara, dan berperikemanusiaan.
Belajar Dari Kalangan Minoritas
Mengapa harus belajar dari kalangan minoritas? Karena sudut pandang materialistik menjadikannya terpinggirkan, termarginalisasi dan ter-ter yang berkonotasi merendahkan lainnya.
Namun justru dari posisi inilah, sesuatu yang berharga dapat kita petik. Ketika seseorang berada di pinggiran, ia memiliki perspektif unik yang tidak berada pada mereka yang berada di lingkar kekuasaan.
Dapat kita lihat bahwa kalangan ini sudah kebal menghadapi tantangan hidup setiap hari, diskriminasi, prasangka, dan ketidakadilan mewarnai realitas hidup mereka. Akan tetapi itu bukanlah tantangan, namun membangun mental dan bangkit dari keterpurukan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan mempertahankan optimisme dalam kesulitan.
Ambil contoh komunitas tuli yang mengembangkan bahasa isyarat. Keterbatasan pendengaran tidak melemahkan mereka, justru melahirkan sistem komunikasi visual yang kaya dan kompleks. Bahasa isyarat bahkan meningkatkan kemampuan kognitif dan spasial penggunanya. Inilah wujud nyata humanisme inklusif: mengakui bahwa perbedaan bukan kekurangan, melainkan kekayaan alternatif.
Dalam kata Buya Husein, minoritas sifatnya unpredictable, tapi mereka ada di hadapan kita. Minoritas Adalah kaum yang harus kita dampingi, bukan malah menjadi terpinggirkan.
Sementara bagi Arthur Combs, aspek krusial dari humanisme adalah sudut pandangnya terhadap dunia, untuk mengerti orang lain, yang terpenting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat, dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau dunianya. Maka paradigma yang bersifat diskriminatif seharusnya cepatlah membusuk, karena menyebabkan makarnya dehumanisasi.
Dengan demikian humanisme inklusif menawarkan jalan menuju kesetaraan yang bukan hanya adil secara moral, tetapi juga cerdas secara strategis. Kemanusiaan kita akan semakin utuh ketika kita merangkul seluruh spektrum pengalaman manusia, termasuk yang berasal dari kalangan yang selama ini terpinggirkan.
Visi Misi Masa Depan : Masyarakat Humanis Inklusif
Melalui pembahasan yang singkat dan visioner namun tidak manis seperti slogan para motivato ini, humanisme inklusif menawarkan jalan kesetaraan menuju keadilan yang berperikemanusiaan. Bukan hanya deal secara moral, namun merdeka sejak dalam pikiran dan cerdas secara ekologis sosial. Karena kemanusiaan tercapai dalam potensi optimalnya apabila setiap individu dapat berkontribusi tanpa hambatan apapun.
Kesetaraan bukan redistribusi power dari satu kelompok ke kelompok lain, melainkan penciptaan sistem di mana power mengalir secara organik sesuai konteks dan kebutuhan. Dalam humanisme inklusif, leadership bersifat situasional dan kolaboratif. Bukan hierarkis dan permanen.
Sebagai indikator keberhasilan, masyarakat humanis inklusif dapat berawal dari unit-unit kecil. Keluarga yang menghargai setiap anggota tanpa stereotyping, sekolah yang mengakui multiple intelligences, workplace yang menerapkan inclusive leadership, komunitas yang merayakan diversity sebagai strength.
Inilah sebuah tawaran untuk menghadapi degradasi moral dan dehumanisasi serta kesetaraan yang tidak hanya bermartabat, tetapi juga regeneratif menciptakan kondisi di mana setiap generasi memiliki akses yang lebih baik untuk mengekspresikan keunikan dan potensinya.
Semoga kemerdekaan negara Indonesia esok menjadi momentum terciptanya peradaban yang inklusif dan berkemanusiaan. Merdeka! []