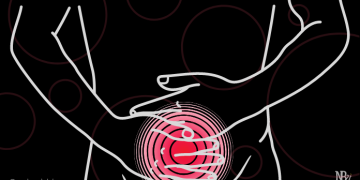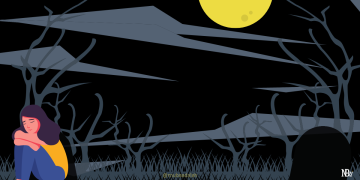Mubadalah.id – Bahasa mencerminkan cara kita berpikir dan memandang dunia. Ia membentuk kesadaran dan menentukan bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Ketika masyarakat masih menggunakan istilah cacat untuk menyebut penyandang disabilitas, kita sebenarnya sedang mempertahankan pola pikir yang menempatkan sebagian manusia pada posisi yang lebih rendah.
Padahal, dalam pandangan Islam, setiap manusia memiliki martabat yang sama dan tercipta dengan hikmah yang tak bisa kita bandingkan dengan ukuran fisik semata. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris disability yang berarti keterbatasan dalam fungsi tertentu.
Namun penggunaan istilah cacat yang lazim di Indonesia sering kali membawa makna moral dan sosial yang berat seolah menandakan ketidaksempurnaan atau sesuatu yang patut kita kasihani. Padahal istilah ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi seseorang tetapi juga membentuk cara orang lain memandangnya. Dalam banyak kasus kata cacat melahirkan stigma jarak sosial bahkan diskriminasi yang tidak kita sadari.
Masih banyak orang yang tanpa beban berkata “anak cacat,” “orang cacat,” atau “cacat mental” tanpa memikirkan dampak emosionalnya. Bahasa seperti itu menempatkan individu sebagai objek stigma bukan subjek yang memiliki martabat. Padahal penyandang disabilitas bukanlah manusia cacat secara nilai atau kapasitas. Maka penting untuk menghapus kata cacat ini dari pikiran.
Mereka memiliki potensi kecerdasan dan semangat hidup yang sering kali justru lebih kuat dari kebanyakan orang yang kita sebut normal. Karena itu istilah disabilitas atau difabel different ability jauh lebih tepat dan manusiawi.
Bahasa yang masyarakat gunakan berperan besar dalam membentuk perilaku sosial. Ketika seseorang kita beri label negatif lingkungan cenderung memperlakukannya sesuai label itu. Anak yang tumbuh dengan sebutan cacat mungkin tumbuh dengan rasa rendah diri karena lingkungan terus menegaskan bahwa dia berbeda.
Labeling Theory
Fenomena ini dapat kita jelaskan melalui Labeling Theory yang dikemukakan oleh Howard Becker(1963). Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang terberi label negatif oleh masyarakat misalnya cacat maka individu itu cenderung mendapat perlakuan sesuai label tersebut. Bahkan dapat mulai menginternalisasi identitas itu. Labeling bukan hanya deskriptif ia membentuk realitas sosial dan memengaruhi cara orang lain serta diri sendiri memandang individu yang dilabeli.
Ini menekankan bahwa penggunaan istilah cacat bukan sekadar masalah bahasa tetapi menciptakan stigma sosial yang melekat pada penyandang disabilitas. Sebaliknya dengan menggunakan istilah yang lebih manusiawi seperti disabilitas atau difabel masyarakat dapat mengurangi efek labeling negatif membuka ruang kesetaraan dan menegaskan martabat individu. Teori Becker memperkuat argumen bahwa perubahan bahasa adalah langkah penting untuk membongkar stigma dan membangun masyarakat inklusif.
Bahasa bukan sekadar alat komunikasi melainkan juga cermin struktur kekuasaan. Mereka yang dominan menentukan istilah yang digunakan dan istilah itu bisa menciptakan ketidakadilan. Karena itu mengubah cara berbicara tentang penyandang disabilitas adalah langkah pertama menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
Evolusi Bahasa tentang Disabilitas
Penelitian oleh Erin E, Andrews Robyn, M Powell, dan Kara Ayers (2022) dalam Disability and Health Journal menjelaskan bahwa evolusi bahasa tentang disabilitas mencerminkan perubahan paradigma sosial.
Istilah seperti person first language orang dengan disabilitas dan identity first language penyandang disabilitas muncul sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas dan preferensi individu. Bahasa bukan sekadar urusan terminologi ia adalah alat perjuangan untuk memulihkan martabat dan memperluas ruang kesetaraan. Bahasa bisa menjadi alat penindasan tetapi juga bisa menjadi alat pembebasan.
Masyarakat kita sering kali berhenti pada rasa simpati terhadap penyandang disabilitas. Mereka terpuji karena luar biasa bisa bekerja atau menginspirasi karena tetap berjuang. Padahal yang mereka butuhkan bukanlah simpati melainkan pengakuan atas hak dan kapasitasnya sebagai manusia yang setara. Rasa simpati yang berlebihan justru bisa berubah menjadi bentuk ableism sikap yang secara halus menempatkan mereka di bawah standar manusia normal.
Di dunia kerja diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sering kali muncul dalam bentuk halus kesempatan promosi yang lebih kecil lingkungan kerja yang tidak aksesibel. Atau rekan kerja yang memperlakukan mereka seolah butuh bantuan terus-menerus. Padahal banyak riset menunjukkan bahwa inklusi di tempat kerja justru membawa dampak positif bagi produktivitas dan moral organisasi.
Lingkungan Kerja yang Inklusif
Penelitian oleh Fitore Hyseni, Douglas Kruse, Lisa Schur, dan Peter Blanck (2022) menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang inklusif terhadap penyandang disabilitas meningkatkan loyalitas kreativitas dan perilaku kewargaan organisasi organizational citizenship behavior.
Ketika karyawan merasa terhargai tanpa syarat mereka cenderung berkontribusi lebih aktif dan membangun suasana kerja yang sehat. Inklusi bukan sekadar kewajiban moral tetapi investasi jangka panjang yang memperkuat organisasi.
Namun kebijakan inklusif tidak cukup jika hanya berhenti di permukaan. Banyak perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas untuk memenuhi kuota tetapi tidak menyiapkan sarana kerja yang memadai.
Sebuah perusahaan yang ramah disabilitas seharusnya memastikan aksesibilitas fisik menyediakan perangkat kerja adaptif serta menumbuhkan kesadaran di kalangan karyawan bahwa perbedaan bukan hambatan melainkan bagian dari keragaman manusia.
Menilik Prinsip Kesalingan
Prinsip kesalingan menjadi kunci dalam memandang isu disabilitas. Kesalingan mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki peran dan nilai yang bisa saling melengkapi.
Relasi antara penyandang disabilitas dan masyarakat bukanlah relasi antara penerima bantuan dan pemberi bantuan melainkan hubungan setara antar-manusia. Kesetaraan bukanlah hadiah yang diberikan oleh yang kuat kepada yang lemah melainkan hak yang melekat pada setiap insan.
Melalui prinsip ini dunia kerja pendidikan dan ruang sosial seharusnya kita atur berdasarkan nilai kolaborasi bukan belas kasihan. Ketika kita memperlakukan penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang berdaya kita sedang mengembalikan fitrah kemanusiaan yang sejati.
Dalam kerangka itulah Islam mengajarkan penghormatan kepada manusia tanpa memandang kondisi fisiknya karena kemuliaan terukur dari kontribusi dan kemanfaatannya kepada sesama.
Menghapus kata cacat dari pikiran bukan hanya soal mengganti istilah tetapi soal membongkar cara pandang lama yang hierarkis. Bahasa adalah pintu kesadaran. Ketika kita mulai menggunakan istilah yang lebih adil kita sedang membentuk masyarakat yang lebih berempati dan setara. Langkah sederhana seperti memilih kata yang tepat mendengarkan pengalaman penyandang disabilitas atau mendukung kebijakan inklusif adalah bentuk nyata dari perubahan sosial yang bermartabat.
Perjuangan kesetaraan bagi penyandang disabilitas adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan itu sendiri. Ia bukan isu pinggiran tetapi cermin dari sejauh mana kita memahami nilai-nilai keadilan. Menghapus kata cacat dari pikiran adalah langkah awal untuk menghapus diskriminasi dari kehidupan sosial kita. Dari bahasa yang memuliakan lahirlah masyarakat yang memanusiakan. []