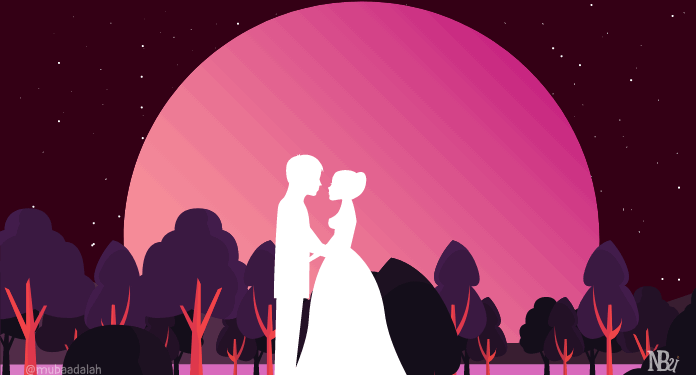Mubadalah.id – Dalam pandangan sebagian masyarakat Indonesia, pernikahan sering dianggap sebagai kewajiban agama, bahkan ibadah yang mutlak harus dijalani. Tak jarang, anggapan ini membuat seseorang merasa terpaksa menikah demi memenuhi norma keagamaan atau tuntutan sosial.
Padahal, dalam fikih, pandangan seperti ini tidak sepenuhnya tepat. Para ulama klasik, termasuk Imam Syafi’i, justru memandang pernikahan sebagai urusan duniawi yang bersifat muamalah—yakni kontrak sosial yang menuntut kerelaan dan kesepakatan, bukan ibadah ritual yang bersifat sakral dan wajib.
Sebagai kontrak, pernikahan berada dalam kerangka kesepakatan yang mensyaratkan kejelasan hak dan kewajiban, kebebasan dari paksaan, serta persetujuan dari kedua belah pihak.
Oleh karena itu, jika terjadi pemaksaan dalam akad nikah—baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Maka kontrak tersebut secara prinsip tidak sah, dan dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.
Pandangan ini sejalan dengan praktik Nabi Muhammad Saw dalam sejumlah peristiwa penting. Salah satunya diriwayatkan oleh Aisyah ra, yang suatu hari didatangi oleh seorang remaja perempuan yang mengadu bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan sepupunya demi alasan status sosial keluarga. “Padahal aku tidak menyukainya,” ungkap gadis itu.
Aisyah kemudian meminta sang gadis menunggu sampai Rasulullah datang. Setelah mendengar cerita itu, Rasulullah Saw memanggil ayah si gadis dan secara tegas mengembalikan keputusan kepada anak perempuannya.
Dalam pernyataannya, gadis itu berkata: “Aku izinkan apa yang dilakukan ayahku. Tetapi aku ingin memberi peringatan kepada semua perempuan bahwa orang tua tidak punya hak atas urusan ini.” (HR. an-Nasa’i, dalam Jami’ al-Ushûl, no. hadis: 8974, jilid 12, hlm. 142).
Pernikahan: Ruang Kesepakatan
Kisah ini bukan sekadar potret historis, tetapi juga menjadi preseden hukum dan moral dalam Islam bahwa pernikahan bukanlah tindakan sakral yang menafikan kehendak personal. Sebaliknya, pernikahan adalah ruang kesepakatan yang harus mereka landasi dengan kerelaan, bukan pemaksaan.
Dalam konteks sosial hari ini, ketika pemaksaan menikah masih banyak terjadi dengan dalih menjaga kehormatan keluarga, status sosial. Bahkan menyelamatkan perempuan dari stigma. Maka kita perlu kembali mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan sebagaimana yang Nabi contohkan.
Oleh sebab itu, menurut pandangan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, menikah karena cinta dan kesalingan jauh lebih sesuai dengan semangat Islam ketimbang menikah karena tekanan atau pemaksaan.
Dengan demikian, memahami pernikahan sebagai kontrak sosial—bukan ibadah yang kaku dan memaksa—bukanlah bentuk sekularisasi. Tetapi justru upaya mengembalikan semangat Islam yang adil, rasional, dan membebaskan. []