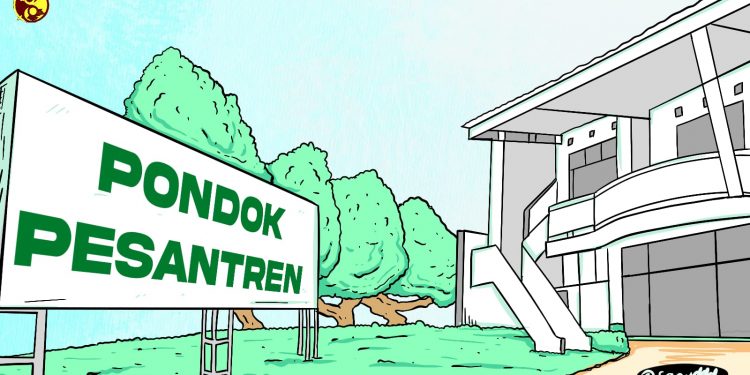Mubadalah.id – Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. (Azyumardi Azra, 2007). Meskipun demikian, pesantren mampu beradaptasi dengan modernitas, sehingga keberadaannya masih eksis di tengah gempuran teknologi pendidikan. Salah satu unsur terpenting adalah kepemimpinan di pesantren dan keberadaan kiai. Ia memiliki pengaruh yang besar dan menjadi rujukan masyarakat untuk menginterpretasi Islam.
Dalam struktur masyarakat patriarki, kiai tak hanya memiliki otoritas tertinggi dalam kepemimpinan pesantren. Namun juga memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan rumah tangganya. (Dhofier, 1982) Adapun nyai (istri kiai) diposisikan sebagai pendamping kyai dan pihak yang bertanggungjawab atas kebutuhan domestik pesantren.
Pun demikian dengan penerus kepemimpinan, kiai memiliki hak penuh untuk memilih siapa yang akan menjadi penggantinya. Mayoritas akan berlanjut pada anak lelakinya atau yang kita kenal dengan sebutan gus.
Namun seiring dengan semakin terbukanya akses bagi perempuan, terjadi perubahan kepemimpinan di pesantren. Posisi nyai tidak hanya sebagai pendamping kiai namun juga sebagai partner yang memiliki hak untuk merumuskan kebijakan pesantren.
Bahkan ada juga pesantren yang kepemimpinannya terpegang oleh bu nyai, antara lain; pesantren Kebon Jambu Al Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon oleh Nyai Masriyah Amva; pesantren Mahasiswa Bekasi oleh Nyai Badriyah fayumi; pesantren putri Cintapada oleh Nyai Nonoh Hasanah.
Nyai sebagai Sentralitas Agensi Perempuan di Pesantren
Perubahan kepemimpinan bu Nyai di pesantren ini tak bisa kita lepaskan dari pengaruh gerakan kesetaraan yang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah usung. (Jamal Makmur, 2015) NU melahirkan organisasi sayap perempuan berupa Muslimat dan Fatayat. Sedangkan Muhammadiyah memiliki Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah. Keduanya organisasi tersebut aktif membincang isu kesetaraan gender dan bagaimana posisi perempuan dalam Islam.
Selain Muslimat, Fatayat, dan Aisyiyah, ada pula FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) yang diinisiasi oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. (Masdar Mas’udi, 2021) Kitab kuning tidak saja merepresentasikan kontinuitas keilmuan dalam pesantren karena ditulis oleh ulama abad pertengahan, tapi juga rujukan penting dalam menginterpretasi Islam. Namun sayangnya, banyak teks-teks misoginis yang terproduksi di dalamnya, dan acapkali menjadi pembenar untuk mensubordinasi perempuan.
Maka sebagai bentuk penghargaan terhadap karya ulama di abad pertengahan, forum ini banyak mengadakan mimbar kajian terbuka tentang gender. Dengan mengkaji kitab kuning melalui pendekatan keadilan, kesetaraan, dan mengedepankan sisi humanisme. Forum ini juga memberikan banyak kritik/wacana tandingan (counter-discourse) terhadap kajian kitab kuning terutama dalam konsep pembagian peran publik dan domestik bagi laki-laki dan perempuan.
Forum Kajian Kitab Kuning (FK3)
FK3 bertujuan untuk lebih memantapkan sosialisasi gender kepada publik. Sehingga muslim bisa menerima pandangan progresif tentang kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Adapun anggota FK3 itu sendiri terdiri dari bu nyai, ning, dan pengasuh pesantren yang harapannya mampu memberi interpretasi baru tentang makna gender sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Keberadaan organisasi sayap perempuan baik di NU maupun Muhammadiyah ini membuka peluang bagi perempuan untuk memperbarui kajian fiqh agar lebih transformatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang selalu berkembang di masyarakat. Hal tersebut mereka lakukan salah satu tujuannya adalah dalam rangka penguatan hak-hak perempuan.
Dengan adanya berbagai gerakan ini pulalah, terjadi pergeseran posisi nyai yang sebelumnya hanya menjadi pelengkap keberadaan kyai dan pesantren berubah menjadi sentralitas agensi. Nyai juga memproduksi ilmu, nyai juga menjadi rujukan untuk pengetahuan agama, nyai juga memiliki hak untuk menafsirkan hal-hal furu’iyah berasaskan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan.
Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan di Pesantren
Perubahan kepemimpinan di pesantren meneguhkan semangat perjuangan kemanusiaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dipertegas oleh Qs al-Hujurat ayat 13 bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bertaqwa kepada Tuhannya. Bukan berdasarkan jenis kelaminnya, suku, ras, bangsa, ataupun faktor lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi untuk menjadi makhluk terbaik di hadapan Allah adalah hak semua gender. Termasuk juga di dalamnya kompetisi dan kerjasama dalam sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam sebuah kelembagaan seyogyanya kita pandang dari segi kapasitas dan kemampuan yang dimiliki bukan berdasarkan jenis kelamin.
Pun demikian dalam otoritas keagamaan, tidak terkooptasi oleh gender tertentu namun terbuka untuk siapapun yang memang memiliki kapasitas dan kemampuan di bidang keagamaan.
Maka dengan demikian penerus kepemimpinan dalam sebuah pesantren seharusnya tidak hanya mengedepankan keturunan dengan gender tertentu. Namun berdasarkan pada kapasitas dan kemampuan para penerus. Terpilih berdasarkan kemampuannya bukan karena faktor-faktor pembeda lahiriyah yang berpotensi menyebabkan diskriminasi dan subordinasi.
Nilai-nilai patriarki yang mengesampingkan sisi kemanusiaan harus kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Dan pondok pesantren sebagai pusat keilmuan agama, bisa menjadi leading sector utama yang mampu mengikis nilai-nilai patriarki di tengah masyarakat. Jika nilai kesetaraan sudah terinternalisasi secara maksimal di sebuah pesantren, maka masyarakat akan mengikuti tradisi baik tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. []