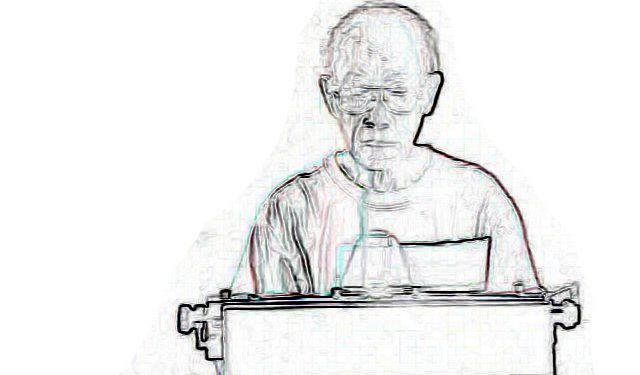Mubadalah.Id– Berikut ini penjelasan suara perempuan dalam karya Pram. Polemik pembuatan film Bumi Manusia oleh Falcon Pictures yang akan disutradarai Hanung Bramantyo masih terus bergulir. Secara pribadi saya menyambut baik rencana itu, karena sebagai salah satu orang pengagum dan pembaca karya-karya Pramoedya Ananta Toer, bayangan jika tetralogi pulau buru itu sudah ada bahkan sejak pertama kali saya mengenal buku-buku Pram medio 2002 silam.
Tak hanya sekali saya membaca buku-buku itu, mungkin sudah lebih dari lima kali, secara hitungan saya tak tahu persis, saking seringnya. Namun di sisi lain pemilihan artis untuk memerankan beberapa tokoh dalam novel itu memang diluar ekspektasi kita bersama para Pram lovers.
Terlepas dari puas atau tidak Bumi Manusia diangkat ke layar lebar oleh Hanung, saya ingin mengulik karya Pram dari sudut yang lainnya.
Patut diakui ada energi luar biasa yang saya rasakan setiap kali usai membaca tulisan Pram, terutama ketika memposisikan perempuan sebagai sang penggerak peradaban, bukan hanya objek sejarah yang hanya menyumbangkan nama dan identitas. Namun, buah pikiran, perasaan, dan aktivitas perempuan yang mencerminkan sebagai manusia yang mandiri, independen dan berdaulat atas dirinya sendiri.
Tahu apa yang harus dilakukan, sehingga seolah budaya patriarkhi dan relasi kuasa yang begitu kental membelenggu perempuan dari masa ke masa di Indonesia (terutama Jawa dalam setingan novel Pram), seakan tiada artinya.
Dan itulah perjuangan sesungguhnya bagi perempuan agar mampu mencapai jalan yang direntasnya sendiri, dengan penuh tekad, gelora semangat dan daya upaya.
Yakni tentang sosok Nyai Ontosoroh (Ibu dari Annelis, Istri Minke) dalam novel Bumi Manusia, yang dikisahkan sebagai seorang perempuan yang mempunyai pendirian kuat dan bermental baja, janda dari seorang Belanda.
Meski Sang Tuan telah tiada, Nyai Ontosoroh mampu membuktikan sanggup mengatasi pekerjaan dan tanggung jawab yang telah ditinggalkan suaminya, bahkan menjadi lebih maju dan modern.
Meski berasal dari kalangan biasa, dengan diberi kesempatan untuk mengubah nasib, Nyai Ontosoroh yang nama masa kecilnya Sanikem, memanfaatkan peluang itu untuk belajar sebaik-baiknya. Tak ada yang dia lewatkan, bagaimana akhirnya dia berdiri sejajar, disegani dan diakui dalam pergaulan yang lebih luas pada masa itu.
Ada kalimatnya yang sampai hari ini menjadi inspirasi bagi para perempuan.
“Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri. bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri.”
kalimat ini menggambarkan dengan jelas tentang sikap kemandirian Nyai Ontosoroh, dan bagaimana dia terus belajar memantaskan diri menjadi perempuan yang berpengetahuan luas, pandai dalam pergaulan dan cermat mengelola keuangan.
Walau pada akhirnya dia harus kehilangan itu semua karena posisi yang lemah secara hukum sebagai Nyai (Perempuan yang dijual untuk dijadikan istri pejabat Belanda).
Kalimat Nyai Ontosoroh yang masyhur lainnya adalah, “Jangan sebut aku perempuan sejati jika hidup hanya berkalang lelaki. Tapi bukan berarti aku tidak butuh lelaki untuk aku cintai.”
Sepeninggal suaminya Tuan Mellema, bisa saja Nyai Ontosoroh menikah lagi dan mudah mendapatkan lelaki manapun. Namun tidak demikian yang menjadi pilihan Nyai Ontosoroh. Dia tidak mengandalkan sepenuhnya pada sosok lelaki, Tak mau hidup di bawah ketiak lelaki, menjadi konco wingking dan tak pernah dianggap ada.
Meski begitu, Nyai Ontosoroh tetap membutuhkan lelaki di mana cintanya kelak akan berlabuh. Sebelum masa itu tiba, dia terus memantaskan diri dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, agar bisa mendapatkan lelaki sesuai dengan pilihan hatinya, yang mau berdiri setara, saling menopang, beriringan bersamanya hingga menua nanti.
Walau akhir kisah Nyai Ontosoroh tragis, karena harus berhadapan dengan hukum kolonial saat itu yang tak memperbolehkan “Nyai” memiliki hak waris, bahkan terhadap anak kandung sendiri. Dia telah melawan dengan sebenar-benarnya perlawanan yang bermartabat sebagai perempuan.
Nyai Ontosoroh hanyalah satu kisah suara perempuan di antara sekian banyak karya Pram yang lain, kita masih membaca cukup banyak yang mengetengahkan tokoh perempuan sebagai figure sentral, diantaranya Midah, Si Manis Bergigi Emas, Gadis Pantai, Larasati dan tentunya Tetralogi Buru. Sosok perempuan dalam karya Pram selalu muncul dengan karakter yang sulit dilupakan.
Dalam kisah Gadis Pantai, selepas membaca hingga lembaran terakhir terasa bagaimana rasa sesak yang tertinggal didada dan tenggorokan yang tercekat menahan tangis, menggelayut kesedihan hingga berjam-jam kemudian, mengingati tentang seorang gadis yang dari awal sampai akhir tak diketahui siapa namanya.
Dalam kepolosan gadis kecil yang dinikahkan dengan sebilah keris, hingga pada akhirnya harus kehilangan segala hal, termasuk anak perempuan kesayangan yang baru dilahirkannya.
Itulah suara perempuan dalam karya Pram, yang mungkin sampai hari ini masih menjadi bagian dari wajah perempuan di Indonesia. Tentang ketakberdayaan dan perlawanan hingga ke titik nadir, lalu sampai pada detik akhir kehidupan memperjuangkan hak-haknya sendiri, terhadap sistem dan realita sosial yang masih belum berpihak pada perempuan.
Namun saya percaya suara perempuan yang tergambar di dalam novel-novel Pram akan terus menginspirasi para perempuan. Terlebih saya sendiri agar terus melangkah menyusuri jalan panjang kesetaraan itu. Meski terasa sunyi tapi saya tahu tak pernah merasa sendiri.
Demikian penjelasan terkait suara perempuan dalam karya Pram. Semoga suara perempuan dalam karya Pram.[Baca juga: Suara Perempuan dalam Karya Pram ]