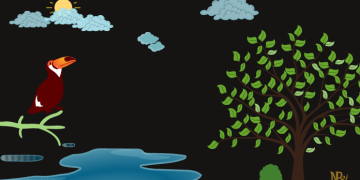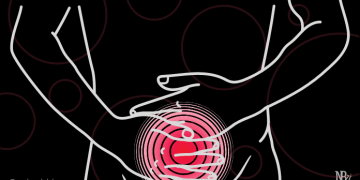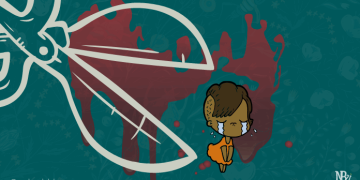Mubadalah.id – Banyak lelaki di muka bumi ini yang hidup kesepian. Berharap dapat memiliki satu saja teman sejati yang mampu membuatnya tak merasa berdiri seorang diri di atas muka bumi.
Banyak sekali lelaki berharap dapat bertemu bidadari yang sanggup memahami, mengerti, menerima kehadirannya dengan tulus, dengan sepenuh hati, yang mencintai sekaligus menggerakkan hati untuk dicintai. Menjadi tempat bersandar, menjadi tempat berpulang, menjadi rumah yang menyediakan selimut kedamaian.
Namun tidak semua laki-laki seberuntung itu. Termasuk diriku.
Gelandangan Cinta
Bagiku, perempuan adalah rumah bagi laki-laki. Tanpa perempuan (yang dicintai), laki-laki hanya gelandangan. Betapapun sukses, cerdas, dan hebatnya laki-laki, tanpa perempuan yang ia cintai di sampingnya, maka semua harta benda dan apa-apa yang dimiliki tak berguna, ia tetap tunawisma. Cinta adalah tempat kembali setelah seharian laki-laki berkelana mencari penghidupan. Celakanya, tak ada perempuan yang bisa menjadi rumah untukku.
Usiaku 45 saat ini. Aku menikah. Namun perempuan yang kunikahi tak bisa menjadi tempat kembali. Kendati setiap hari aku pulang dari kantor selalu menuju rumahku, namun hatiku tak pernah berada di sana. Kendati kami sudah dikaruniai tiga anak, dia tetap bukanlah sosok yang mampu membuatku merasa penuh dan utuh.
Aku dulu menikahinya karena cinta dan aku bertanggung-jawab. Namun di tahun ke delapan, rasa cintaku pudar. Sudah kucoba beragam cara untuk membangkitkan cintaku lagi, tetap saja cintaku padanya tak pernah kembali hadir.
Ada kehampaan, dan perasaan hambar yang akut manakala bersamanya. Aku sudah berusaha mengingat semua kebaikan-kebaikannya, berharap bisa menghadirkan kembali rasa yang hilang, tetap tak bisa. Ini kondisi di mana kau benar-benar sudah tidak terkoneksi, tidak cocok, hampa, buntu, tidak punya rasa pada seseorang. Namun tak ada yang bisa kau lakukan dan kau hanya terbakar, putus asa, frustasi. Aku tak bisa melawan rasa ini dan semakin dipertahankan, rasanya semakin menyakitkan.
Kencan Ulang
Sudah kucoba melakukan kencan ulang seperti rekomendasi buku-buku dan para psikolog. Sebuah upaya untuk membangkitkan kembali kenangan masa silam, sebuah usaha untuk membangkitkan cinta kami yang sudah lapuk.
Kami berjalan-jalan ke kota tua seperti saat kami pacaran dulu. Lalu kami mengunjungi pabrik kopi, kami meminum kopi juga. Aku tertawa-tawa, karena aku memang pria yang hobi tertawa. Kami juga ngobrol, aku tukang ngobrol, dia juga suka mengobrol, namun kata-kata yang ia ucapkan pada akhirnya menguap seperti menjadi sampah semua. Kami berjalan-jalan dan berwisata, kami saling mengambil foto, namun chemistry tetap tidak terbangun.
Sampai di rumah, aku merasa energiku terkuras habis. Kembali ke rutinitas, kembali monoton. Sepertinya kesepian sudah menjadi takdirku, aku merasa sesak dan sakit karena itu. Mungkin inilah yang disebut pernikahan adalah penjara, aku terperangkap dengan seseorang, seseorang yang salah.
Namun siapa yang mau mengaku jika ia telah menikah dengan orang yang salah? Aku selalu berkamuflase meyakinkan diriku bahwa pilihanku benar. Namun hati tidak bisa dimanipulasi.
Sudah Tak Ada Nyala Api Cinta
Lain waktu, sudah kucoba melakukan sesi mengobrol intens, menatap matanya, fokus padanya, namun ujungnya selalu datar. Tak ada api yang menyulut dadaku untuk berkata, ya dialah cintaku. Kami hidup bersama, berdampingan, setiap hari bertemu, namun rasanya kosong dan hampa.
Tak ada keintiman antara kami bahkan dalam hubungan intim. Seks yang terjadi antara kami pada akhirnya hanya proses biologis semata, hanya aktivitas yang mirip buang hajat saja. Hanya pemenuhan kebutuhan insting hewani. Ini menyakitkan.
“Apa masalahmu? Apa yang kalian bicarakan sehari-hari?” Tanya Panji sahabatku.
“Aku punya banyak kegelisahan, namun dia tidak pernah bisa paham dan mengerti kegelisahanku. Aku punya banyak keruwetan di kepala, namun ia tak bisa mengerti, apalagi membantuku mengurai semuanya. Pembicaraan kami dari awal menikah adalah tentang kulit dan cangkang. Aku ingin kami menjadi partner yang sejalan dalam pemikiran, melakukan pembicaraan yang nyambung dan klop, bukan hanya perkara domestik dan pernak-pernik, tapi wacana yang lebih luas layaknya dua manusia dewasa yang sama-sama mendayagunakan akalnya untuk berfikir. Namun tak pernah ada pembicaraan sedewasa itu terjadi.”
Terbang dengan Berat Sebelah
Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dieratkan oleh cinta, gairah dan kepuasan. Namun sekarang sudah tak ada rasa puas, tak ada kedekatan, tak ada keintiman. Apalagi mencapai kondisi jiwaku merasa berlimpah energi dan kebahagiaan. Hubungan kami setiap hari berangsur menjadi makin dangkal. Separuh jiwaku rasanya hilang, dan aku merasa terbang dengan berat sebelah.
Pada akhirnya, aku hidup dengan istriku hanya untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. Pada akhirnya, kami hanyalah dua orang yang bersepakat hidup dalam satu atap seperti rekan ngontrak yang terikat oleh akta pernikahan untuk membesarkan anak-anak. Makan, tidur, kerja, basa-basi, haha-hihi, selebihnya hanya percakapan receh dan tawa-tawa palsu yang menjadi buih dan hilang dalam sekejap.
Aku merasa kesepian, meskipun sedang bersama seseorang. Setiap hari menjalani rutinitas yang sama dan tak ada habisnya. Setiap hari aku pulang ke rumah, namun jiwaku entah di mana. Dan sepertinya kesepian ini akan berlangsung seumur hidup.
Jebakan Pernikahan
“Jika akhirnya akan seperti ini, kenapa kau menikahinya? Seharusnya kau lebih selektif lagi!” Ucap Panji di lain waktu.
“Dulu dia adalah perempuan terbaik dari semua pilihan yang ada. Dialah pilihan terbaikku setelah kulakukan penjajakan dan pertimbangan serasional mungkin. Namun cinta adalah hal yang rumit, dan pernikahan seperti jebakan. Ada orang yang menikah dengan orang yang tidak dicintai, namun di usia limapuluhan cinta mereka menggebu layaknya anak muda. Ada yang menikah dengan cinta menggebu dan keyakinan sebesar gunung di awal-awal, namun endingnya menjadi kehampaan. Aku yang nomer dua.”
“Jika pernikahan adalah jebakan, seharusnya kau terjebak dengan yang terbaik. Agar semua mudah diperbaiki.”
Menusuk sekali ucapan Panji itu. Dia memang mengenal istriku. Kata Panji, istriku bukanlah tipe terbaik yang bisa diperbaiki. Mau dipoles bagaimanapun, hasilnya tetap sama, aku akan merasa hampa. Menurut Panji, sumber mati rasaku paling besar ada dalam pribadi istriku sendiri.
Dia teman atau musuh batasnya serasa tipis sekali. Istriku memang punya banyak kekurangan, namun dia juga punya banyak kebaikan. Dia menemaniku dari nol, berjuang susah-senang bersama, memberiku anak, dan telah banyak berkorban. Jasa-jasanya itulah yang membuatku memilih bertahan, meski aku remuk di pedalaman.
“Hidup bukan hanya tentang balas jasa, Andreas. Kau bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat. Apa gunanya hidup tanpa cinta? Kau akan remuk seumur hidup. Jiwamu menjadi impoten! Malang sekali.”
Panji memberiku hujatan sekaligus nasehat-nasehat yang kurasa sudah kubaca semua di buku. Entah itu anjuran untuk duduk bersama membuka komunikasi dua arah, membongkar sampai ke akar, konseling psikologi, hingga rukyah, doa-doa, dan mantera-mantera.
…
Panji;
Tahun ke delapan pernikahan adalah gerbang kejenuhan pernikahan yang pertama, namun Andreas memilih tetap melanjutkannya berharap istrinya bisa berubah dan memperbaiki kekurangannya seiring berjalannya waktu. Dan sembari menunggu perubahan pasangan secara pasif itu, sudah lahir anak kedua. Kondisi ini terus berlanjut. Namun bisa dibaca bahwa istrinya tidak akan berubah karena tidak ada usaha, namun ia masih berharap sambil semua dijalani saja, sampai lahir anak ketiga, sampai pendidikan doktornya selesai.
Dan istrinya masih dengan kualitas yang sama seperti sejak awal menikah meski ijazah S2 sudah di kantong. Ya, ijazah memang hanya tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda seseorang pernah berfikir. Kekurangan fatal istri Andreas bukan ketidaksetiaan, tapi tidak adanya kecerdasan. Kecerdasan tidak akan jadi soal jika pasangan kita tidak pintar, namun pria cerdas membutuhkan partner hidup yang sama cerdasnya, atau minimal hampir sama.
Ditambah, Andreas memiliki libido seks yang tinggi, istrinya tak mampu merawat diri dan tak bisa mengimbangi gairah, fantasi dan performa seksual Andreas di ranjang, ini fatal. Belum lagi caci-maki, kemarahan, dan komentar pedas istri Andreas yang seringkali tidak menunjukkan bahwa ia seorang terpelajar…
Secerdas apapun laki-laki, jika istrinya tidak cerdas, maka dia berpotensi mengalami kesepian yang dalam. Mengapa demikian? Karena kegelisahan dan keruwetan pikiran si laki-laki tidak mungkin bisa dipahami oleh orang yang secara intelektual jauh di bawahnya.
Dan kesepian semacam ini adalah kesepian substansial, menyentuh wilayah paling vital, yang tidak bisa diobati dengan padatnya aktivitas keseharian ataupun hiburan-hiburan temporer yang disediakan kehidupan. Satu-satunya solusi adalah pasangan harus menyetarakan diri secara intelektual, namun proses belajar adalah hal yang tidak bisa dipaksa dan tidak instan.
Memaksa orang belajar tidak semudah itu, harus dimulai dengan kemauan. Jika watak dasar seseorang tidak suka membaca dan berfikir, maka seribu anjuran dan nasehat akan dianggap angin lalu. Dan seribu buku yang tersedia di hadapannya hanya diperlakukan bagai kertas biasa. Istri Andreas telah nyaman dengan kebodohannya. Kebodohan yang melukai suaminya.
Memang dari awal, memilih jodoh yang sekufu secara kecerdasan itu penting. Jika tidak, selamanya pembicaraan akan menjadi hambar. Kenapa pembicaraan menjadi hambar? Karena tidak setara. Manusia cerdas akan bicara menyentuh ranah substansi sampai ke daging-dagingnya, istri Andreas hanya membicarakan kulit di permukaan. Padahal pernikahan berisi 80% percakapan.
Andreas hidup dengan wanita paruh baya dengan nalar dan logika anak sekolah menengah, sementara dia pria intelek dengan kapasitas nalar profesor. Setahun dua tahun mungkin bisa ditahan, tapi jika sudah berlangsung belasan tahun, tentu itu masalah. Andreas telah sampai pada, “Udahlah ngapain cerita, ngapain ngobrol serius, ngapain curhat kegelisahan dan kerumitan pikiranku, toh dia tidak akan mudeng!”.
Andreas menginginkan saripati, istrinya memberi ampas.
…
Pengingkaran dan Kamuflase
Sudah sejuta cara kutempuh, namun cara itu tidak berguna. Aku menjalani hariku dengan pengingkaran-pengingkaran. Senin sampai Jumat bekerja, hari Sabtu Minggu untuk keluarga. Aku menjalani rutinitas dengan menghindari pertanyaan-pertanyaan eksistensial untuk diriku sendiri. Berharap suatu hari aku akan menemukan cara, atau sekelumit keajaiban terjadi. Semua kesibukan membantuku melewati hari, melupakan kegelisahan, namun itu bukan solusi.
Hanya akhir pekan hiburanku bersama anak-anak yang sedikit membuatku “menyala”. Menemani mereka renang, nonton film, nonton festival, main ke taman hiburan, ke pantai, keliling kota, mendengarkan mereka berceloteh, bertingkah-polah. Namun seperti biasa, pulang sampai di rumah aku akan bersandar di kursiku, menghela nafas berat dan panjang.
Menjelang malam, dalam keheningan, aku akan bertanya ulang: begini-begini sajakah hidup yang akan kujalani? Dan hal ini akan terus kulakukan sampai anakku kelak selesai kuliah semua, sampai mereka dewasa, menikah, punya anak sendiri dan aku menua, kembali berdua dengan istriku.
Jika panjang umur mungkin aku akan menjalani kehampaan ini, 30 atau 40 tahun lagi. Sungguh bukan waktu yang singkat, namun inilah pilihan yang aku pilih. Remuk redam yang akan kujalani.
Batin yang Sekarat
Kata Panji, aku sudah berada dalam kondisi batin yang sekarat. Aku menderita kesepian dan kehampaan berat. Dan akar masalahku hanya satu, sudah tidak ada cinta di hatiku. Mau bagaimanapun berusaha, aku tak akan pernah selesai dengan diriku sendiri sebelum perkara cinta ini selesai. Cinta adalah hal yang pelik, kita tak bisa memaksanya untuk tiba-tiba datang, kita juga tidak bisa memaksanya untuk tiba-tiba tumbuh dan bertahan. Aku tak berdaya.
Perempuan adalah rumah bagi laki-laki namun tidak ada perempuan yang bisa menjadi rumahku. Perempuan yang mampu membuatku merasa hidup, merasakan eksistensiku ada. Perempuan yang mampu membuatku mendekapnya dengan perasaan mendalam, dengan tatapan sakral penuh penghayatan, dan dengan yakin tanpa keraguan aku berkata bahwa dialah cintaku. Atau setidaknya membuatku tentram walau barang sekejap.
Oh. Bagaimanakah caranya aku menyembuhkan hubungan yang sudah kering kerontang, habis mata airnya? Bagaimana aku mengembalikan cinta yang sudah pupus bertahun-tahun? Buku-buku yang kubaca tak bisa mengembalikannya. Petuah bijak tak ada yang mampu menolongku. Inikah takdir hidup yang harus kuhadapi sepanjang sisa usia yang kumiliki?
Aku menikah, dan pasanganku sudah tidak bisa menjadi seseorang yang dapat memberiku semangat dan memberiku harapan hidup.
Menangis dalam Sunyi
Apakah aku selamanya berdiri seorang diri tanpa bisa punya rumah tempat jiwaku kembali? Aku iri melihat lelaki yang memiliki rumah jiwa semacam itu. “Rumah” yang benar-benar aku miliki bukan karena dipaksa-paksakan bahwa itu disebut rumah. Rumah betulan yang bukan fatamorgana.
Entahlah, aku kalut, aku frustasi. Jika memang nasibku hidup di dunia adalah menjalani absurditas hidup semacam ini, maka terjadilah! Aku hanya bisa menangis seorang diri, dalam sunyi, tanpa berharap ada yang mampu memahami. []