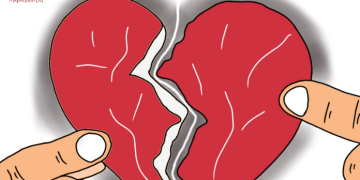Mubadalah.id – Setiap menjelang hari raya Idul Fitri, kita selalu diingatkan akan kewajiban membayar zakat fitrah. Selama ini, kebiasaan yang berlaku adalah menunaikannya dengan beras sebanyak 2,5 kilogram atau uang senilai Rp 47.000, sebagaimana ketetapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2025. Namun, pernahkah kita bertanya: Mengapa harus beras? Mengapa harus uang? Apakah ketentuan ini benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, atau sekadar kebiasaan yang terus kita wariskan tanpa evaluasi?
Sebagian besar dari kita mungkin merasa sudah tenang setelah membayar zakat fitrah dengan cara tersebut. Tetapi, bagi yang berpikir lebih jauh, muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar: Mengapa ukuran 2,5 kg beras atau uang sebesar Rp 47.000? Apakah besaran ini memiliki dasar eksplisit dalam al-Qur’an dan Hadits? Apakah ada logika dan alasan kuat di balik angka tersebut? Lebih jauh, apakah angka ini ditentukan berdasarkan kecukupan pangan bagi pemberi zakat (muzakki), atau justru didasarkan pada kebutuhan dasar penerima zakat (mustahiq)?
Pertanyaan yang lebih krusial adalah: Apakah zakat fitrah yang kita keluarkan setiap tahun benar-benar mampu menjawab kebutuhan orang miskin di masa sekarang? Ataukah zakat fitrah hanya sebagai ritual tahunan yang tidak memiliki dampak nyata dalam pemberdayaan mereka? Jika tujuan zakat fitrah adalah memastikan bahwa orang-orang miskin dapat menikmati hari raya dengan layak. Apakah jumlah yang kita keluarkan selama ini benar-benar mencukupi?
Mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar: Apakah al-Qur’an dan Hadits benar-benar menyebutkan beras dan uang sebagai harta zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap orang setelah mengakhiri bulan Ramadan?
Apa Kata al-Qur’an dan Hadits?
Jika kita merujuk pada al-Qur’an dan Hadits Nabi, tidak ada satu pun dalil yang secara eksplisit menyebutkan bahwa zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk beras atau uang. Hadits Nabi hanya menyebutkan bahwa zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk satu sha’ (sekitar 2,5 kg) gandum, atau kurma. Tidak ada beras, dan tidak ada pula uang. Lalu, dari mana asal usul zakat fitrah dalam bentuk beras atau uang yang kita kenal saat ini?
Jawabannya terletak pada ijtihad ulama. Mazhab Syafi’i menggunakan metode analogi (qiyas), dengan menganggap beras sebagai makanan pokok setempat yang setara dengan gandum di Arab. Menurut Imam Syafi’i, setiap makanan pokok boleh dijadikan sebagai harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Sementara itu, Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan istihsan (mencari kebijakan yang lebih baik), dengan memperbolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang yang setara dengan nilai makanan pokok tersebut. Hal ini dianggap lebih praktis dan lebih sesuai dengan kebutuhan penerima zakat.
Namun, perlu kita sadari bahwa ijtihad kedua mazhab ini lahir pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah. Sedangkan kita kini hidup di abad ke-15 Hijriah. Artinya, dalam dua hingga tiga abad setelah kehidupan Nabi Saw, para ulama sudah melakukan ijtihad yang menyesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi pada masa mereka. Ironisnya, dalam kurun waktu 12 abad berikutnya, hampir tidak ada ijtihad baru yang secara serius mempertimbangkan perubahan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Padahal, dalam rentang waktu yang begitu panjang, dunia telah mengalami transformasi luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan.
Jika para ulama abad ke-2 dan ke-3 mampu melakukan ijtihad untuk menjawab tantangan sosial di zamannya, mengapa kita yang hidup 12 abad setelah mereka tidak melakukan hal yang sama? Bukankah kita juga memiliki tanggung jawab—bahkan kewajiban—untuk merumuskan kembali konsep zakat fitrah agar lebih relevan dengan kondisi sosial kita sendiri?
Antara Ibadah Ritual atau Ibadah Sosial?
Sayangnya, masih banyak di antara kita yang terjebak dalam cara pandang bahwa zakat fitrah adalah semata-mata ibadah ritual yang harus sama persis seperti yang Nabi Saw contohkan. Padahal, Nabi sendiri tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras, apalagi uang. Perubahan dari gandum menjadi beras, atau dari makanan pokok menjadi uang, adalah hasil ijtihad ulama setelah masa Nabi sebagai bentuk adaptasi terhadap konteks sosial yang berbeda.
Hal ini menunjukkan bahwa bentuk harta zakat fitrah tidak harus kita pahami secara kaku sebagai ibadah ritual yang harus sama persis dengan masa Nabi, yaitu berupa gandum atau kurma. Sebaliknya, yang lebih utama adalah memastikan bahwa zakat fitrah kita keluarkan dalam bentuk yang benar-benar bermanfaat bagi penerimanya. Makanan pokok masyarakat setempat, termasuk dalam bentuk uang yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, adalah bagian dari esensi zakat yang harus terus kita perbarui sesuai dengan perkembangan zaman.
Jika kita melanjutkan semangat ijtihad ini dan memandang zakat fitrah sebagai ibadah sosial yang harus relevan dengan kondisi kehidupan saat ini. Maka konsepsi kita tentang bentuk dan besaran zakat fitrah pun seharusnya menyesuaikan dengan realitas sosial-kontemporer. Artinya, kita tidak lagi sekadar berfokus pada keabsahan bentuk zakat (beras atau uang) dalam jumlah tertentu secara formal. Tetapi lebih kepada fungsi sosial zakat itu sendiri: berapa dan dalam bentuk apa zakat fitrah seharusnya diberikan agar benar-benar mampu memenuhi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya.
Zakat Fitrah dalam Konteks Sosial-Ekonomi Kontemporer
Pada masa Nabi, makanan pokok merupakan kebutuhan dasar yang paling utama. Sehingga wajar jika zakat fitrah diwujudkan dalam bentuk gandum, kurma, atau makanan pokok lainnya. Namun, realitas kehidupan saat ini telah berubah secara signifikan. Kebutuhan dasar manusia tidak lagi hanya sebatas makanan pokok. Tetapi juga mencakup lauk pauk, asupan energi yang cukup dan sehat, serta dalam beberapa kondisi. Termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Jika kita tetap terpaku pada beras atau uang setara 2,5 kg beras, tanpa mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang. Maka kita justru mengabaikan hakikat zakat fitrah sebagai instrumen kesejahteraan sosial.
Coba kita pikirkan secara logis. Jika tujuan zakat fitrah adalah mencukupi kebutuhan dasar orang miskin pada hari raya. Apakah benar kebutuhan tersebut hanya sebatas 2,5 kg beras atau uang senilai itu? Mengapa angka ini diberlakukan secara seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan ekonomi, geografi, dan kondisi sosial di berbagai daerah? Pada kenyataannya, hampir di seluruh dunia saat ini, kebutuhan pangan yang layak tidak hanya terdiri dari makanan pokok yang kaya karbohidrat. Tetapi juga harus mengandung protein, serat, zat besi, kalsium, dan nutrisi lainnya agar benar-benar memenuhi standar gizi yang layak.
Mungkinkah kita mendesain ulang besaran zakat fitrah agar tidak hanya berfokus pada kecukupan makanan pokok. Tetapi juga pada kecukupan pangan yang sehat dan bergizi? Sehingga, orang-orang yang memiliki kemampuan finansial membayar zakat dalam jumlah yang sesuai dengan standar gizi yang layak. Sementara mereka yang kurang mampu benar-benar mendapatkan manfaat yang lebih besar dari zakat ini.
Di masa tertentu, mungkin kebutuhan orang miskin tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga mencakup layanan kesehatan dasar atau pendidikan. Namun, setidaknya untuk saat ini, akses terhadap makanan sehat dan bergizi tetap menjadi prioritas utama yang perlu kita perjuangkan. Maka, apakah kita masih akan bertahan dengan model zakat fitrah yang statis, atau mulai membuka ruang bagi pembaruan agar zakat benar-benar menjadi solusi bagi kemiskinan di era modern?
Mengapa Harus Berubah?
Pemahaman zakat fitrah dalam bentuk 2,5 kg beras atau uang senilai Rp 47.000 mungkin masih relevan bagi sebagian kecil masyarakat miskin di daerah tertentu. Namun, angka ini tidak dapat kita generalisasi untuk seluruh wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar. Di daerah urban, jumlah tersebut nyaris tidak mencukupi kebutuhan pangan satu keluarga miskin. Karena dalam banyak kasus terdiri dari empat anggota keluarga: ayah, ibu, dan dua anak.
Memaksakan standar 2,5 kg beras atau Rp 47.000 tanpa mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi justru berisiko membuat zakat fitrah kehilangan makna sosialnya. Padahal, zakat seharusnya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan bagi orang-orang miskin, terutama di hari raya. Jika kita sepakat bahwa zakat adalah ibadah sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat. Maka besaran zakat fitrah harus kiita sesuaikan dengan standar kecukupan pangan yang layak pada masa kini.
Salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan adalah merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka kecukupan pangan yang layak, sehat, dan bergizi untuk satu keluarga dalam satu hari. Angka ini dapat kita ambil dari rata-rata nasional atau, idealnya, sesuai dengan kondisi ekonomi setiap kota dan kabupaten. Dengan demikian, besaran zakat fitrah dapat lebih proporsional dan kontekstual.
Jika kita mengikuti ijtihad yang menyatakan bahwa zakat fitrah hanya wajib bagi mereka yang mampu dan memiliki kecukupan pangan tersebut. Maka orang miskin yang tidak mencapai batas tersebut tidak wajib berzakat. Namun, jika ada yang tetap ingin berzakat, hal itu tentu tetap boleh. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penerima zakat benar-benar orang-orang yang secara pendapatan harian tidak mencapai standar kecukupan pangan layak dalam keluarganya. Terutama mereka yang, pada hari raya, tidak memiliki cukup makanan yang layak, sehat, dan bergizi untuk dikonsumsi.
Merujuk pada Teladan Nabi Saw
Dalam sebuah hadits riwayat Imam Baihaqi, menyebutkan bahwa zakat fitrah hanya untuk orang-orang miskin agar mereka tercukupi kebutuhan pangannya dan tidak harus meminta-minta pada hari raya. Esensi zakat fitrah bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban secara formal. Tetapi juga memastikan bahwa setiap individu yang kurang mampu dapat merasakan kebahagiaan Idul Fitri tanpa kekhawatiran akan kelaparan. Namun, kecukupan ini bersifat kontekstual dan harus terus kita evaluasi berdasarkan realitas sosial-ekonomi yang berkembang.
Jika kita benar-benar ingin meneladani Nabi Saw dalam memberi kecukupan pangan kepada orang-orang miskin. Maka besaran dan bentuk zakat fitrah yang kita keluarkan harus kita sesuaikan dengan standar kehidupan masa kini, bukan sekadar terpaku pada 2,5 kg beras atau uang senilai itu. Sebab, apa yang ia anggap cukup di masa lalu belum tentu cukup di era sekarang. Di mana kebutuhan dasar tidak hanya sebatas makanan pokok, tetapi juga asupan gizi yang layak. Dengan memahami konteks sosial-ekonomi kontemporer, kita dapat menjadikan zakat fitrah lebih relevan, adil, dan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan.
Kini, pertanyaannya: Apakah kita masih ingin mempertahankan praktik zakat fitrah yang sekadar menggugurkan kewajiban tanpa benar-benar memberikan kecukupan pangan yang layak bagi orang miskin? Ataukah kita berani melakukan perubahan agar zakat fitrah kembali kepada fungsi sejatinya sebagai instrumen keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Islam? []