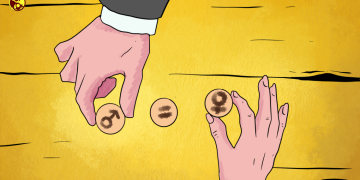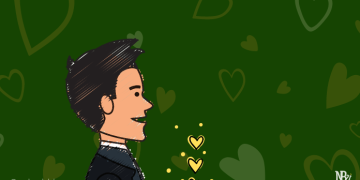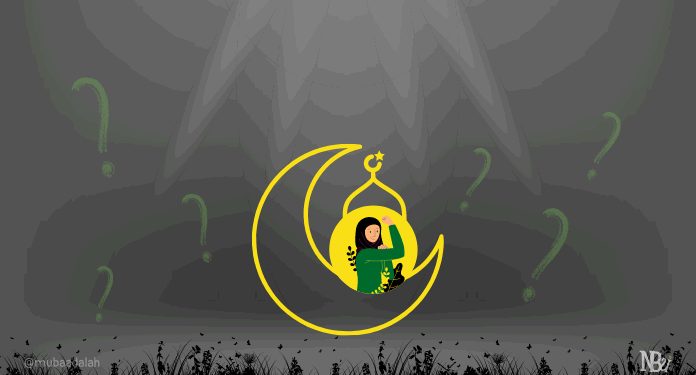Mubadalah.id – Dalam ajaran Islam, perempuan bukanlah objek yang bisa dipaksa untuk menikah. Melainkan ia adalah subjek yang memiliki hak penuh untuk memilih dan menentukan pasangan hidupnya.
Dengan pemahaman ini, kawin paksa atau perjodohan, seharusnya kita hentikan. Karena kalau kita mau mengambil pelajaran dari dialog yang terjadi antara seorang anak perempuan, ayahnya dan Nabi Muhammad SAW, semestinya praktik kawin paksa terhadap perempuan tidak terjadi dalam masyarakat yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad Saw.
Bahkan seribu empat ratus tahun yang lalu, seorang perempuan mengemukakan pernyataan yang sangat lantang di hadapan Nabi SAW dan para sahabat: “Aku lebih berhak tentang perkawinannya daripada ayahku”.
Kisahnya, seperti yang dituturkan Aisyah ra, bahwa ada seorang remaja perempuan yang datang menemuinya seraya berkata:
“Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar status sosialnya terangkat olehku, padahal aku tidak suka”. “Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku tanyakan”, jawab Aisyah.
Ketika Rasulullah SAW datang, beliau mengungkapkan persoalan perempuan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan (sambil memberi peringatan), dan mengembalikan persoalan itu kepada si perempuan untuk memberikan keputusan.
Di hadapan mereka, remaja perempuan tadi menyatakan (dengan tegas): “Aku izinkan apa yang telah dilakukan ayahku. Tetapi aku ingin memberikan peringatan sekaligus pernyataan untuk semua perempuan: bahwa mereka para orang tua sama sekali tidak memiliki hak atas persoalan (pernikahan) ini”. (Riwayat an-Nasa’i, lihat Jami’ al-Ushul, no. hadis: 8974, juz XII, hal. 142).
Keputusan Menikah Ada di Tangan Perempuan
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Malik, Abu Dawud dan an-Nasa’i, bahwa ketika seorang perempuan yang bernama Khansa binti Khidam ra merasa dipaksa dikawinkan oleh orang tuanya, Nabi mengembalikan keputusan itu kepadanya, mau diteruskan atau dibatalkan, bukan kepada orang tuanya.
Bahkan dalam riwayat Abu Salamah, Nabi Saw menyatakan kepada Khansa r.a: “Kamu yang berhak untuk menikah dengan seseorang yang kamu kehendaki”. Khansa pun pada akhirnya kawin dengan laki-laki pilihannya Abu Lubabah bin Abd al-Mundzir r.a. Dari perkawinan ini, ia memiliki anak bernama Saib bin Abu Lubabah.
Seharusnya fiqh memandang perempuan, sebagai calon mempelai, memiliki hak lebih kuat daripada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, apalagi saudara yang lebih jauh, tidak berhak untuk memaksakan kehendak dalam hal pemilihan pasangan hidup.
Karena pemaksaan tidak akan pernah melahirkan kerelaan, ketulusan, apalagi kebahagiaan. Sekalipun untuk hal-hal yang memang diperlukan oleh mereka yang dipaksa menikah. Ia hanya akan melahirkan hipokritas relasi keluarga, bahkan pertengkaran dan pertentangan.
Moralitas keberagamaan sejatinya kita tanamkan secara partisipatoris untuk menjadi pilar dalam membangun kehidupan berkeluarga, bukan menjadi cambuk yang mengancam orang agar selalu taat dengan peraturan dan norma perkawinan. []
Sumber: Buku Pertautan Teks dan Konteks dalam Muamalah karya Dr. Faqihuddin Abdul Kodir.