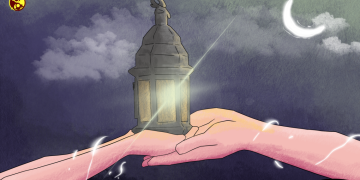Mubadalah.id – Di sebuah bangunan di Sukabumi, sekelompok pelajar mesti bertahan dari amarah dan rasa kebencian berbasis agama. Tak ada perlindungan yang aman. Di selepas salat Jumat, segerombol massa merusak eksterior, atau mungkin bahkan interior, bangunan yang terduga menjadi tempat ibadah sebuah agama.
Mereka adalah pelajar Kristen yang memakai bangunan itu untuk menjalankan serangkaian ibadah, dalam satu versi mereka tengah latihan menyanyikan lagu rohani dan mereka menyewanya (bayar). Rupa-rupa alasan terbaca ihwal alih fungsi itu bangunan.
Konon, sebelum menjadi tempat tinggal, mulanya bangunan menjadi ruang pemipilan jagung, ternak domba, dan ternak ayam. Setelahnya bangunan itu resmi menjadi tempat tinggal pemiliknya.
Setelahnya, bangunan itu pernah terjadikan sebagai tempat misa dan jenis peribadahan lainnya. RT dan perwakilan masyarakat sekitar merasa keberatan jika bangunan menjadi ruang peribadatan. Acara demi acara yang konon terduga sebagai bentuk peribadatan itu terlaksana di sana. Pemilik rumah, dan mungkin panitianya, tak begitu menanggapi imbauan keberatan itu.
Sampai pada puncaknya, pada Jumat (27 Juni 2025), setelah melewati sekian mediasi antara pemerintah desa setempat dengan pemilik rumah dan penyelenggara tak berhasil, massa mulai merangsek. Terlihat di pelbagai video bertebaran di media sosial, massa memecahkan kaca. Ada pula yang naik ke lantai atas lalu menurunkan salib kayu. Dan, bentuk pengrusakan lain terhadap fasilitas yang ada.
Usaha Menghargai
Kita membaca sejenak penggalan Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, …” Konsep ‘beribadat menurut agamanya’ itu apakah mesti mendapat izin dari pemerintah, aparat, atau bahkan masyarakat setempat beragama mayoritas?
Ada ruang yang oleh negara sisakan untuk kemudian menjadi perdebatan-perdabatan. Jika pun suatu umat beragama merasa terganggu dengan cara peribadatan umat agama lain, itu mestinya terselesaikan di meja mediasi.
Manakala tak menemu hasil, tidak juga lantas sikap anarkis dan semena-mena itu menjadi lampu hijau penyelesaian. Apa yang pemilik bangunan dan penyelenggara latihan menyanyi rohani agama Kristen lakukan dengan mengindahkan keberatan masyarakat sekitar tentu itu salah. Namun, perilaku masyarakat mayoritas yang, ketika imbauan keberatannya terhiraukan, malah melakukan aksi pengrusakan itu jauh lebih salah.
Kadang kala, persoalan kecil bisa membikin bara amat besar jika tak tersikapi pikiran terbuka. Ada egoisme dan kebencian yang kedua belah pihak pegang. Ada hal yang semestinya umat beragama pegang selain fokus pada hak mereka beragama saja.
Melakukan segala bentuk peribadatan memang terjamin oleh negara, tetapi kadang negara telambat hadir untuk menengahi-nyelesaikannya, atau bahkan tidak hadir sama sekali. Maka sikap menghargai “tak tertulis” terhadap umat agama lain itu perlu terjunjung.
Seandainya ada keberatan umat agama satu terhadap umat agama lainnya, maka perundingan di sana menjadi jalan menuju kemufakatan, bukan berujung pada sikap kebencian. Umat agama satu jangan anarkis, satunya lagi jangan egois. Memang keduanya tak dapat dibenarkan. Jauh sekali dengan falsafah toleransi. Beragama tidak boleh egois dan anarkis. Keduanya tak dapat terbenarkan dengan alasan apapun.
Kunci Kemajemukan
Dalam majalah Tempo Edisi Hari Kemerdekaan 20 Agustus 2006, Ignas Kleden memberi padangan apik soal perbedaan lewat tulisan berjudul “Merdeka dalam Kemajemukan”. Ignas menyoroti orang-orang Indonesia gemar memakai retorika semboyan lama: berbeda-beda tapi satu, padahal kemajemukan menuntut pembalikan itu secara total dengan: satu tetapi berbeda-beda.
Retorika lama soal ‘berbeda tapi satu’ ini, sesuai tangkapan saya atas tulisan Ignas itu, cenderung memaksa kesadaran akan pluralisme. Pemaknaannya bisa beragam, berbeda agama, suku, ras, kebudayaan, dsb, tetapi satu atas nama bangsa Indonesia ini kadang masih menyisakan lubang tafsir pragmatis.
Paradigma yang terpakai berbeda, lalu satu. Pantas jika peristiwa-peristiwa intoleransi dari hari ke hari, atau yang lebih spesifik mutakhir itu, banyak yang mendukung atas dalih solidaritas agama, tetapi tak sedikit juga yang mengutuknya.
Satu itu sematkan dalam setiap jiwa masyarakat Indonesia. Satu tujuan untuk masa depan, kemajemukan, kemaslahatan, dsb walaupun berbeda dari pelbagai hal. Tak ada lagi egosime, kebencian, dan luka karena kita berbeda, tapi sembuhkan luka yang terlanjur itu dengan rasa satu. Kalau saja nyaris umat beragama kita masih terbalik memaknainya, maka sejatinya kita belum benar-benar merdeka seutuhnya dalam perbedaan. []