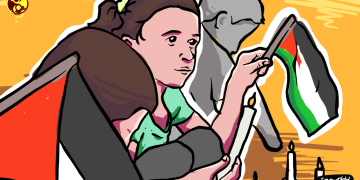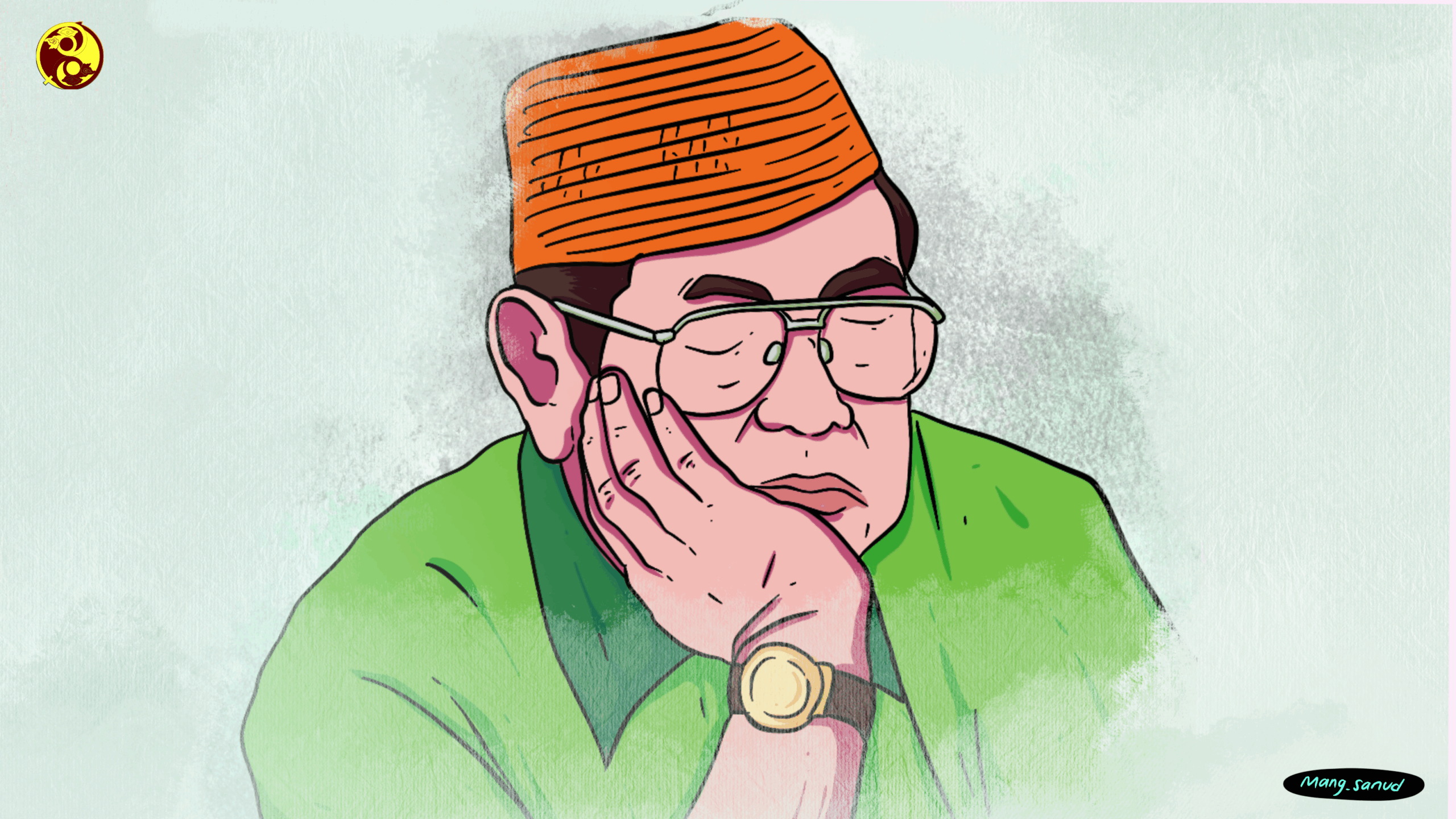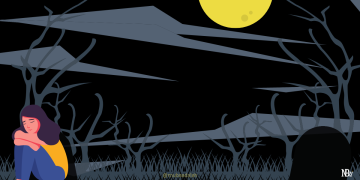Mubadalah.id – Akhir-akhir ini, jalanan dan linimasa kita terhiasi oleh fenomena bendera tengkorak bertopi jerami. Jolly Roger, lambang dari kelompok bajak laut Topi Jerami dalam serial anime dan manga populer One Piece. Bendera ini berkibar di tiang-tiang darurat depan rumah, di belakang truk, hingga menjadi mural di tembok-tembok kota.
Fenomena yang memuncak menjelang hari kemerdekaan ini memicu perdebatan yang membelah masyarakat. Di satu sisi, banyak yang melihatnya sebagai ledakan kreativitas, simbol kebebasan, atau bahkan cara jenaka untuk menyuarakan kritik sosial terhadap situasi negara saat ini. Bagi mereka, Luffy dan kawan-kawan adalah simbol perjuangan melawan tirani dan ketidakadilan.
Namun, di sisi lain, muncul reaksi yang penuh kecurigaan. Sejumlah pejabat negara dan anggota parlemen melihat bendera ini sebagai “provokasi” yang berpotensi merusak persatuan dan menurunkan martabat Merah Putih. Menko Polhukam bahkan mengeluarkan peringatan keras, mengancam akan menindak pengibaran bendera fiksi tersebut jika ia anggap sengaja merendahkan kehormatan simbol negara.
Mengapa bendera dari dunia fiksi ini dijadikan pusaran diskursus nasionalisme yang kaku, terancam dengan pasal-pasal pidana, dan terbingkai sebagai potensi ancaman terhadap negara?
Menurut saya, perdebatan ini, jika kita amati lebih dalam, terasa ganjil dan agak berlebihan. Pakar hukum telah menjelaskan bahwa tidak ada aturan spesifik yang melarang pengibaran bendera One Piece, selama posisinya tidak menyaingi atau merendahkan bendera Merah Putih.
Bukan Gerakan Makar
Sosiolog pun menafsirkannya bukan sebagai gerakan makar, melainkan ekspresi sosial yang wajar dalam demokrasi. Sebuah cara untuk menyalurkan ketidakpuasan secara visual ketika saluran lain terasa buntu.
Kepanikan sebagian elite politik dalam menanggapi bendera fiksi ini justru menunjukkan kerapuhan. Respon berlebihan ini mencerminkan cara pandang yang kaku, yang melihat warga negaranya dengan penuh curiga dan lebih mengedepankan pendekatan represif ketimbang dialog.
Untuk keluar dari cara pandang yang sempit ini, kita sebenarnya tak perlu mencari jauh-jauh. Sejarah bangsa kita sendiri pernah mencatat sebuah teladan yang luar biasa tentang bagaimana seorang pemimpin negara merespon simbol-simbol tertentu yang “dianggap” berbahaya dan sarat dengan muatan politik separatisme. Bukan dengan gertakan, melainkan dengan kearifan dan kemanusiaan.
Kisah ini datang dari Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita sapa Gus Dur, ketika ia berhadapan dengan tuntutan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua. Peristiwa ini terjadi pada rentang waktu kepemimpinannya yang singkat, antara 1999 hingga 2001.
Dalam ‘Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka’, Ahmad Suaedy menguraikan dengan rinci bagaimana Gus Dur membongkar pendekatan militeristik dan kekerasan yang selama puluhan tahun menjadi kebijakan standar negara dalam menghadapi konflik di Aceh dan Papua.
Belajar dari Gus Dur
Ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, situasi di kedua provinsi tersebut berada di puncak kegentingan. Warisan represi Orde Baru, terutama melalui Daerah Operasi Militer (DOM), telah melahirkan luka dan trauma yang mendalam, sehingga mendorong gerakan separatis menguat.
Mereka tidak lagi percaya pada Jakarta. Di tengah bara api inilah, Gus Dur memilih jalan yang sama sekali berbeda. Jalan yang oleh banyak kalangan saat itu dianggap mustahil dan naif.
Gus Dur tidak melihat para aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai musuh negara yang harus termusnahkan. Sebaliknya, ia memandang mereka sebagai warga negara yang memiliki keluhan dan aspirasi yang sah, yang harus didengarkan. Ia mengubah paradigma dari yang semula state-centric (berpusat pada negara) menjadi pendekatan humanis yang berpusat pada manusia.
Pendekatan inilah yang ia bawa ketika menangani situasi di Papua. Gus Dur memahami bahwa identitas dan kebudayaan orang Papua telah lama tertekan. Sebagai langkah simbolis pertama, ia mengabulkan permintaan rakyat Papua untuk mengubah nama provinsi dari Irian Jaya—sebuah nama yang dianggap sebagai pemberian Jakarta—kembali menjadi Papua, nama yang mereka pilih sendiri.
Lebih dari itu, ia tidak hanya mengizinkan, tetapi juga memberikan dukungan dana bagi penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua II pada Mei-Juni 2000. Sebuah forum di mana rakyat Papua berkumpul dan menyuarakan aspirasi mereka dengan bebas, termasuk tuntutan kemerdekaan.
Kebijaksanaan Gus Dur
Di sinilah letak kebijaksanaan Gus Dur yang saya kira relevan dengan perdebatan kita tentang bendera One Piece hari ini. Dalam kongres tersebut, tuntutan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan kemerdekaan Papua, mengemuka. Bagi aparat keamanan dan kalangan nasionalis garis keras, permintaan ini adalah sebuah provokasi, sebuah tindakan makar yang tidak bisa ditoleransi.
Namun, Gus Dur melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia memahami bahwa bendera itu bukan sekadar simbol separatisme, tetapi juga representasi dari identitas budaya dan harga diri orang Papua yang telah lama terinjak-injak.
Gus Dur tidak melarang pengibaran Bintang Kejora. Ia justru mengizinkan bendera itu berkibar sebagai simbol budaya, sebagai pengakuan atas eksistensi dan kekhasan orang Papua. Namun, ada satu syarat penting: Bendera itu harus dikibarkan di bawah bendera Merah Putih.
Dengan kebijakan ini, Gus Dur mengirimkan beberapa pesan sekaligus. Pertama, ia mengakui dan menghormati identitas orang Papua. Kedua, ia menegaskan bahwa penghormatan itu berlangsung dalam kerangka NKRI. Ia tidak memadamkan api dengan paksa, melainkan memberinya ruang aman agar tidak membakar seisi rumah.
Langkah ini tentu saja bukan tanpa risiko. Gus Dur dikritik keras oleh banyak politisi dan purnawirawan militer yang menuduhnya lembek dan membahayakan keutuhan nasional. Namun, Gus Dur bergeming. Ia percaya bahwa fondasi NKRI tidak dibangun di atas laras senjata atau ketakutan, melainkan di atas keadilan, kepercayaan (trust), dan pengakuan atas keberagaman.
Dengan merangkul, bukan memukul, ia justru berhasil meredam ketegangan dan membuka jalan bagi dialog-dialog selanjutnya. Pendekatan personal dan dialogis yang ia terapkan berhasil menumbuhkan kembali kepercayaan para tokoh Papua kepada pemerintah pusat. Ini adalah modal yang sangat krusial untuk penyelesaian konflik jangka panjang.
Fenomena Bendera One Piece
Sekarang, mari kita kembali ke fenomena bendera One Piece. Jika Gus Dur, sebagai kepala negara, mampu bersikap bijaksana dan akomodatif terhadap Bintang Kejora, mengapa hari ini kita begitu panik dan reaktif terhadap bendera dari serial komik Jepang itu? Perbedaan skala ancamannya begitu jauh, bagaikan langit dan bumi!
Bintang Kejora adalah simbol nyata dari perjuangan politik yang telah memakan korban jiwa. Sementara Jolly Roger Topi Jerami adalah simbol fiksi yang diadopsi oleh anak-anak muda sebagai media ekspresi budaya populer dan kritik sosial yang sering kali berbalut humor.
Sikap berlebihan dari sebagian pejabat dalam menanggapi bendera One Piece menunjukkan sebuah kemunduran dalam cara kita bernegara. Ini menunjukkan ketakutan yang tidak pada tempatnya dan menunjukkan ketidakpercayaan negara terhadap kreativitas dan dinamika warganya sendiri.
Gus Dur mengajarkan kita bahwa negara yang kuat adalah negara yang tidak takut pada simbol. Negara yang besar adalah negara yang mampu berdialog dengan warganya, bahkan dengan mereka yang paling kritis sekalipun. Gus Dur menunjukkan bahwa kunci dari integrasi nasional bukanlah penyeragaman yang kita paksakan, melainkan pengelolaan keberagaman yang adil dan beradab.
Maka, saya kira, ketika kita melihat bendera One Piece berkibar, kita tidak perlu buru-buru menghakimi pengibarnya sebagai anti-nasionalis atau pemberontak. Mungkin kita bisa berhenti sejenak dan meniru sedikit saja dari kearifan Gus Dur. Mungkin kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang apa adanya. Sebuah fenomena budaya, ekspresi, pertanyaan, atau bahkan lelucon.
Menanggapinya dengan senyuman dan kemauan untuk mendengarkan. Alih-alih dengan amarah dan ancaman. Barangkali adalah cara yang jauh lebih baik dan dewasa untuk merawat kewarasan kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena pada akhirnya, sebuah bangsa yang besar tidak terukur dari seberapa keras ia menindak warganya, tetapi dari seberapa besar ruang yang ia sediakan bagi warganya untuk bermimpi, berkreasi, dan berekspresi. []