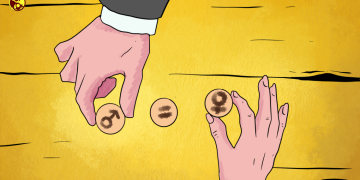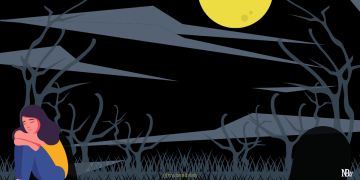Mubadalah.id – Dalam banyak narasi keagamaan, wacana kesetaraan kerap berhenti di ranah relasi laki-laki dan perempuan. Padahal, Islam sejak awal menanamkan prinsip rahmah — kasih sayang yang menembus sekat, merangkul semua tanpa kecuali. Salah satu lensa yang menegaskan prinsip itu adalah mubadalah, sebuah perspektif yang menekankan kesalingan, keadilan, dan kemitraan dalam relasi sosial.
Sebagaimana mubadalah mampu mengikis ketimpangan gender, ia juga sanggup merobohkan tembok diskriminasi berbasis kemampuan fisik. Jika diperluas maknanya, mubadalah bukan semata soal kesetaraan perempuan dan laki-laki. Ia dapat menjadi kerangka pikir yang inklusif terhadap kelompok yang kerap terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas.
Dengan kacamata mubadalah dan disabilitas ini, ajaran Islam hadir sebagai rahmah yang nyata, memastikan setiap insan, tak peduli kondisi fisik dan mentalnya, ia tetap memiliki peluang yang sama untuk berperan dan hidup bermartabat.
Kesalingan ini bukan sekadar gagasan abstrak, melainkan fondasi untuk membangun relasi yang setara antara sehat dan sakit, antara yang berdaya penuh dan yang memiliki keterbatasan. Islam mengajarkan bahwa setiap insan punya peran, nilai, dan kemuliaan yang sama di hadapan Allah serta di tengah masyarakat.
Kesetaraan itu bukan berarti meniadakan perbedaan, melainkan mengelolanya dengan kebijaksanaan. Masing-masing dapat memberi dan menerima sesuai kemampuan, sehingga kehidupan sosial menjadi taman yang saling meneduhkan, bukan pagar yang membatasi.
Dalam praktiknya, masyarakat yang memegang prinsip mubadalah akan memastikan akses yang layak ke rumah ibadah, transportasi, lingkungan kerja, hingga ruang sosial. Kesetaraan yang dibangun di atas rahmah tidak berhenti pada pasal undang-undang, tetapi menubuh dalam tindakan yang dirasakan langsung oleh semua pihak.
Mubadalah: Makna, Aplikasi, dan Transformasinya
Menurut Kupipedia, mubadalah secara terminologis adalah prinsip Islam yang menekankan kesalingan dalam menjalankan peran sosial, baik di ranah domestik maupun publik, berlandaskan keadilan dan kemaslahatan bersama. Prinsip ini menolak adanya dominasi atau subordinasi; semua pihak saling menopang, bukan menindas.
Penerapannya bisa terlihat di banyak ranah. Dalam rumah tangga, jika keramahan, perhatian, dan dukungan dianggap baik diberikan seorang istri kepada suaminya, maka hal yang sama juga baik diberikan suami kepada istrinya. Di ruang publik, mubadalah mengajak semua warga negara — laki-laki maupun perempuan — untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan.
Ketika diaplikasikan pada isu disabilitas, mubadalah menuntut adanya relasi yang setara. Masyarakat bukan hanya memberi fasilitas secara sepihak, tetapi juga membuka ruang interaksi yang sejajar. Penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi dan daya cipta, bukan sekadar penerima belas kasihan. Akses ke masjid, sekolah, pekerjaan, dan ruang publik lainnya harus punya standart yang ramah bagi semua, sehingga rahmah Islam betul-betul membumi.
Ketika Islam Turun: Meruntuhkan Stigma
Sejak fajar kelahirannya, Islam membawa misi mematahkan belenggu diskriminasi, termasuk stigma yang menimpa penyandang disabilitas. Masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam kultur kesukuan yang mengagungkan kesempurnaan fisik.
Mereka yang memiliki kekurangan fisik kerap terkena stigma lemah, tak berguna, bahkan terkucilkan dari pergaulan. Ada catatan sejarah yang menunjukkan betapa tokoh-tokoh Quraisy enggan duduk apalagi makan bersama mereka.
Lalu turunlah Al-Qur’an sebagai koreksi tegas. Dalam QS. an-Nur ayat 61, Allah menegaskan tidak ada penghalang bagi orang buta, pincang, atau sakit untuk berinteraksi sosial, termasuk makan bersama. Untuk konteks masyarakat Arab kala itu, pesan ini revolusioner: ia membongkar sekat sosial, membalik stigma, dan memulihkan martabat mereka. Nilai seseorang, tegas Islam, bukan terletak pada rupa atau raga, melainkan pada takwa dan kontribusinya.
Reformasi nilai ini selaras dengan prinsip mubadalah dan disabilitas: kesalingan tidak terbatas pada relasi gender, tapi juga merangkul perbedaan fisik. Relasi yang sehat adalah relasi yang saling menguatkan, bukan saling merendahkan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari denyut nadi masyarakat, sama-sama berhak menentukan arah dan masa depannya.
Esensi Teladan Nabi: Perspektif Inklusif dalam Islam
Prinsip rahmah Islam pun mengakui ragam kondisi manusia. Cak Nun pernah mencontohkan: Nabi Muhammad berjalan tegak penuh wibawa, tetapi itu tidak berarti semua umat harus menirunya persis. Sebab meneladani Nabi bukan berarti menyalin bentuk fisik, tetapi menghidupkan esensi ajarannya.
Hal ini serupa dengan pelaksanaan ibadah dalam kondisi sakit. Dalam QS. Ali Imran ayat 191, Allah memuji mereka yang mengingat-Nya “sambil berdiri, duduk, dan berbaring.” Pak Imam Suprayogo memaknainya sebagai ajakan untuk beribadah dalam segala keadaan. Yang utama bukan kesempurnaan postur, tetapi kemurnian niat, ketulusan hati, dan fokus pada Sang Pencipta.
Namun, di banyak tempat, pemahaman ini belum meresap sepenuhnya. Masih ada masjid yang tak ramah difabel, kebijakan yang belum inklusif, dan sikap sosial yang mengulang stigma lama. Paling tidak, perspektifnya harus benar lebih dahulu, sebab niat baik saja tak cukup.
Inilah yang semestinya menjadi pegangan para pemuka agama, guru, tokoh masyarakat, hingga super kiai manapun, agar ajarah Islam yang rahmah tak berhenti sebagai wacana, tetapi hadir sebagai napas kehidupan yang merangkul semua, tanpa terkecuali. []