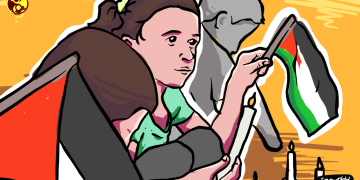Disclaimer: Tulisan ini mengandung pembahasan mengenai bunuh diri. Jika kamu sedang berada dalam kondisi tertekan atau memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, segera cari pertolongan. Kamu tidak sendirian.
Mubadalah.id – Masih teringat jelas dalam ingatanku, ketika seorang teman difabel Netra, tiba-tiba mengirimkan pesan voicenote. Suaranya begitu getir, kalimat-kalimatnya penuh keputusasaan, bahkan ia ingin mengakhiri hidupnya. Sebuah ungkapan yang langsung membuatku terdiam. Ia bercerita bagaimana dia berulang kali tertolak saat melamar pekerjaan, bahkan di posisi yang sebenarnya mampu ia jalani.
Alih-alih diberi kesempatan, ia hanya berada di rumah. Dunia seolah menutup pintu rapat-rapat. “Aku tidak berguna lagi,” katanya lirih. Aku hanya bisa terdiam, menahan perasaan yang bercampur antara sedih, marah, dan bingung.
Bagaimana mungkin seseorang yang kukenal penuh semangat bisa merasa seputus-asa itu? Tapi justru di situlah aku sadar, ada luka terdalam seringkali tidak tampak. Bukan pada tubuh yang terlihat berbeda, melainkan pada batin yang terus-menerus tertolak dan terpinggirkan.
Luka yang Tak Terlihat
Cerita temanku hanyalah satu potongan kecil dari kenyataan yang jauh lebih besar. Banyak difabel yang mengalami tekanan serupa. Di balik senyum mereka, ada kemungkinan tumpukan rasa kecewa, marah, bahkan putus asa. Masalahnya, kesehatan mental difabel seringkali luput dari perhatian.
Fokus kita kerap terhenti pada aksesibilitas fisik seperti jalur kursi roda, lift di gedung publik, atau papan informasi braille. Semua itu penting, tentu saja. Tetapi jarang sekali kita menengok pada dimensi batin, bagaimana rasanya hidup dalam dunia yang hampir setiap hari berkata, “kamu tidak layak”?
Ketika berbicara tentang difabel, banyak orang masih terjebak dalam dua pandangan sempit. Pertama, melihat difabel sebagai “pahlawan” yang harus selalu kuat, tabah, dan menjadi inspirasi. Kedua, menempatkan mereka sebagai “beban” yang hanya pantas untuk kita kasihani. Dua-duanya sama-sama berbahaya, sebab sama-sama menghapus kemanusiaan mereka yang utuh.
Dari kacamata psikologis, beban difabel tidak hanya terletak pada keterbatasan fisik atau sensorik yang mereka miliki. Beban terbesar justru datang dari interaksi sosial, seperti tatapan iba, ucapan merendahkan, perlakuan diskriminatif, hingga sistem yang menutup kesempatan mereka.
Bayangkan, setiap kali melamar kerja, pintu tertutup hanya karena label “difabel.” Setiap kali keluar rumah, tubuh mereka kita pandang seolah-olah menjadi pusat rasa kasihan. Setiap kali ingin menyuarakan pendapat, suara mereka dianggap tidak penting.
Difabel dan Beban Psikologis
Akumulasi perlakuan semacam itu melahirkan luka batin yang sulit tersembuhkan. Rasa percaya diri terkikis, perasaan tidak berguna menguasai, hingga akhirnya muncul pikiran untuk menyerah. Dalam psikologi, kita mengenal istilah “learned helplessness” atau keadaan ketika seseorang merasa tak berdaya karena berulang kali mengalami kegagalan akibat faktor di luar kendalinya.
Pada difabel, kondisi ini bisa lebih cepat muncul karena dukungan sosial seringkali minim. Lebih buruk lagi, budaya kita masih tabu membicarakan isu kesehatan mental. Depresi seringkali disalahpahami sebagai “kurang iman.” Keinginan bunuh diri dianggap sekadar “lemah.”
Padahal, masalah ini nyata, sama seriusnya dengan penyakit fisik. Bagi difabel, stigma ganda pun muncul, mereka sudah mendapat stigma karena tubuhnya, ditambah lagi dianggap “tidak waras” ketika mengalami gangguan mental.
Apa yang temanku alami sebetulnya mungkin dialami juga oleh teman difabel lainnya. Banyak kisah serupa berserakan, meski jarang tersuarakan. Seorang penyandang disabilitas fisik pernah bercerita bahwa ia merasa seperti “beban keluarga.” Setiap kali ingin keluar rumah, ia harus meminta bantuan, dan itu membuatnya merasa bersalah.
Seorang difabel tuli mengatakan bahwa ia sering merasa tidak terdengar, bukan hanya karena keterbatasan komunikasi, melainkan karena orang-orang enggan bersabar untuk benar-benar memahami bahasanya.
Di satu sisi, cerita-cerita ini menunjukkan bahwa yang mereka butuhkan bukanlah sekadar fasilitas fisik, melainkan penerimaan sosial yang tulus. Di sisi lain, kisah ini juga menegaskan bahwa isu kesehatan mental difabel bukanlah persoalan individu belaka, melainkan persoalan kolektif.
Sistem yang Tidak Inklusif
Mengapa difabel begitu rentan terhadap masalah kesehatan mental? Jawabannya terletak pada sistem sosial yang tidak inklusif. Sejak dari pendidikan, mereka sudah menghadapi tantangan. Banyak difabel tidak bisa mengakses sekolah yang ramah karena fasilitas minim atau guru tidak terlatih untuk mengajar secara inklusif. Akibatnya, peluang untuk berkembang sejak dini sudah tertutup.
Ketika memasuki dunia kerja, hambatan semakin nyata. Data menunjukkan tingkat pengangguran difabel jauh lebih tinggi daripada non-difabel. Perusahaan sering menolak dengan alasan “tidak sesuai kebutuhan,” padahal kenyataannya mereka enggan beradaptasi. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, stigma sosial memperparah situasi.
Difabel sering direduksi menjadi “kasihan” atau “pahlawan,” padahal mereka butuh untuk kita perlakukan sebagai manusia biasa. Layanan kesehatan mental pun jarang ramah difabel. Banyak psikolog, psikiater, atau konselor belum memiliki pelatihan untuk mendampingi difabel, bahkan fasilitas konseling jarang yang aksesibel secara fisik maupun komunikatif.
Sistem yang eksklusif ini membuat difabel menghadapi hambatan ganda, baik fisik maupun mental. Pada akhirnya, muncul lingkaran setan. Keterbatasan akses memicu stres, stres memperburuk kondisi fisik, lalu berujung pada semakin sempitnya kesempatan. Di sinilah kita melihat betapa pentingnya hal kecil yang sering kita anggap remeh yaitu mendengarkan.
Ketika temanku mengungkapkan keinginan bunuh diri, aku tidak punya jawaban. Aku bukan psikolog, bukan pula ahli konseling. Yang bisa kulakukan hanyalah mendengarkan. Aku membiarkan ia bercerita panjang tanpa menyela, tanpa buru-buru menghakimi. Aku tahu, satu kata “jangan” pun bisa terdengar seolah-olah meremehkan penderitaannya. Maka aku hanya hadir, berusaha menunjukkan bahwa ada seseorang yang peduli.
Mendengarkan Sebagai Pertolongan Pertama
Kadang, mendengarkan memang menjadi pertolongan pertama paling sederhana namun paling ampuh. Banyak difabel terbiasa tertolak suaranya. Maka, ketika ada yang sungguh-sungguh mau mendengar, mereka merasa eksistensinya diakui. Itu bisa menjadi tali kecil yang menahan mereka dari jurang paling gelap.
Namun, tentu saja mendengarkan saja tidak cukup. Mereka butuh akses ke layanan profesional, komunitas suportif, serta dukungan nyata dari lingkungan sekitar. Tetapi setidaknya, mendengarkan bisa menjadi pintu awal untuk menyelamatkan nyawa.
Kesehatan mental difabel tidak bisa didekati hanya sebagai masalah pribadi. Ia harus dilihat sebagai isu struktural dan sosial. Perlu ada pendidikan publik tentang kesehatan mental yang membongkar stigma “kurang iman” atau “lemah” yang melekat pada orang dengan depresi. Edukasi ini penting agar difabel bisa mencari bantuan tanpa takut dihakimi.
Layanan kesehatan mental pun harus inklusif, dengan fasilitas yang aksesibel, tenaga profesional yang terlatih, dan pendekatan yang memahami konteks kehidupan difabel. Dunia kerja juga harus berubah, membuka pintu bagi difabel bukan hanya karena kewajiban hukum, melainkan karena pengakuan bahwa mereka mampu dan berhak. Kesempatan kerja bukan hanya soal penghasilan, melainkan juga soal harga diri dan kesehatan mental. Komunitas suportif juga memegang peran penting.
Banyak difabel menemukan kekuatan dalam komunitas yang saling memahami, berbagi pengalaman, dan saling menopang. Ruang-ruang ini perlu diperluas, didukung, dan difasilitasi agar menjadi tempat berbagi tanpa stigma. Dan di luar semua itu, setiap kita sebagai individu punya peran. Hal sederhana seperti menghargai, tidak meremehkan, dan tidak memperlakukan difabel dengan kasihan bisa memberi dampak besar. Dukungan sosial adalah penyangga utama kesehatan mental.
Merawat Kesehatan Mental Difabel
Tulisan ini lahir dari pertemuan dengan keputusasaan seorang teman difabel. Tetapi lebih dari itu, pertemuan itu menjadi refleksi bahwa isu difabel bukan hanya soal akses fisik, melainkan juga soal jiwa. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap fakta bahwa banyak difabel bergulat dengan depresi, kecemasan, bahkan keinginan bunuh diri.
Sebagai masyarakat, kita punya pilihan, apakah terus membiarkan mereka merasa sendirian, atau mulai bergerak menciptakan ruang inklusif? Bagiku, jawabannya jelas. Kita perlu menjadikan kesehatan mental difabel sebagai bagian dari publik, kebijakan negara, dan juga perhatian pribadi.
Aku percaya, setiap manusia ingin merasa berarti. Dan tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tidak ada satu pun yang merasa hidupnya tidak layak dijalani. Difabel bukan sekadar “inspirasional” atau “beban”, mereka adalah manusia penuh, yang berhak hidup dengan martabat, kesempatan, dan kesehatan mental yang terjaga.
Pengalaman itu menjadi pengingat abadi bagiku bahwa terkadang, hidup seseorang bisa diselamatkan hanya dengan keberanian untuk hadir. Tetapi di atas itu semua, kita membutuhkan perubahan besar agar difabel tidak lagi dibiarkan tenggelam dalam kesepian dan keputusasaan.
Mari kita mulai dari hal kecil, mendengar, memahami, menghargai. Dari sana, semoga lahir sistem yang lebih adil, lebih ramah, dan lebih manusiawi. Karena dunia yang sehat adalah dunia yang tidak meninggalkan siapa pun, termasuk mereka yang difabel. []