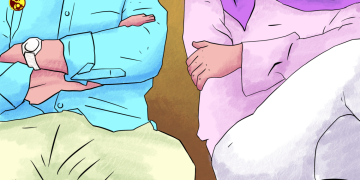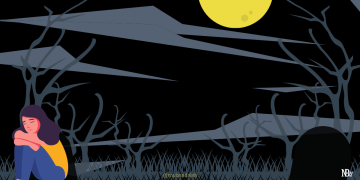Mubadalah.id – Setiap anak dilahirkan unik, dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda. Ada anak yang tumbuh dengan perkembangan yang sesuai tahap usianya, ada pula yang membutuhkan perhatian khusus. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah mereka yang mengalami hambatan dalam perkembangan fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Kelompok ini mencakup anak dengan disabilitas, tunanetra, tunarungu, ADHD, down syndrome, hingga mereka yang mengalami gangguan belajar spesifik.
Sayangnya, di tengah wacana pembangunan pendidikan nasional, anak-anak ini kerap terpinggirkan. Padahal, pendidikan bagi ABK adalah jalan untuk membangun kemandirian, melatih keterampilan sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, dan membuka peluang masa depan yang lebih baik.
Bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan berfungsi lebih dari sekadar akademik. Pertama, pendidikan membentuk kemandirian agar mereka mampu mengurus diri sendiri tanpa selalu bergantung pada orang lain.
Kedua, pendidikan melatih keterampilan sosial, membuat mereka lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Ketiga, pendidikan membangun harga diri: anak-anak ini belajar bahwa mereka berharga, mampu berkarya, dan layak dihargai.
Keempat, pendidikan membuka pintu masa depan, karena dengan keterampilan yang tepat, mereka bisa bekerja, berkarya, bahkan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas.
Terlebih, konstitusi kita sebenarnya sudah memberikan jaminan. Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan.
Konvensi Hak Anak pun mengamanatkan hal serupa. Artinya, tidak ada pengecualian. Anak berkebutuhan khusus sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai kondisi dan potensinya.
Sayangnya, praktik di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan amanat hukum tersebut. Banyak ABK masih kesulitan mengakses pendidikan layak karena keterbatasan sekolah, tenaga pendidik, maupun pemahaman masyarakat.
Inklusi: Jalan Menuju Keadilan
Di sinilah pentingnya gagasan pendidikan inklusif yaitu sistem pendidikan yang dirancang untuk semua anak, tanpa terkecuali.
Bahkan, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak lain dalam kelas reguler dengan penyesuaian kurikulum, metode, dan fasilitas. Tujuannya jelas: menciptakan ruang belajar yang aman, ramah, dan setara bagi semua.
Melalui pendidikan inklusif, anak-anak non-ABK bisa belajar tentang empati, toleransi, dan persaudaraan. Sementara ABK belajar bahwa mereka diterima apa adanya, tanpa stigma dan diskriminasi.
Dalam webinar bertajuk “Kemerdekaan Hak untuk Pendidikan Inklusif” yang diselenggarakan Mubadalah.id pada 21 Agustus 2025 lalu, Alifa, salah satu narasumber, menegaskan: “Pendidikan inklusif berarti memastikan setiap anak memiliki kesempatan belajar yang sama. Bukan hanya masuk sekolah, tapi benar-benar bisa belajar dengan nyaman, bermakna, dan berkontribusi di lingkungannya.”
Pernyataan ini penting untuk kita pikirkan. Karena selama ini sistem pendidikan bagi ABK masih terbagi ke dalam tiga model.
Pertama, pemisahan, yakni anak berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah khusus (SLB). Kedua, integrasi, di mana mereka masuk sekolah umum tetapi dengan sedikit adaptasi.
Ketiga, inklusi, yang menekankan agar ABK belajar di sekolah umum dengan penyesuaian menyeluruh sesuai kebutuhan. Dari ketiga model tersebut, inklusi adalah yang paling adil dan sesuai dengan semangat kesetaraan.
Tantangan Pendidikan Inklusif
Tentu, mewujudkan pendidikan inklusif bukan perkara mudah. Kita masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan guru pendamping khusus, minimnya sarana prasarana, hingga stigma masyarakat yang masih menganggap ABK sebagai “beban” ketimbang aset bangsa.
Padahal, banyak ABK memiliki potensi luar biasa. Ada yang unggul di bidang seni, olahraga, teknologi, bahkan kewirausahaan. Hanya saja, mereka membutuhkan pendekatan berbeda. Dengan dukungan pendidikan yang tepat, potensi itu bisa berkembang, bukan justru terpendam.
Lebih dari itu, pendidikan inklusif bukan hanya soal fasilitas. Ia adalah soal paradigma. Apakah kita, sebagai bangsa, benar-benar percaya bahwa setiap anak berhak atas kesempatan yang sama? Ataukah kita hanya menjadikan pendidikan inklusif sebagai jargon tanpa komitmen nyata?
Maka dengan begitu, pendidikan inklusif bukan belas kasihan, melainkan hak. Karena pada dasarnya semua anak adalah berbeda, tetapi semua berhak untuk tumbuh dan belajar. Ketika satu anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan, sejatinya kita sedang membangun peradaban yang lebih manusiawi.
Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang adil. Ia tidak menyingkirkan yang lemah, tetapi justru merangkul semua perbedaan. Pendidikan inklusif adalah jalan menuju masyarakat semacam itu. Kini, pertanyaannya: apakah kita siap membuka ruang belajar yang benar-benar setara bagi semua anak? []