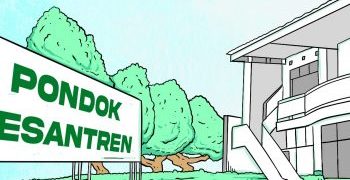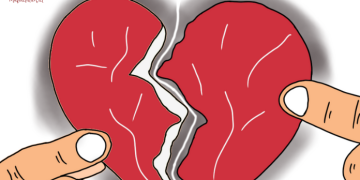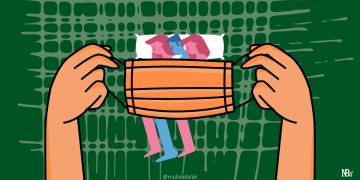Mubadalah.id – Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memainkan peran besar dalam membentuk moral, spiritualitas, dan kebangsaan masyarakat. Ia menjadi ruang pembelajaran, pengabdian, dan pengembangan karakter yang mengakar pada nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.
Namun, dalam era industri hiburan modern, wajah pesantren kerap terseret ke ruang representasi yang keliru. Media massa, terutama televisi dan konten daring. Mereka sering kali membingkai pesantren sebagai tempat yang “unik” secara komikal, penuh kelucuan, atau bahkan menakutkan—bukan sebagai pusat pendidikan yang berwibawa dan berperadaban.
Kasus terbaru yang melibatkan Trans7 menjadi contoh nyata bagaimana framing media dapat menimbulkan persepsi yang salah. Dalam salah satu tayangan program hiburan, terdapat penggambaran pondok pesantren yang dikaitkan dengan tindakan menyimpang dan kekerasan simbolik. Salah satu pesantren besar, Pondok Pesantren Lirboyo, bahkan terseret dalam pemberitaan karena framing yang tidak akurat.
Tayangan tersebut menimbulkan kegaduhan publik, memunculkan kritik dari berbagai kalangan, dan memaksa pihak stasiun televisi untuk meminta maaf. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya lembaga pendidikan Islam diperlakukan secara serampangan di ruang media yang lebih mengutamakan sensasi ketimbang akurasi dan etika.
Framing Media dan Distorsi Citra Pesantren
Dalam teori komunikasi, framing adalah cara media membingkai realitas dengan menonjolkan aspek tertentu dan menutupi yang lain. Ketika Trans7 menayangkan konten yang menyiratkan pesantren sebagai tempat tindakan kekerasan atau pelanggaran moral, sesungguhnya media sedang membentuk realitas sosial baru di benak publik. Framing semacam ini berpotensi menciptakan stigma negatif, terutama bagi masyarakat yang tidak pernah berinteraksi langsung dengan kehidupan pesantren.
Padahal, pesantren seperti Lirboyo memiliki sejarah panjang sebagai pusat keilmuan Islam, tempat lahirnya para ulama dan tokoh bangsa. Namun media hiburan sering kali mengabaikan kompleksitas tersebut dan memilih narasi yang lebih sensasional.
Akibatnya, pesantren direduksi menjadi sekadar latar budaya atau bahan lelucon. Media gagal memahami bahwa pesantren bukan hanya ruang belajar agama, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial, pendidikan karakter, dan inovasi keislaman berbasis kemandirian.
Kesalahan framing semacam itu tidak sekadar soal teknis jurnalistik, tetapi juga persoalan etika. Media memiliki tanggung jawab moral untuk menampilkan realitas secara proporsional, terutama jika menyangkut lembaga keagamaan yang menjadi bagian penting dari struktur sosial Indonesia. Dengan memilih sudut pandang yang salah, media justru memperkuat stereotip negatif dan memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam.
Narasi Hiburan dan Komodifikasi Religiusitas
Kasus Trans7 juga memperlihatkan bagaimana industri hiburan mengkomodifikasi religiusitas. Dalam logika kapitalisme media, nilai-nilai keagamaan bisa diubah menjadi komoditas tontonan. Kehidupan pesantren, dengan segala kekhasan simbol dan bahasanya, sering diolah menjadi bahan visual yang menjual: ada humor, ada konflik, ada keanehan yang dianggap menarik bagi penonton. Namun di balik tawa dan sensasi, nilai-nilai luhur pesantren dikorbankan.
Komodifikasi ini melahirkan narasi keliru: seolah pesantren identik dengan kekerasan, ketertinggalan, atau praktik aneh yang tidak rasional. Padahal, pesantren justru menjadi pelopor moderasi beragama, pusat kebijaksanaan sosial, dan basis dakwah yang damai.
Media yang hanya mengejar “rating” dan “engagement” tanpa riset dan empati pada realitas sosial telah menjadikan simbol keagamaan sebagai bahan dagangan. Dalam konteks ini, Trans7 tidak hanya melakukan kesalahan editorial, tetapi juga melanggar tanggung jawab etis media dalam menjaga kehormatan nilai-nilai religius masyarakat.
Namun, kritik terhadap media tidak cukup hanya berupa kecaman. Pesantren juga perlu bertransformasi menjadi subjek aktif dalam membangun narasi tandingan. Melalui kanal YouTube, podcast, atau film dokumenter, pesantren bisa menunjukkan kehidupan santri yang disiplin, ilmiah, dan kreatif.
Representasi alternatif semacam ini penting agar publik tidak hanya mengenal pesantren dari media arus utama yang bias, tetapi juga dari suara pesantren itu sendiri.
Membangun Literasi Media dan Representasi Kritis
Kasus Trans7 seharusnya menjadi pelajaran penting untuk memperkuat literasi media di kalangan masyarakat dan lembaga pendidikan Islam. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua tayangan televisi mencerminkan kebenaran sosial.
Literasi media membantu publik agar tidak mudah termakan oleh framing yang menyesatkan. Sementara itu, pesantren perlu melatih para santri untuk mampu membaca dan memproduksi media secara kritis—menjadi content creator yang membawa pesan dakwah dan pendidikan dengan cara yang segar namun tetap bermartabat.
Selain itu, kita memerlukan dialog yang lebih intens antara kalangan media dan lembaga pesantren. Kolaborasi semacam ini bisa menghasilkan tayangan edukatif yang menggambarkan inovasi dan peran pesantren di bidang sosial, ekonomi, hingga lingkungan.
Misalnya, kisah pesantren yang mengembangkan pertanian organik, program kewirausahaan santri, atau gerakan literasi kitab kuning yang mendunia. Dengan cara ini, media tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga wahana pembelajaran publik yang mencerdaskan.
Pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga perlu memperkuat regulasi tentang etika representasi keagamaan di media. Penayangan yang menyinggung simbol atau lembaga keagamaan harus disertai pertimbangan kultural dan konsultasi dengan pihak yang relevan. Bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk memastikan media menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab.
Mengembalikan Kehormatan Pesantren di Ruang Publik
Kasus salah framing pesantren oleh Trans7 menjadi cermin bahwa dunia hiburan masih sering gagal memahami kompleksitas lembaga keagamaan. Kesalahan semacam ini bukan hanya melukai marwah pesantren seperti Lirboyo, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap media. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran baru: bahwa pesantren bukan bahan hiburan, melainkan sumber nilai, ilmu, dan inspirasi sosial.
Media seharusnya menjadi jembatan antara pesantren dan masyarakat, bukan dinding yang menimbulkan prasangka. Dengan membangun literasi media, memperkuat narasi tandingan, dan menegakkan etika penyiaran, kita dapat mengembalikan pesantren pada posisinya yang terhormat—sebagai benteng moral bangsa dan pelita peradaban Islam Nusantara. []