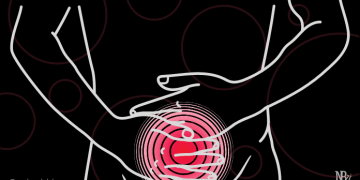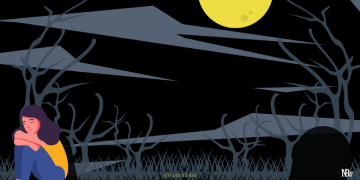Mubadalah.id – Di era digital yang serba cepat ini, membaca buku kian tergeser oleh aktivitas scrolling di media sosial. Jempol kita jauh lebih sibuk menggulir layar TikTok atau Instagram dibanding membuka buku. Padahal, membaca buku bukan hanya memperluas wawasan, melainkan juga menajamkan daya nalar dan kepekaan berpikir.
Kesadaran akan pentingnya membaca inilah yang terus diingatkan melalui berbagai momentum literasi dunia. Salah satunya adalah peringatan Hari Perpustakaan Sekolah Internasional (International School Library Day) yang jatuh setiap tanggal 18 Oktober.
Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh Dr. Blanche Wolls, Presiden International Association of School Librarianship (IASL), pada 18 Oktober 1999.
Di Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) turut memperingati momentum ini sebagai upaya menegaskan kembali pentingnya budaya literasi di sekolah. Peringatan tersebut juga menjadi pengingat akan peran vital perpustakaan sebagai ruang belajar yang memperkaya pengetahuan dan menumbuhkan minat baca.
Namun, peringatan hari literasi kerap berlalu begitu saja, tanpa perubahan berarti dalam perilaku membaca masyarakat.
Krisis Minat Baca
Berbagai laporan menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah. Data yang sering dikutip dari UNESCO menyebutkan bahwa minat baca Indonesia hanya 0,001% artinya, dari 1.000 orang, hanya satu yang benar-benar membaca secara aktif.
Data tersebut seharusnya menyadarkan kita bahwa membaca belum benar-benar menjadi kebiasaan utama di negeri ini.
Bahkan, hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menyebutkan, skor literasi membaca pelajar Indonesia masih jauh di bawah rata-rata internasional. Persentase siswa yang mencapai tingkat kecakapan minimum pun masih rendah, menandakan bahwa banyak pelajar kita belum terbiasa memahami teks secara kritis dan mendalam.
Sementara survei domestik dari GoodStats tahun 2025 menunjukkan, hanya 20,7% responden yang membaca buku setiap hari. Itu berarti hanya satu dari lima orang Indonesia yang memiliki kebiasaan membaca secara rutin. Data ini memperlihatkan bahwa kebiasaan membaca belum terinternalisasi dalam keseharian masyarakat.
Padahal, di tengah banjir informasi digital, kemampuan membaca kritis menjadi sangat penting. Masyarakat yang tidak terbiasa membaca akan mudah terseret arus informasi palsu (hoaks), bahkan kehilangan daya berpikir kritis.
Kalah dengan Gawai
Meskipun begitu, namun kita semua patut menyadari bahwa sumber utama pengetahuan bukan lagi buku, melainkan video pendek berdurasi 30 detik. Platform seperti TikTok dan YouTube memang menawarkan hiburan cepat dan ringan. Namun, di balik kemudahannya, ada risiko besar yaitu budaya instan yang menumpulkan intelektual mereka.
Ketika pengetahuan disajikan dalam potongan video singkat, kemampuan manusia untuk merenung dan berpikir mendalam ikut memudar. Buku yang seharusnya menjadi jendela dunia berubah menjadi barang asing di rak-rak rumah.
Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, terutama bagi generasi muda. Sebab, membaca bukan sekadar soal menambah pengentahuan, melainkan melatih kemampuan memahami perspektif orang lain sesuatu yang tak bisa digantikan oleh video pendek.
Joglo Baca
Di tengah situasi tersebut, muncul berbagai inisiatif literasi yang mencoba menghidupkan kembali semangat membaca dengan cara yang kreatif. Salah satunya datang dari lingkungan Sarjana Ulama Perempuan Indonesia (SUPI) di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.
Gerakan ini bernama Joglo Baca, sebuah kegiatan literasi yang berlangsung setiap malam minggu. Alih-alih menghabiskan malam dengan malmingan, para mahasantri SUPI memilih untuk malbukuan — membaca, berdiskusi, dan belajar bersama.
Namun, Joglo Baca bukan sekadar kegiatan membaca bersama tetapi membentuk komunitas sesuai minat baca seperti hukum, sastra, psikologi, hingga pemikiran Karl Marx. Setiap minggu, satu orang mendapat giliran mempresentasikan isi buku yang mereka bacanya, lalu peserta lain menanggapi dan mengajukan pertanyaan.
Suasana ini membuat membaca tidak lagi terasa membosankan, melainkan hidup, menyenangkan, dan penuh pertukaran ide. Lebih dari sekadar aktivitas akademik, Joglo Baca menjadi ruang menemukan buku apa yang disukai, apa yang dipahami, dan bagaimana ilmu yang dibaca bisa dibagikan kembali kepada orang lain.
Inisiatif seperti Joglo Baca menunjukkan bahwa membaca bisa menjadi kegiatan sosial yang produktif dan inklusif. Ia mematahkan anggapan bahwa membaca adalah kegiatan yang membosankan. Sebaliknya, membaca bisa menjadi pintu menuju dialog, kolaborasi, dan kebahagiaan intelektual.
Literasi Sebagai Gaya Hidup
Kita perlu memandang membaca sebagai gaya hidup. Negara-negara dengan tingkat literasi tinggi seperti Finlandia atau Jepang, tidak hanya memiliki perpustakaan lengkap. Tetapi juga masyarakat yang menjadikan membaca sebagai bagian dari keseharian.
Di Indonesia, upaya seperti Joglo Baca perlu mendapat dukungan luas baik dari lembaga pendidikan, pemerintah, maupun komunitas. Sekolah dan kampus seharusnya tak hanya mengajarkan cara membaca teks, tetapi juga menciptakan ekosistem yang membuat membaca terasa menyenangkan.
Perpustakaan, baik di sekolah maupun di masyarakat, harus direvitalisasi. Ia tak cukup menjadi tempat menyimpan buku, tetapi juga ruang berdialog dan berdiskusi.
Oleh sebab itu, membaca adalah tindakan perlawanan terhadap arus instan yang serba cepat. Ia menuntut kesabaran, ketekunan, dan keingintahuan — tiga hal yang makin langka di era digital.
Di tengah budaya scrolling, mari kita bangun kembali budaya reading. Karena bangsa besar tidak hanya ditandai oleh jumlah pengguna internetnya. Tetapi oleh seberapa banyak warganya yang mau berhenti sejenak, membuka buku, dan membacanya. []