Mubadalah.id – Pada Minggu pagi, 9 November 2025, pukul 08.00 WIB atau pukul 12.00 di Sydney, Hijroatul Maghfiroh Mahasiswa program magister di Macquarie University ikut menandatangani Petisi Bersama Penolakan Wacana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Baginya, penolakan ini adalah bentuk perlawanan atas ingatan yang coba dipelintir atas kekuasaan, kekerasan, dan kerusakan yang diwariskan Orde Baru.
“Ini sangat personal,” katanya. Ia terdiam sejenak, seolah menahan luapan emosi yang sudah lama mengendap.
Di awal 2000-an, Firoh masih menjadi aktivis muda yang terlibat dalam advokasi korban kekerasan 1965–1966. Bersama Sarekat Indonesia dan Komnas Perempuan, ia mendampingi perempuan korban penyiksaan militer — para ibu, nenek, dan gadis muda.
Ia masih ingat betul cerita-cerita para korban kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan penahanan tanpa proses hukum. Semua itu, katanya, tak mungkin terjadi tanpa restu dan komando dari puncak kekuasaan Presiden Soeharto.
Maka, ketika hari ini ada pejabat yang dengan gagah menyatakan “Soeharto tidak terlibat dalam tragedi 65”, baginya itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan kemanusiaan.
“Orang-orang yang saya temui adalah saksi hidup. Mereka menanggung luka seumur hidup karena kekuasaan yang Soeharto jalankan tanpa nurani,” ujarnya.
Dosa Ekologis Soeharto
Sekitar satu dekade setelah Soeharto tumbang, Firoh menapaki jalur advokasi baru yaitu isu lingkungan. Pada tahun 2010, ia mulai mendampingi masyarakat di Kalimantan Timur — mereka yang hidup di sekitar tambang dan bekas tambang. Di sana, ia melihat sendiri bagaimana kerakusan ekonomi Soeharto menindas kehidupan rakyat kecil.
“Saya mendengar sendiri dari seorang kiai setempat,” kisahnya. “Beliau bilang, ‘Orang-orang Jakarta lewat sini dengan mobil besar, mereka bawa kekayaan kami, tapi kami yang tinggal di sini hanya dapat bencana.’”
Kalimat itu menancap di ingatan Firoh, menjadi pengingat bahwa ketimpangan ekologis selalu beriring dengan ketimpangan kekuasaan masa Soeharto.
Soeharto mungkin telah tiada, tapi jejak kebijakannya masih hidup bersama penderitaan rakyat. Dari penelusuran Firoh, kerusakan ekologis di Indonesia tak bisa kita lepaskan dari kebijakan Orde Baru yang mengobral izin eksploitasi hutan dan tambang.
Sejak 1967 — tahun-tahun awal kekuasaannya, Soeharto membuka lebih dari 62 juta hektar hutan untuk pengusahaan hutan (HPH). Sebanyak 585 perusahaan swasta dan BUMN mendapat izin konsesi. Mayoritas di antaranya dimiliki oleh kroni, keluarga, dan jaringan bisnis yang bernaung di bawah perlindungan politik Orde Baru.
Indonesia kemudian menjadi pengekspor kayu lapis tropis terbesar di dunia pada akhir 1980-an. Ekspor itu, katanya, menyisakan kerusakan yang sangat massif seperti deforestasi, banjir bandang, hilangnya biodiversitas, dan penggusuran masyarakat adat.
Data Global Forest Watch menunjukkan, sejak 2001 Indonesia telah kehilangan lebih dari 30 juta hektar tutupan pohon, atau sekitar 19% dari total hutan.
Bersama Brasil dan Kongo, Indonesia kini termasuk tiga negara dengan kehilangan hutan hujan primer terbesar di dunia.
“Dari situ saya sadar, kerusakan lingkungan hari ini bukanlah kebetulan, Ini warisan sistemik dari kebijakan Orde Baru,” tegasnya.
Kolonialisme Ekologi
Firoh menyebut fenomena ini sebagai bentuk “kolonialisme ekologis”. Istilah itu muncul ketika ia menelusuri kontrak karya pertama antara pemerintah Soeharto dan Freeport Sulphur Company asal Amerika Serikat pada tahun 1967 — dua tahun sebelum Papua resmi bergabung dengan Indonesia.
Kontrak itu memberi hak istimewa penuh kepada perusahaan asing untuk menambang di tanah Papua, tanpa persetujuan rakyat yang tanahnya mereka ambil.
Padahal, dampaknya sangat terasa sampai sekarang, seperti pencemaran sungai, peningkatan logam berat, hilangnya tanah adat, dan marginalisasi masyarakat Amungme dan Kamoro.
“Kontrak Freeport adalah simbol paling telanjang dari bagaimana kedaulatan lingkungan ia korbankan demi modal asing dan kroni kekuasaan,” ujarnya tegas.
Sistem patronase yang Orde Baru bangun di sektor sumber daya alam, kata Firoh, masih bertahan hingga kini. Nama-nama besar seperti keluarga Cendana, kroni bisnis, dan perusahaan-perusahaan lama masih mendominasi.
“Bahkan proyek reboisasi yang dulu digembar-gemborkan Soeharto sebagai upaya pelestarian hutan seperti di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur ternyata menyimpan ironi,” katanya.
Bukit Soeharto, yang seluas 61.850 hektar dan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, kini justru rusak oleh aktivitas tambang dan perambahan.
“Nama Soeharto di sana seolah simbol ekologis yang menipu. Di balik jargon ‘pembangunan hijau’, ada eksploitasi yang terus mereka langgengkan.”
Belum lagi reklamasi Teluk Benoa di Bali oleh Tommy Soeharto dan proyek-proyek besar lainnya yang mengabaikan keadilan ekologis.
“Semua itu adalah rantai panjang dari dosa ekologis yang diwariskan, dari ayah ke anak, dari kekuasaan ke bisnis,” ujar Firoh.
Melawan Lupa
Bagi Firoh, penolakan terhadap gelar Pahlawan untuk Soeharto adalah upaya mempertahankan ingatan bahwa pembangunan tak boleh dibangun di atas darah dan hancurnya alam.
“Bagaimana mungkin seseorang yang meninggalkan jutaan korban manusia dan alam kita sebut pahlawan?,” jelasnya.
Dua puluh lima tahun setelah Orde Baru tumbang, luka itu belum sembuh. Sungai-sungai masih tercemar dan hutan masih terbakar. Bahkan banyak masyarakat adat masih terusir.
“Menolak lupa bukan berarti hidup di masa lalu. Tapi memastikan agar masa depan tidak diulang dengan kebohongan yang sama,” tutup Firoh. []








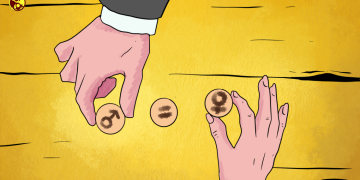
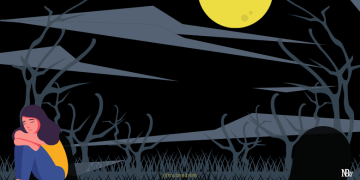


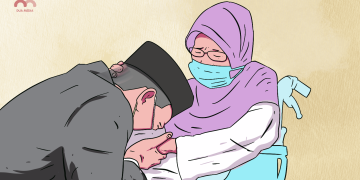

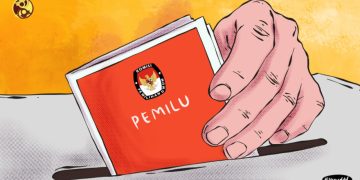































Comments 1