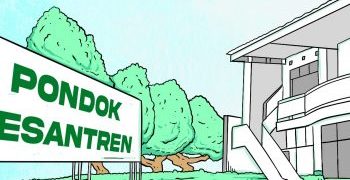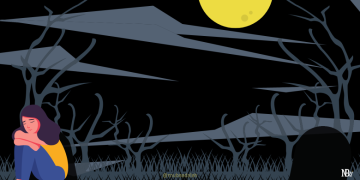Mubadalah.id – Beberapa waktu yang lalu, seorang pelaku pembunuhan berencana yakni Ferdi Sambo divonis dengan hukuman mati. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya hakim memutuskan bahwa Ferdi Sambo tidak dihukum mati, tetapi akan mendapat vonis penjara seumur hidup.
Hukuman mati selalu menjadi isu yang memicu perdebatan. Perdebatan yang muncul adalah apakah mengambil nyawa pelaku kejahatan demi keadilan dapat dibenarkan? Apakah negara memiliki hak moral untuk menentukan siapa yang berhak hidup dan siapa yang harus mati?
Banyak negara yang masih mempertahankan hukuman mati. Alasannya adalah sebagai bentuk balasan atas kejahatan berat. Namun Gereja Katolik, melalui perjalanan panjang refleksi moralnya, memilih berdiri pada sisi yang berbeda. Gereja dengan tegas menolak hukuman mati dalam kondisi apa pun.
Penolakan ini bukan sekadar sikap ideologis, melainkan buah dari keyakinan mendasar bahwa hidup manusia adalah karunia Allah yang tak boleh direnggut oleh siapa pun. Dalam Hukuman mati tidak hanya menyangkut pelaku, tetapi juga keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, serta struktur sosial yang sering kali tidak adil.
Martabat Manusia: Titik Berangkat Ajaran Gereja
Gereja Katolik selalu mendasarkan ajaran moralnya pada keyakinan bahwa manusia merupakan ciptaan menurut gambar dan rupa Allah (Kej 1:27). Artinya, setiap manusia, tanpa memandang dosa, kesalahan, atau kondisi hidupnya memiliki martabat yang sama
Paus Yohanes Paulus II dalam Evangelium Vitae menegaskan bahwa hidup manusia adalah “sakral” dan “tidak tersentuh”. Gereja memang pernah membolehkan hukuman mati secara sangat terbatas pada masa-masa ketika negara belum memiliki kemampuan melindungi masyarakat tanpa menghilangkan nyawa pelaku. Namun perkembangan moral dan teknologi hukum membuat alasan itu tidak lagi relevan.
Pada tahun 2018, Paus Fransiskus memperbarui Katekismus dengan pernyataan tegas. Pernyataan yang terbaru adalah bahwa hukuman mati dalam bentuk apapaun tidak dapat diterima (inadmissible). Hal ini berdasarkan bahwa hukuman mati menyerang martabat pribadi manusia. Dengan dasar ini, Gereja berdiri jelas bahwa kejahatan, seberat apa pun, tidak mampu menghapus nilai kehidupan seseorang.
Evolusi Ajaran Gereja: Dari Pembolehan Terbatas ke Penolakan Total
Ajaran Gereja mengenai hukuman mati bukanlah perubahan instan, tetapi hasil refleksi panjang tentang martabat manusia dan perkembangan masyarakat modern. Pada zaman dahulu, hukuman mati merupakan cara untuk mempertahankan ketertiban publik. Gereja tidak mendukungnya secara penuh, tetapi mengizinkannya ketika negara tidak memiliki pilihan lain.
Namun seiring berkembangnya sistem hukum, teknologi keamanan, dan kesadaran HAM, negara kini memiliki banyak cara melindungi masyarakat tanpa mengambil nyawa siapa pun. Di sinilah perubahan moral Gereja terjadi. Gereja akhirnya memutuskan dari membatasi hingga akhirnya menolak sepenuhnya.
Paus Fransiskus menekankan bahwa belas kasih dan pemulihan sejati tidak dapat terjadi jika dengan membalas kekerasan dengan kekerasan. Hukuman mati, apa pun alasannya, “bertentangan dengan Injil”. Pandangan ini menunjukkan bahwa Gereja semakin menyadari bahwa relasi manusia harus ada atas rasa kesalingan, bukan pembalasan.
Ketidakadilan Struktural: Perspektif Humanis dan Mubadalah
Masalah terbesar dari hukuman mati bukan hanya soal moral, tetapi juga soal struktur sosial yang timpang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati sering jatuh lebih berat pada mereka orang miskin, dan mereka yang tidak memiliki akses bantuan hukum memadai. Selain itu ketimpangan juga akan terjadi kepada mereka kelompok minoritas atau mereka yang lebih rentan dalam sistem peradilan.
Dalam banyak kasus, hukuman mati mencerminkan bias sosial, bukan keadilan yang sejati. Pendekatan dengan prinsip kesalingan, mengajak kita untuk melihat semua pihak sebagai subjek. Subjek tersebut adalah korban kejahatan, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta masyarakat.
Semua memiliki luka, semua memiliki martabat, dan semua membutuhkan keadilan yang tidak merendahkan kemanusiaan. Dengan demikian, hukuman mati tidak menyelesaikan luka sosial, ia hanya memotong satu rantai tanpa memulihkan apa pun.
Peran Gereja: Membela Kehidupan di Tengah Ketidakpastian
Salah satu alasan Gereja menolak hukuman mati adalah karena Gereja mengedepankan keadilan restoratif, bukan retributif. Keadilan restoratif sendiri berfokus pada pemulihan korban, pertobatan pelaku, rekonsiliasi sosial, dan penyembuhan komunitas.
Dalam banyak kasus, hukuman mati justru menutup kemungkinan pelaku untuk berubah dan bertobat. Ia memutus proses perbaikan diri serta menghilangkan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk mencapai penyembuhan yang lebih manusiawi. Gereja percaya bahwa manusia dapat berubah. Bahkan orang yang paling berdosa sekalipun dapat bertobat, dan pertobatan itu memiliki nilai moral dan spiritual yang sangat tinggi.
Gereja bukan hanya membuat pernyataan moral. Di banyak negara, Gereja hadir mendampingi terpidana mati seperti memberi penguatan rohani, menyediakan pendamping hukum, membela hak dasar mereka, bahkan mendampingi keluarga korban. Gereja juga mendesak negara untuk meninjau ulang sistem hukum yang membuka ruang bagi eksekusi.
Di sisi lain, Gereja tidak menyepelekan penderitaan korban. Pendampingan kepada keluarga korban menjadi bagian penting dari pastoral kasih. Pada bagian ini, Gereja harus mendengarkan, menyembuhkan trauma, dan menyediakan jalan rekonsiliasi bila memungkinkan. Dengan pendekatan ini, Gereja ingin membangun kultur kehidupan bahwa ada sebuah cara pandang yang menolak kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk kekerasan yang negara buat.
Hukuman Mati Tidak Sejalan dengan Martabat Manusia
Pandangan Gereja tentang hukuman mati sangat jelas. Kehidupan manusia tidak boleh direnggut, bahkan dari seseorang yang telah melakukan kejahatan berat. Hukuman mati tidak membawa pemulihan, tetapi hanya memperdalam luka sosial. Gereja mengajak masyarakat untuk membangun keadilan yang memulihkan, bukan membalas. Gereja menanamkan keadilan yang menegakkan martabat semua pihak, bukan memperpanjang lingkaran kekerasan.
Pada akhirnya, perjuangan menolak hukuman mati bukan hanya persoalan ajaran Gereja, tetapi persoalan kemanusiaan. Mengakui nilai hidup setiap orang dan menjaga agar dunia tidak menjawab kekerasan dengan kekerasan yang lebih besar. []