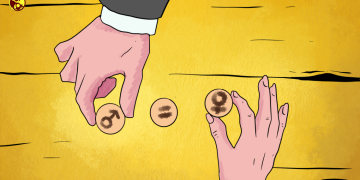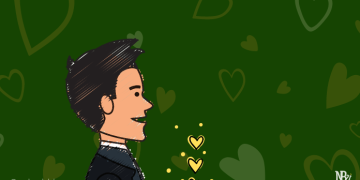Mubadalah.id – Sudah lebih dari tiga pekan bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, meninggalkan luka yang tak mudah disembuhkan untuk banyak keluarga. Di berbagai kanal media sosial, kita menyaksikan potongan kehidupan pascabencana yang terasa begitu dekat sekaligus menyayat.
Dalam sebuah video Instagram @havizadinata, seorang anak tersenyum sambil berkata, “Besok bawa baju untuk aku ya.” Permintaan sederhana itu menyisakan keheningan panjang, di usia ketika anak-anak seharusnya memilih warna dan tokoh kartun, ia justru belajar bahwa memiliki pakaian untuk esok hari tak lagi pasti.
Video lain dari TikTok @aniisitumurong, dua anak menatap rumahnya yang hancur dan berkata pelan, “Rumahku gak ada, rumahku sudah hancur.” Tak ada ledakan emosi, hanya kehilangan yang terlalu besar untuk tubuh sekecil mereka.
Video-video tersebut tidak sedang mempertontonkan ketangguhan sebagai tontonan heroik, melainkan memperlihatkan bagaimana anak-anak terpaksa tumbuh di tengah ketidakpastian yang seharusnya belum menjadi bagian dari dunia mereka. Sehingga menjadi penting untuk melakukan upaya trauma healing bagi anak-anak korban bencana di Sumatra.
Bencana mungkin sering kita pahami sebagai kerusakan fisik. Namun bagi anak-anak, yang runtuh adalah rasa aman. Mereka kehilangan sekolah, ruang bermain, dan rutinitas yang menenangkan. Karena itu, bantuan tak cukup berhenti pada tenda dan makanan, ada kebutuhan lain yang lebih genting yakni pemulihan psikologis. Trauma healing menjadi kebutuhan bukan pelengkap bantuan kemanusiaan.
Luka yang Jarang Terlihat
Di pos pengungsian, tidak semua luka tampak di permukaan. Ada anak yang tiba-tiba diam, menempel pada orangtuanya, menolak bicara. Lalu ada yang bangun ketakutan karena suara hujan, atau kembali ngompol karena kecemasan yang tak mampu mereka namai. Ada pula yang tampak baik-baik saja, hanya untuk kemudian mudah marah atau sulit fokus ketika kegiatan belajar darurat dimulai.
Reaksi seperti ini bukan karakter, bukan nakal, apalagi manja. Ini adalah respons biologis tubuh anak ketika berhadapan dengan ancaman yang terlalu besar untuk mereka proses sendirian.
Psikolog Annette La Greca mengatakan bahwa tanpa intervensi psikososial yang tepat, anak-anak lebih berisiko mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), kecemasan, dan depresi setelah bencana. Dan efek ini bisa mengikuti mereka hingga dewasa.
Kenapa Anak Lebih Rentan?
Anak hidup dalam dunia yang terbangun oleh orang dewasa. Ketika dunia runtuh, rumah hilang, sekolah rusak, orangtua sendiri kebingungan memulihkan hidup, anak kehilangan fondasinya. Di banyak lokasi banjir di Sumatera, sekolah berubah fungsi menjadi dapur umum atau gudang logistik. Guru pun menjadi relawan dadakan, bukan lagi sosok yang memegang ritme belajar dan bermain.
Untuk anak perempuan, kerentanannya sering berlipat. Mereka kerap diminta menjaga adik di pengungsian, kehilangan ruang aman untuk bermain, atau mendapat pengawasan berlebih karena dianggap lebih berisiko. Anak laki-laki menghadapi tekanan berbeda, dorongan untuk kuat dan tidak menangis, padahal mereka sama-sama trauma.
Bencana memperlebar ketimpangan yang sudah ada. Anak-anak menjadi pihak yang paling cepat merasakan retaknya struktur itu.
Trauma Healing Bukan Sekadar Bicara
Kita sering membayangkan trauma healing sebagai sesi konsultasi formal. Padahal, untuk konteks kebencanaan, pemulihan psikologis anak justru kerap dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana.
Trauma healing menjadi proses untuk membantu anak memulihkan rasa aman, mengolah pengalaman traumatis, dan membangun kembali kemampuan mereka untuk merasa tenang, percaya, dan berfungsi dalam keseharian. Hadirnya orang dewasa yang memastikan anak merasa aman, didengar, dan ditemani tanpa penghakiman, seperti dalam Psychological First Aid, bisa menjadi langkah awal yang penting.
Ruang bermain yang aman, permainan yang terstruktur, hingga kelas darurat dengan rutinitas sederhana bukan sekadar pengisi waktu. Ia membantu tubuh dan emosi anak perlahan mengenali kembali ritme kehidupan yang sempat runtuh.
Pemulihan ini juga tidak bisa kita bebankan pada anak seorang diri. Dukungan bagi orang tua dan guru menjadi bagian yang tak terpisahkan, sebab anak membutuhkan pendamping yang juga cukup stabil untuk hadir secara emosional. Kegiatan sederhana berbasis sekolah dan komunitas seperti ini mampu menurunkan gejala trauma secara signifikan pada anak-anak terdampak bencana.
Kalau Diabaikan, Efeknya Panjang
Ketika trauma anak tidak kita pulihkan, dampaknya bukan cuma pada hari ini. Ia memengaruhi kemampuan belajar, relasi dengan teman sebaya, dan perkembangan emosional. Bahkan, di daerah yang berulang kali terlanda banjir, generasi demi generasi bisa tumbuh dengan beban kecemasan yang terwariskan.
Kita bisa membangun kembali jembatan, jalan, dan rumah. Tapi jika anak-anak yang akan mengisi masa depan itu tumbuh dengan luka yang tidak terurus, rekonstruksi apa sebenarnya yang kita lakukan?
Apa yang Sebaiknya Dilakukan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan?
Respons cepat bencana sering terfokus pada urusan logistik. Padahal fase awal justru menjadi waktu paling menentukan untuk mencegah trauma kronis pada anak. Karena itu, layanan MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support) bagi anak perlu masuk dalam paket bantuan darurat, bukan sebagai tambahan.
Lebih lanjut, sekolah dapat kita jadikan pusat pemulihan dengan membuka kelas darurat, melatih guru Psychological First Aid, dan menekan stigma terhadap bantuan psikologis.
Di saat yang sama, peran keluarga dan komunitas perlu kita perkuat melalui pelatihan sederhana: mengenali tanda bahaya, menenangkan anak, dan memberi dukungan emosional dasar.
Negara juga perlu memastikan alokasi anggaran jangka menengah bagi anak-anak yang membutuhkan pendampingan profesional lanjutan. Ini bukan sekadar kebijakan yang baik, melainkan wujud tanggung jawab terhadap warga paling rentan, yakni anak-anak yang sedang belajar kembali merasa aman.
Menutup Luka, Memulihkan Masa Depan
Anak-anak mungkin tidak punya bahasa untuk menjelaskan traumanya, tapi tubuh dan perilaku mereka sudah bicara lebih dulu. Memberi mereka trauma healing berarti memberi mereka kesempatan untuk tetap menjadi anak-anak, bukan penyintas kecil yang menelan semuanya sendirian.
Pemulihan pascabencana tidak hanya soal membangun kembali rumah, tetapi membangun kembali rasa aman. Dan di setiap bencana, anak selalu menjadi pusat dari masa depan itu. Jika kita memulihkan mereka, kita sedang memulihkan Sumatra, dan mungkin, memulihkan kemanusiaan kita sendiri. []