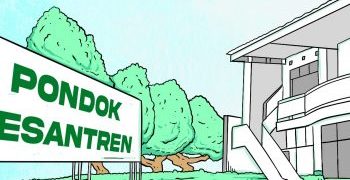Mubadalah.id – Jagat media sosial akhir-akhir ini tengah terasa panas sekali sejak terjadi peristiwa runtuhnya bangunan musala dari Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran, Sidoarjo. Akibat fenomena tersebut, masyarakat terpecah menjadi tiga bagian. Ditambah lagi dengan adanya berita keikutsertaan santri dalam agenda ngecor bangunan pondok.
Pertama, mereka yang bertanya-tanya mengapa para santri ikut bekerja selayaknya tukang bangungan? Mengapa tidak belajar saja? Bukankah tugas mereka di pesantren hanya belajar dan belajar? Kedua, golongan mereka yang pernah dan sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Ketiga, golongan putih atau netral yang memilih tidak memihak siapapun dan hanya jadi penyimak berita, namun juga gampang terprovokasi tulisan-tulisan di media.
Pertanyaan seperti mengapa para santri ikut bekerja selayaknya tukang bangunan? Mengapa tidak belajar saja yang bagus selama di pondok? Dan pertanyaan-pertanyaan serupa adalah pertanyaan yang muncul dari cara pandang masyarakat modern yang menilai pendidikan sebatas aktivitas akademik di ruang kelas.
Padahal, bagi dunia pesantren, kegiatan seperti ro’an, khidmah, dan tabarrukan adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang telah mengakar kuat dalam sejarah Islam Nusantara.
Tradisi Pesantren
Dalam tradisi pesantren, budaya ro’an adalah sebuah kegiatan kerja bakti bersama yang dilakukan oleh para santri. Baik untuk kepentingan pondok maupun masyarakat sekitar. Aktivitas ini bukan semata-mata kegiatan fisik belaka, namun juga mengandung nilai pendidikan dan spiritual di dalamnya. Akar spiritualnya berpijak pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2.
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Qs. al-Ma’idah [5]: 2).
Pendidikan di pesantren menempatkan kegiatan keilmuan dan pengabdian sosial dalam satu kesatuan yang integratif. Santri terdidik agar tidak serta merta mempelajari ilmu agama saja, namun juga mampu mengekspresikan nilai-nilai keislaman dalam bentuk kepedulian sosial dan kontribusi nyata di lingkungan sekitarnya.
Ro’an atau kerja bersama menjadi bentuk nyata dari ukhuwah (persaudaraan) dan ta’awun (kerja sama) yang melahirkan rasa tanggung jawab dan solidaritas sosial yang tinggi.
Ro’an dan Nilai-nilai Luhur di dalamnya
Ro’an berasal dari kata tabaaraka-yatabaaraku-tabaarukan yang bermakna mengharap kebaikan dari seseorang, perbuatan atau suatu benda yang semuanya berlandaskan dengan kekuasaan Allah sebagai pemilik segala kebaikan.
Kemudian kata tersebut mengalami penyusutan dalam penyebutannya menjadi tabarukan-rukan-ru’an-roan. Dalam dunia pesantren, ro’an dapat diartikan dengan kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan dan merapikan lingkungan.
Budaya ro’an sebenarnya memiliki dua substansi; pertama, nadzafah dzahiriyah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat. Kedua, nadzafah bathiniyah yang bertujuan untuk melatih hati untuk menjauhi sifat-sifat buruk dan melatihnya untuk terbiasa dengan sifat-sifat terpuji. Dengan kata lain, ro’an dapat teraplikasikan sebagai olahraga fisik sekaligus riyadhoh hati.
Budaya ro’an juga mengandung nilai-nilai pendidikan sebagai berikut. Pertama, melatih siswa untuk berjiwa sosial. Siswa harus mempersiapkan diri demi masa depan mereka, sehingga perlu membekali diri dengan pengetahuan juga solidaritas dan jiwa sosial.
Kedua, menanamkan nilai keikhlasan dan kesabaran yang mana keduanya tidak bisa kita dapatkan secara instan. Ketiga, membentuk karakter konservatif yang peka terhadap kebersihan lingkungan dan selalu menjaga diri dari upaya merusak lingkungan.
Tradisi ro’an erat kaitannya dengan semboyan “Kebersihan adalah sebagian dari iman” dan ro’an hadir untuk benar-benar menyadarkan santri bahwa ajaran Islam tersebut harus kita amalkan.
Kegiatan Ro’an Sebagai Budaya Pesantren dan Bentuk Pendidikan Luar Kelas
Kegiatan seperti membersihkan lingkungan, ngecor, memperbaiki bangunan, membantu tetangga, membersihkan dan merapikan asrama bukanlah pekerjaan kasar yang dapat menurunkan harkat dan martabat santri. Justru, dalam pandangan kyai kegiatan tersebut merupakan madrasah kehidupan yang mengajarkan nilai-nilai luhur Islam seperti keikhlasan, disiplin, dan kebersamaan.
Ahmad Tholabi Khalie, seorang guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, anggota dewan Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek RI sekaligus alumnus Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Jawa Barat dalam tulisannya di Republika.co.id ia menulis bahwa dalam dunia pesantren terdapat sebuah adagium penting, “man laa yakhdim, laa yafham.”
Artinya barang siapa yang tidak pernah berkhidmah maka ia tidak akan pernah memahami (ilmu) yang ia pelajari dengan sempurna. Artinya, ilmu tidak hanya tercapai melalui pengajaran (ta‘lim), tetapi juga melalui pengabdian (khidmah). Dalam tradisi ini, mengabdi kepada pondok dan masyarakat adalah bagian dari proses pencarian ilmu itu sendiri.
Khidmah di sini bisa bermacam-macam penafsirannya. Namun, yang jelas ro’an adalah salah satu contoh bentuk khidmah paling ringan yang dapat kita lakukan, selain menaati peraturan pesantren. Dari sinilah pesantren menumbuhkan generasi santri yang berilmu dalam agama, berdaya dalam kehidupan sosial, dan memiliki kemandirian dalam menjalani peran-peran kemasyarakatan.
Di berbagai daerah, santri diajarkan keterampilan praktis seperti menyervis motor, memperbaiki alat-alat pertanian, atau membangun rumah. Bahkan, beberapa pondok mendirikan Badan Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana untuk melatih keterampilan para santrinya.
Ada yang berfokus pada keterampilan menjahit, memasak, perikanan, pengolahan daur ulang sampah dan banyak lagi. Semua ini melatih mereka agar mampu berkiprah di tengah masyarakat dengan bekal kemandirian. Termasuk ro’an. Sejatinya, pendidikan di pesantren adalah pendidikan integral, yakni menggabungkan aspek keilmuan, moralitas, dan keterampilan hidup (life skills).
Refleksi Kegiatan Ro’an dan Momentum Pesantren untuk Berbenah
Ro’an sejatinya adalah kegiatan yang melatih keikhlasan, disiplin dan kebersamaan. Namun, jika melihat keadaan yang terjadi di Al-Khoziny, kita juga tidak bisa menutup mata pada aspek keselamatan dan tata kelola kegiatan.
Insiden ini menjadi sebuah alarm pengingat bahwa setiap amal baik tetap harus kita jalankan dalam koridor hifzh al-nafs atau menjaga keselamatan jiwa, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam maqashid as-syari‘ah. Dalam hukum Islam, ada kaidah penting yang menyatakan:
دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ
“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”
Maka, semangat ro’an yang luhur tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan profesionalisme. Pesantren perlu melakukan penyesuaian manajerial agar kegiatan semacam ngecor tetap aman bagi para santri. Bukan berarti menghapus tradisi itu, tetapi mengatur ulang dengan prosedur keselamatan yang memadai.
Sejak awal, pesantren memang tumbuh dari budaya swadaya. Semangat kiai dan tanah wakaf menjadi unsur berdirinya pondok pesantren. Kemudian, santri ikut membangun, masyarakat ikut menyumbang, alumni patungan, dan setahap demi setahap gedung pun berdiri.
Model tersebut berhasil melahirkan ribuan pesantren di pelosok Nusantara tanpa harus menunggu intervensi pemerintah. Inilah kekuatan pesantren yang disebut Gus Dur sebagai lembaga pendidikan yang memiliki “kemandirian”.
Namun, di balik kemandirian tersebut terdapat kerentanan yang tidak terlihat. Banyak bangunan pesantren yang berdiri tanpa rencana teknis yang jelas, tanpa desain arsitektur yang memenuhi standar keamanan, bahkan sering tanpa keterlibatan insinyur atau pengawas konstruksi.
Hasilnya memang selesai, namun rapuh kualitasnya. Bahkan, sampai hari ini kita masih bisa mendapati gedung kelas yang terbangun seadanya, sempit tanpa ventilasi. Ataupun asrama yang sempit, padahal anggotanya banyak.
Menilik Tragedi di Al-Khoziny
Tradisi ro’an memanglah sebuah sarana pendidikan karakter, melatih kebersamaan, tanggung jawab, dan jiwa gotong royong. Namun, ketika ro’an kita lakukan dalam upaya pembangunan pondok yang seharusnya membutuhkan tenaga professional, maka di sanalah muncul sebuah masalah.
Santri yang tidak terlatih, seringkali diminta membantu mengangkut material, mencampur semen, bahkan ikut memasang bata. Jarang yang mempertanyakan, atau bahkan hampir tidak ada yang mempertanyakan tentang keselamatan dan ketahanan. Padahal, keselamatan tidak lahir dari keikhlasan semata, tetapi dari keahlian dan disiplin standar. Tragedi di Al-Khoziny menyadarkan kita bahwa romantisme gotong royong tidak boleh lagi mengorbankan nyawa santri.
Tragedi Al-Khoziny merupakan alarm keras bahwa pendekatan lama sudah tidak bisa kita pertahankan. Pesantren sering dibangun dengan “iman dan ikhlas”. Sumbangan masyarakat, tenaga santri dan restu kiai menjadi modal yang paling utama. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk membangun bangunan yang kokoh.
Sebuah refleksi yang harus kita terima dan benahi. Pada titik ini, slogan pesantren al-muhafazatu alal qadim as-salih wal akhdzu bil jadid al-aslah artinya mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil baru yang lebih baik, menjadi dasarnya. Pesantren tidak boleh lagi bersembunyi di balik kalimat “ini tradisi pesantren” atau “semua ini dijalankan dengan ikhlas”.
Tradisi yang sudah tidak relevan harus terganti dengan kebaruan yang memiliki maslahat lebih besar. Keselamatan santri harus ditempatkan sebagai prioritas mutlak, bukan sekadar urusan tambahan.
Kolaborasi adalah Kunci
Dalam sebuah opini yang terbit di Jawa Pos kapan hari mengenai kasus ini, terdapat sebuah saran yang menurut saya cukup bagus dan menjadi sebuah pencerahan yang dapat kita tiru dan terapkan. Bahwasanya kita harus belajar dari dunia pendidikan formal yang dikelola oleh negara, yakni sekolah negeri wajib mengikuti standar bangunan gedung pendidikan. Ada peraturan teknis, mekanisme pengawasan, dan prosedur perizinan.
Jika pesantren ingin tetap menjadi pilar pendidikan nasional, standar keselamatan serupa seharusnya kita berlakukan. Tidak adil jika gedung sekolah negeri diperiksa ketat, sedangkan ribuan santri di pesantren, kita biarkan tinggal di asrama yang rawan runtuh.
Urusan ini tentu saja bukan hanya menjadi urusan pesantren, namun juga menjadi urusan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga Kementerian Agama. Semua pihak tersebut haruslah berkolaborasi untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan kondisi fisik pesantren. Bangunan yang tidak memenuhi standar harus segera kita perbaiki, kita perkuat, atau bahkan kita ganti. Biaya yang muncul jangan kita anggap sebagai beban, melainkan investasi keselamatan.
Hal ini kita lakukan dalam rangka ikhtiar atas prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih atau meminimalkan korban di tempat lain. Tragedi di Al-Khoziny menjadi tamparan keras dan pelajaran berharga bagi pesantren di seluruh Indonesia. Jangan sampai tragedi menyedihkan tersebut hanya menjadi sebuah momentum jangka pendek yang kemudian kedukaannya terlupakan dan hilang dari ingatan.
Satu korban saja sudah cukup banyak, maka jangan sampai korban-korban yang berjatuhan hanya dicukupkan dengan doa sebagai penenang, tanpa melahirkan perubahan yang nyata. []