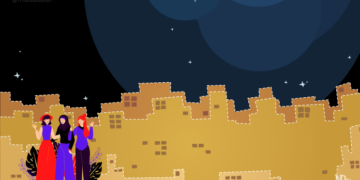Dalam beberapa seloroh, jalan tol sering disebut sebagai ash-shirath al-mustaqim, atau jalan yang lurus. Secara literal bisa jadi benar, tetapi dalam realitas kehidupan jalan tol bisa jadi tidak ideal sebagai satu-satunya “jalan yang lurus” yang harus diikuti semua orang. Tidak semua daerah punya jalan tol, tidak semua orang punya uang atau nyaman dengan jalan tol, atau bisa jadi macet karena digunakan mudik saat liburan nasional.
Karena itu, jalan lurus lebih tepat diartikan sebagai jalan yang bisa membawa seseorang sampai kepada tujuan. Tidak mesti jalan tol. Bisa jalan arteri, bahkan bisa jalan tikus atau yang berkelok. Bisa juga jalur kereta api dan udara dengan pesawat terbang. Ini semua adalah pilihan. Yang pokok adalah sesuatu yang membuat seseorang sampai pada tujuan yang ingin dicapainya. Demikianlah yang lebih tepat sebagai terminologi jalan lurus atau ash-shirath al-mustaqim dalam ungkapan seloroh tadi.
Analogi serupa juga benar dalam hal ber-Islam. Jalan lurus bukan cara tertentu dalam beribadah, mazhab tertentu dalam beragama, golongan atau kelompok tertentu. Kita tahu, dalam berbagai hadits, misalnya, ada lebih dari tujuh puluh jalan keimanan (Sahih Bukhari, no. hadits: 9 dan Sahih Muslim, no. hadits: 161 dan 162). Ada berbagai pernyataan Nabi Saw juga tentang kebaikan-kebaikan yang utama dalam Islam. Jadi, jalan lurus itu bukan satu persatu dari amal perbuatan tertentu, bukan pula mazhab teologi dan fiqh tertentu.
Tetapi lebih merupakan jalan kehidupan, way of life, yang membentuk perspektif dan paradigma seseorang yang dipegangnya selama kehidupan. Dengan paradigma ini, seseorang memandang dirinya sebagai hamba yang berelasi dengan Allah Swt dan sekaligus berelasi sesama hamba. Karena itu, ayat tentang jalan lurus dalam al-Fatihah diawali dengan deklarasi ketuhanan Allah Swt dan proklamasi penghambaan kita kepada-Nya. Deklarasi ini yang membuat “jalan lurus” itu menjadi definitif dan jelas. ash-shirath al-mustaqiim (the straight way-jalan lurus itu).
Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin.
“Hanya kepada-Mu, Ya Allah, kami menghambakan diri dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan”. Penghmbaan kita, sebagai manusia, hanya kepada Allah Swt. Hanya Allah Swt yang Tuhan. Laa ilaaha illallaah. Tiada tuhan selain Allah. Proklamasi ini penting agar kita memiliki pegangan dalam menjalani kehidupan, memiliki martabat dan kemuliaan dalam berelasi dengan siapapun di dunia ini. Relasi antar manusia, sebagai sesama hamba, yang saling menghormati martabat dan kemuliaan masing-masing, satu sama lain.
Seseorang yang meyakini tidak menghamba selain kepada Allah Swt, tidak akan merasa rendah diri di hadapan orang lain. Tidak juga merendahkan orang lain. Sebagai hamba Allah Swt, kita hanya merendah di hadapan-Nya saja. Sementara sesama manusia, sebagai sesama hamba-Nya, harus saling menghormati satu sama lain, menjaga kemuliaan dan kehormatan semua. Tidak boleh ada seseorang yang menghamba atau memperhamba orang lain. Karena penghambaan kita semua hanya kepada Allah Swt.
Wa iyyaaka nasta’iin.
Hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. “Meminta pertolongan” yang hanya kepada Allah Swt, dalam ayat ini, adalah yang korelatif dengan penghambaan di awal ayat. Karena, seringkali seseorang yang meminta pertolongan kepada yang lain, ia akan menghambakan diri kepadanya. Atau, tidak sedikit dari mereka yang dimintai tolong akan memperhamba orang-orang yang meminta tolong pada mereka.
Permintaan tolong yang seperti ini, korelatif denagn penghambaan, hanya boleh kepada Allah Swt. Jadi, penggalan ayat ini (wa iyyaaka nasta’iin) hanya melarang permintaan tolong yang merendahkan seseorang, yang menjadikan relasi seseorang dengan yang lain menjadi relasi seperti hamba dengan Tuhan. Ini yang haram dan hanya boleh dalam relasi kita sebagai manusia dengan Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan kita semua.
Deklarasi primordial penghambaan kita kepada Allah Swt ini penting sebagai dasar relasi kesalingan sesama manusia, agar selalu kerjasama dan saling menolong satu sama lain (QS. Al-Maidah, 5: 2). “Seseorang yang suka menolong orang lain”, kata Allah Swt dalam sebuah hadits qudsi “akan selalu dalam pertolongan Allah Swt” (Sahih Muslim, no. hadits: 7208). Allah Swt, dalam sebuh hadits qudsi yang lain, juga menegaskan bahwa relasi saling menzalimi satu sama lain, sesama hamba-Nya, adalah haram dan tidak boleh dilakukan (Sahih Muslim, no. hadits: 6737).
Menegaskan prinsip relasi ini, Rasulullah Saw menjadikannya sebagai bagian dari keimanan yang paripurna. Sahabat Mu’adz bin Jabal ra pernah bertanya kepada Rasulullah Saw tentang keimanan yang sempurna. Rasulullah Saw menjawab: “Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah”. Mu’adz bertanya: “Ada lagi wahai Rasul?”. Dijawab: “Ketika kamu mencintai untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu dan menghindarkan mereka dari sesuatu yang kamu sendiri tidak suka pada dirimu, menyatakan kebaikan atau diam”. (Musnad Ahmad, no. Hadits: 22558 dan 22560).
Dalam kasus lain, ada seorang Sahabat Nabi Muhammad saw yang bercerita: “Saya bertanya kepada Rasulullah Saw: Wahai Rasul, ceritakan pada saya tentang perbuatan yang mendekatkan pada surga dan menjauhkan dari neraka”. Rasul menjawab: “Kamu dirikan shalat, membayar zakat, menjalankan haji ke baitullah, berpuasa di bulan Ramadan, mencintai untuk manusia apa kamu cintai untuk dirimu, menghindarkan dari mereka apa yang tidak kamu sukai terjadi pada dirimu” (Musnad Ahmad, no. Hadits: 16130).
Dus, keyakinan “iyyaaka na’budu wa iyyaakan nasta’iin” yang transendental harus melahirkan moralitas horizontal antar manusia selalu saling mencintai, saling mengasihi, saling menolong, dan saling kerjasama. Kesalingan sosial ini yang disebut sebagai mubadalah, yang jika didasarkan pada dua teks hadits terakhir di atas, bisa diformulasikan dalam sebuah kalimat berikut:
“Cintailah semua manusia sebagaimana kamu juga ingin dicintai, dan jauhilah membenci mereka sebagaimana kamu juga tidak ingin dibenci”. Tentu saja, pondasi dari rumusan ini adalah keimanan kepada Allah Swt, sebagai satu-satunya Tuhan. Laa ilaaha illallaah.
Paradigma transendental vertikal yang berimplikasi pada moralitas horizontal inilah yang menjadi “way of life” yang akan memandu kita menjalani kehidupan ini, sehingga menjadi orang-orang yang dicintai Allah Swt dan manusia, dan kelak di akhirat memperoleh ridha dan restu-Nya, untuk memasuki surga-Nya. Cara pandang inilah yang disebut sebagai “jalan yang lurus”, atau ash-shirath al-mustaqiim, the straight way.
Ihdina ash-shiratth al-mustaqiim.
“Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu, agar kami terus berada pada jalan yang lurus itu”. Kata “ash-shirath al-mustaqiim” telah dibubuhi artikel (al/ash-). Artinya, jalan itu sudah definitif dan jelas. Seseorang meminta sesuatu kepada Allah Swt, tentu saja harus jelas terlebih dahulu apa sesuatu tersebut. Kita meminta ditunjukkan pada “jalan yang lurus itu”. Jalan itu sudah jelas terlebih dahulu di dalam benak kita, agar kita tahu apa yang kita minta dari Allah Swt. Ia sudah definitif.
Secara susunan kalimat, “jalan yang lurus itu” sesungguhnya sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Yang paling dekat adalah deklarasi penghambaan kita sebagai manusia: hanya kepada Allah Swt (iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin). Deklarasi yang berkorelasi dengan moral horizontal saling mencintai sesama manusia. Korelasi ini merupakan pengejawantahan secara langsung dari kesadaran pada kasih sayang-Nya (rohamutiyah), pentingnya apresiasi (hamdiyah) dan kerja pengasuhan dan pelestarian (rububiyah) segenap semesta (‘aalamiyah). Semua hal ini sudah definitif ditegaskan dalam ayat-ayat sebelumnya dalam surat al-Fatihah.
Jadi, hidayah dalam perspektif surat al-Fatihah adalah “jalan lurus itu” atau ash-shirath al-mustaqiim. Ini yang selalu kita minta setiap shalat lima waktu. Persisnya setiap membaca Surat al-Fatihah. Hidayah yang berupa ‘ubudiyah kita kepada Allah Swt secara vertikal dan relasi mubadalah kita antar manusia secara horizontal. ‘Ubudiyah berarti penghambaan dan ibadah kita hanya untuk Allah Swt. Mubadalah berarti kita selalu bersikap saling mencintai, menolong, dan kerjasama satu sama lain, dalam relasi antar manusia. Baik relasi personal antar individu, marital antara suami istri dalam pernikahan, familial antar anggota keluarga, sosial antar anggota komunitas atau bangsa, maupun global antar penduduk dunia dan universal antar entitas semesta alam.
Shirath ol-ladziina an’amta ‘alaihim, ghair il-maghdhuubi ‘alaihim wa la dh-dhalliin.
“Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri anugerah, yang tidak dibenci, dan juga tidak tersesat”. Demikianlah jalan hidup, atau way of life, orang-orang yang memperoleh anugerah dari Allah Swt, dicintai, tidak dibenci, dan tidak tersesat, melainkan akan sampai pada kebhagiaan dunia dan akhirat (fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanan), dan akan memperoleh ridha dan restu-Nya, serta memasuki surga-Nya sebagai jiwa-jiwa yang tenang, damai, dan sejahtera. Semoga kita semua hidayah yang benar, yaitu jalan lurus ini, yang mengandung ‘ubudiyah kepada Allah Swt dan mubadalah antar manusia. Amiin.