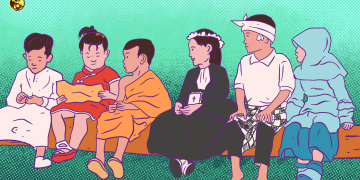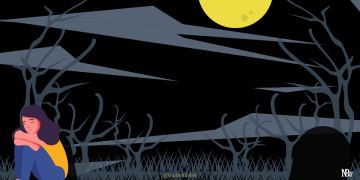Judul: Fiqh Zakat Progresif Memaknai Ulang Nisab, Kadar, Muzakki, Mustahiq, dan Amil Zakat dalam Perspektif Keadilan dan Kemashlahatan
Penulis: Faqihuddin Abdul Kodir
Penerbit: IRCiSoD
Tahun terbit: 2025
Tebal: 401 Halaman
ISBN: 978-634-7157-27-0
Mubadalah.id – Membincang persoalan zakat, seakan tampak di pikiran kita akan kesenjangan ekonomi di antara Muzakki (pihak yang menunaikan zakat) dan Mustahiq (pihak yang berhak menerima zakat). Namun begitu zakat berada di posisi tengah untuk mengurai benang kusut ketimpangan ekonomi yang terasa oleh masyarakat Muslim.
Sebab dalam Islam, zakat menjadi salah satu ibadah yang berorientasi pada harta dan sosial, ia menjadi salah satu ritual penghambaan yang berdampak terhadap kehidupan nyata.
Tujuan dasar ritual zakat, tiada lain untuk mengangkat kebencian orang-orang yang kurang mampu kepada mereka yang memiliki kekayaan lebih. Di sisi lain, zakat juga menjadi penolong dari banyaknya kesulitan yang kelompok tertentu alami dengan cara memberi dukungan finansial.
Secara mekanisme, harta zakat terambil dari mereka yang memiliki kekayaan lebih (aghniya’). Lalu didistribusikan kepada mereka yang tidak atau kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.
Dalam pembahasan zakat dalam kitab-kitab fiqh klasik, ia selalu identik dengan kriteria ibadah yang tetap (ibadah mahdlah) seperti halnya salat, sehingga seringkali dianggap tidak memiliki ruang untuk diberikan kreativitas agar sesuai dengan keadaan di mana zakat itu terlaksana.
Anggapan demikian, salah satunya tersampaikan oleh Muhammad al-Khudheri Bek dalam karyanya, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami (2022). Ia mengatakan bahwa zakat termasuk dalam ibadah mahdlah (ibadah yang murni ketetapannya), sama seperti halnya salat, puasa, dan haji.
Pun demikian, mayoritas ulama juga memiliki pandangan yang sama: bahwa zakat adalah bentuk ibadah yang memiliki ketentuan murni dan cara pelaksanaanya yang tetap. Zakat tidak memiliki ruang untuk kita ijtihadi meskipun ketentuannya tidak lagi selaras dengan kompleksitas zaman.
Realitas Ketimpangan
Anggapan tersebut, telah memberi stimulus bagi KH. Faqihuddin Abdul Kodir, sosok aktivis Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), untuk mendenyutkan kembali keadilan zakat. Ia menawarkan beberapa pembaruan atas fiqh zakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang telah mengalami banyak perubahan.
Menurutnya, jika zakat masih kita pahami sebagai ibadah yang murni dan tetap (mahdlah), dan tidak bisa tersentuh dengan ijtihad baru, maka ia akan mengimplikasikan persoalan yang serius dalam diskursus zakat sendiri. Ia akan kehilangan esensinya untuk mengangkat kesulitan bagi mereka yang kurang mampu dan terpinggirkan (mustadh’afiin).
Kang Faqihuddin Abdul Kodir telah membeberkan realitas ketimpangan yang sangat kentara, ketika diskursus zakat terpahami secara kaku. Sebut saja ketetapan fiqh klasik atas nishab (batas minimal kepemilikan harta) padi dengan capaian 5 wasaq atau setara dengan 653 kilogram yang atau kita uangkan sebesar Rp 9.795.000.
Hasil panen tersebut –dalam keterangan fiqh klasik— sudah menjadikan petani sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat. Terlepas angka tersebut sudah termasuk dalam kategori di atas ambang kesejahteraan petani atau belum. Petani tetap harus mengeluarkan zakat, sebesar 10% jika dengan modal irigasi alami atau 5% dengan modal mandiri.
Berbeda dengan nishab (batas minimal kepemilikan harta) zakat profesi, seperti dokter, advokat, arsitek dan semisalnya. Kewajiban zakatnya setara dengan nishab emas, yaitu 85 gram atau Rp 148. 750.000 jika kita uangkan, dengan pengeluaran sebagai zakat sebesar 2,5 persen.
Dalam tamtsil tersebut, kita bisa merasakan suatu hal yang ironis dalam diskursus zakat. Di mana seharusnya ia menjadi instrumen keadilan sosial dan bisa memenuhi kebutuhan mereka yang kurang mampu dan terpinggirkan (mustadh’afiin). Sebaliknya justru ia menjadi bumerang bagi petani yang hanya dengan penghasilan 9,8 juta, sudah wajib untuk membayar zakat. Sementara dokter dengan penghasilan 140 juta, masih belum terkena wajib zakat.
Di Mana Keadilan Zakat Itu?
Oleh sebab itu, pembaruan ijtihad dalam diskursus zakat bukan lagi suatu hal yang dianggap kreativitas tanpa arah dan dasar. Justru ia menjadi suatu keharusan untuk menjawab realitas umat yang timpang, ekonomi yang kurang berdaya, dan kehidupan sosial yang kurang adil.
Sebab bagaimanapun –menurut Kyai Sahal Mahfudz dalam bukunya, Nuansa Fiqh Sosial (1994), fiqh harus bisa merangkul dua sisi vitalnya. Dua sisi yang beliau maksud adalah sisi langit dan bumi. Di mana fiqh tidak boleh terlepas dari sisi transendentalnya. Pada saat yang sama, fiqh juga harus bisa menjawab realitas pelik yang umat Islam hadapi.
Dalam banyak kasus zakat di Indonesia, gagasan Fiqh Zakat Progresif (2025) ini dapat menjadi modal pokok bagi para pelaksana, pengkaji, peneliti, dan pemerhati zakat. Yakni untuk menjembatani keadilan zakat yang dapat mengangkat ketimpangan ekonomi dan sosial hari ini, tanpa kehilangan sisi transendentalnya.
Dalam buku ini, kita akan menjumpai lima kamar dan satu kamar tengah, yang masing-masing kamarnya tersedia cermin dan jendela untuk melihat persoalan zakat di masa lalu dan kenyataan zakat hari ini. Dari pembaruan zakat akan lahir sebagai bentuk jawaban dari kegelisahan yang lahir atas kurang efektifnya nilai-nilai zakat pada saat ini.
Kontekstualisasi Fiqh Zakat: Menyatukan Teks dan Realitas
Dengan melihat realitas timpang yang terjadi pada zakat padi dan emas untuk saat ini, Kang Faqih telah mengupayakan keras dalam memaknai ulang perihal karakteristik zakat. Dalam pembahasan fiqh klasik sudah dianggap sebagai ibadah yang murni dan tetap.
Kang Faqih membeberkan fakta lain atas ketidak monolitiknya pendapat para ulama atas karakteristik zakat. Apakah ia sebagai ibadah yang murni dan tetap atau ibadah yang memberikan ruang ijtihad. Sehingga dapat kita berikan kreativitas pada diri zakat untuk menjawab kompleksitas pelik ekonomi-sosial di kehidupan yang serba berubah ini?
Artinya, Kang Faqih telah menemukan banyak pendapat para ulama terdahulu –tentang isu yang mendasar terkait zakat— yang beragam. Dari sini, bukan tidak mungkin bagi ulama kontemporer untuk meropisisi pemahaman keibadahan zakat.
Sehingga, Kang Faqih menemukan titik krusial dalam memahami karakteristik zakat, yang bukan hanya sekadar ibadah spiritual semata. Namun juga ibadah yang memiliki dimensi sosial atau mu’amalah (hal-hal yang termasuk dalam urusan kemasyarakatan), untuk bisa menyejahterakan umat.
Selain itu dengan karakter ibadah zakat yang mu’amalah, zakat bukan lagi menjadi kewajiban yang sakral semata. Akan tetapi, zakat menjadi instrumen keadilan sosial, distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan penolong bagi kaum yang rentan.
Karena di sisi lain, zakat juga kita pandang sebagai ibadah yang berorientasi pada harta dan sosial (ibadah maliyah ijtima’iyyah). Ia memiliki peran transformatif yang harus berkembang untuk menjawab tantangan zaman yang kompleks secara kontekstual dan adaptif.
Menghidupkan Ruh Zakat dalam Nadi Perubahan Zaman
Dalam buku ini, zakat tidak lagi terpahami sebagai ibadah ritual semata, namun juga sebagai instrumen distribusi kesejahteraan umat. Sehingga pembahasannya lebih luas dan kompleks, sebagai ikhtiyar agar teks dan realitas dapat berjalan beriringan tanpa harus ada yang terkorbankan.
Dalam konteks zakat mal (harta kekayaan), zakat kita artikan sebagai kewajiban atas harta yang sudah mencapai ambang batas kekayaan (nishab), bukan sekadar kewajiban yang bersandar pada individu. Sehingga anak kecil, perempuan, atau orang yang dalam gangguan jiwa, tetap kita wajibkan untuk menunaikan zakat, jika hartanya telah mencapai nishab.
Begitu pula, harta yang lembaga atau perusahaan miliki, atau juga harta pinjaman yang dikuasai oleh peminjam atau yang sudah dikembalikan kepada yang meminjamkan. Tergantung siapa yang sedang menguasai harta tersebut.
Kewajiban zakat juga, wajib atas harta yang kita peoleh secara illegal, seperti pencurian atau korupsi –namun tidak serta merta penulis menganggap sah perbuatan haram tersebut. Begitu pun, barang bukti yang negara kuasai, ia wajib terbayarkan zakatnya. Jika semua itu telah melebihi ambang batas kekayaan.
Pandangan demikian bukan berarti melegalkan perbuatan haram tersebut, hanya saja untuk menegaskan tanggung jawab sosial atas harta yang terkuasai.
Pendeknya, prinsip yang Kang Faqih tawarkan dalam hal subjek hukum zakat, tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok yang memliki harta, akan tetapi zakat adalah kewajiban atas harta yang sudah mencapai ambang batas kekayaan (nishab). Baik ia dikuasai anak kecil, perempuan, orang dalam gangguan jiwa, atau ia hasil dari cara yang terlarang.
Dengan tawaran demikian, tujuan dan ruh zakat kembali terasa hidup yang denyut keadilan zakat bisa menyentuh pada mereka yang membutuhkan. Di sisi lain –meminjam istilah pak Prabowo, fenomena Serakahnomics bisa terangkat oleh pembaruan zakat progresif ini.
Membaca Ulang Makna Nishab dan Kadar Zakat
Menjadi sangat penting untuk kita bahas –dalam rangka menghidupkan kembali ruh keadilan zakat— dalam kenyataan modern ini, adalah perhitungan nishab dan kadar yang dikeluarkan oleh muzakki (pemberi zakat).
Kang Faqih –dalam buku ini, menawarkan pembaruan yang sangat relevan bagi harta kekayaan yang dimiliki di era modern. Di mana jenis kekayaannya tidak terbatas pada jenis harta tertentu, seperti emas, perak, hewan ternak, padi, dan barang dagangan saja.
Dalam hal ini, Kang Faqih bukan hanya memandang objek zakat dengan jenis harta yang tersebutkan dalam nash –al-qur’an dan hadist semata. Namun ia memperluas cakupan harta kontemporer yang memliki nilai ekonomi, tumbuh, dan berkelanjutan.
Sehingga, Kang Faqih membagi dua jenis harta yang wajib untuk kita zakati dalam kenyataan hari ini, yaitu harta likuid dan non likuid.
Harta likuid adalah harta yang dengan mudah dapat kita cairkan dan langsung dapat kita gunakan untuk kebutuhan sosial. Seperti uang tunai, tabungan, deposito, emas perak, surat hutang, dan hasil pertanian yang sudah siap dijual. Sementara, harta non-likuid adalah harta yang memerlukan konversi atau belum menghasilkan secara mudah dan langsung.
Nishab yang Kang Faqih tawarkan–dalam hal ini, adalah harta yang sudah melebihi ambang kebutuhan dasar pemiliknya (hadd al-kifayah), bukan hanya terbebankan kepada mereka yang baru hidup di batas kecukupan.
Dalam konteks Indonesia, angka ambang kesejahteraan (hadd ar-rafah) ini berupa PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Konkritnya, nishab yang Kang Faqih tawarkan yaitu ketika kekayaan sudah mencapai Rp 67.000.000 bagi yang lajang, dan Rp 126.000.000 bagi yang sudah berkeluarga, lembaga atau peruashaan.
Panggilan Moral dan Spiritual
Sementara, kadar yang wajib kita keluarkan bagi harta likuid adalah sebesar 2.5%, dan harta non-likuid yang zakatnya terambil dari laba hasil bersihnya: sebesar 2.5%. Keduanya akan menjadi 5% ketika hasilnya mencapai sepuluh kali nishab, dan bisa menjadi 10% jika sudah mencapai seratus kali lipat nishab.
Bukan hanya itu, Kang Faqih juga memaknai ulang atas nishab zakat atas harta temuan (Rikaz). Ia tidak lagi kita artikan hanya pada harta temuan belaka. Namun juga harta hadiah atau hibah dari orang lain. Ia wajib kita keluarkan zakatnya sebesar 20% ketika sudah mencapai batas nishab.
Walhasil, Buku Fiqh Zakat Progresif (2025) ini dan pembaruan-pembaruan yang ia tawarkan, bukan sekadar menjadi alternatif fiqh belaka. Namun sebagai panggilan moral dan spiritual yang lahir dari kesadaran realitas ekonomi modern yang sangat kompleks.
Selain itu sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan tujuan keadilan zakat. Yakni alat untuk mendistribusikan kekayaan yang berpihak pada kaum yang lemah dan dilemahkan –baik secara sosial ataupun struktural. Di samping itu, gagasan demikian tidak keluar dari koridor cita-cita zakat yang dapat menciptakan keadilan sosial dan solidaritas umat. []