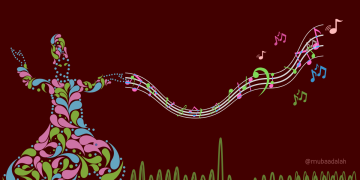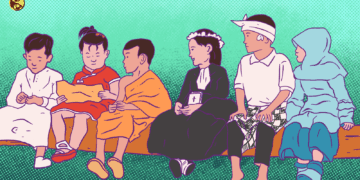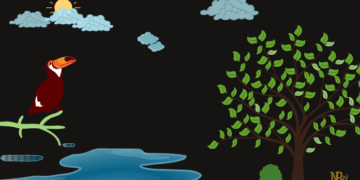Mubadalah.id – Dalam perbincangan dunia modern, masyarakat Jawa kerap tergambarkan sebagai komunitas yang lebih menonjolkan sisi emosional ketimbang rasionalnya. Beberapa peneliti Barat bahkan mengaitkan kecenderungan ini dengan faktor iklim dan udara yang mengiringi di saat orang-orang Jawa terlahirkan.
Salah satunya adalah penelitian yang pernah Petrus Henri Marie Travaglino lakukan. Ia meneliti perihal emosional orang Jawa. Penelitian itu, tertera dalam karya Hans Pols yang berjudul Obat, Ilmu, dan Kuasa: Sejarah Kesehatan dan Kedokteran Indonesia (2025). Resensi ini pernah terbit di Harian Kompas pada 6 Juli 2025 dengan judul Psikiatri Kolonial, Ketika Ilmu Dijadikan Alat Penaklukan (Harian Kompas, 6 Juli 2025).
Salah satu contoh nyata dari praktik yang dianggap tidak masuk akal ini, adalah kisah seorang ibu yang mengubur tujuh ikan lele hidup-hidup di tengah warungnya. Ia menggantung tujuh ketupat di atas pintu, lalu meniupnya setelah terbacakan mantra dan doa. Semua itu ia lakukan demi harapannya, agar warung itu laris dan mampu menopang kehidupan keluarga.
Kisah itu tercatat dalam Rubrik Konsultasi Koran Minggu Ini Cempaka (Edisi 26/XIV/25, September 1 Oktober 2003), bersama berbagai keresahan masyarakat lainnya. Seperti jodoh, undian berhadiah, dan penglaris warung. Kendati jawaban yang diberikan dalam rubrik tersebut cenderung tidak rasional, ia mencerminkan lanskap batin masyarakat yang hidup dalam harapan dan simbol.
Keterkaitan Tradisi Keilmuan Klasik dan Disiplin Psikologi Modern
Dalam narasi modern, hal demikian akan cenderung kita kritik sebagai praktik yang tidak begitu masuk akal. Dengan kata lain, segala bentuk tradisi yang tidak dapat terbukti secara empiris harus kita hilangkan atau setidaknya harus bisa kita buktikan dengan data dan rasio.
Sebut saja, tradisi pesantren yang akhir-akhir ini tidak luput dari sorotan. Beberapa praktik seperti berlutut sebagai bentuk penghormatan kepada guru, atau memberi amplop bebungah kepada kiai, telah menjadi bahan perbincangan di media sosial dan ruang-ruang publik.
Di sinilah, tuntutan kentara rasionalitas modern seolah menafikan bahwa tindakan tersebut juga memiliki logika tersendiri, yang memang kita bahasakan dengan bahasa yang berbeda.
Keterkaitan erat antara tradisi keilmuan klasik dan disiplin psikologi modern, kiranya pada saat ini sudah terkuak begitu jelas. Sebut saja, praktik turun-temurun yang melekat di lingkungan pesantren, yang selama ini termanifestasi dalam metodologi pengajaran dan pembentukan karakter. Kini tradisi itu menemukan validasi ilmiahnya. Fenomena ini terbukti selaras dengan apa yang Albert Bandura kembangkan dalam Social Learning Theory (Teori Belajar Sosial) dalam ilmu Psikologi.
Dengan demikian, apa yang secara kultural kita sebut meniru atau keteladanan yang mengakar di pesantren, tanpa tersadari, telah terakui dan terbingkai ulang dalam bahasa yang sepenuhnya ilmiah dan modern. Dalam tradisi Jawa, hal ini telah lama hidup dalam pepatah “ngelmu iku kalakone kanthi laku.” Bahwa ilmu bukan hanya soal nalar, tetapi juga laku, yang dapat terserap melalui praktik yang terlihat di sekitarnya.
Tradisi dan Sains Modern
Pada gilirannya, gelombang rasionalisasi juga merambah ke mitos dan dongeng tradisional. Misalnya, larangan kencing di bawah pohon besar karena teryakini ada roh penunggu. Pernyataan ini seringkali dianggap tidak masuk akal. Padahal, hal semacam itu adalah simbol ekologis dan spiritual tersendiri yang terwariskan untuk menjaga harmoni dengan alam.
Hal itu, memiliki keselarasan menarik dengan apa yang Media Kompas terbitkan pada 2 November 2025 yang meresensi buku Denyut Nadi Bumi: Geologi Politik di Jawa dengan tajuk yang berjudul Ratu Kidul, Patahan Opak, dan Di Balik Meletusnya Gunung Merapi.
Resensi tersebut, mengungkapkan bahwa mitos Ratu Kidul bukan hanya sekadar takhayul yang sudah kadung terpercayai dari generasi ke generasi. Melainkan di dalamnya terkandung tafsir geologi dengan gaya bahasa yang bersifat lokal. Karena, di balik legenda itu, tersimpan pengetahuan ekologis yang terwariskan melalui ritual dan cerita rakyat.
Selain itu resensi tersebut, juga memiliki keselarasan menarik dalam studi ilmiah yang meninjau ulang kearifan lokal. Seperti jurnal yang membahas pengobatan tradisional di Desa Lumbungsari, misalnya. Ia mengungkapkan bahwa di balik praktik yang tampak mistis, terkandung manfaat nyata bagi kesehatan.
Pengobatan di sana terbagi menjadi empat jenis, termasuk pengobatan hikmah yang menangani masalah spiritual hingga fisik, serta pengobatan herbal yang menggunakan berbagai tumbuhan obat (Suryani, 2017).
Studi itu, telah menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak semuanya harus kita rasionalkan secara tergesa-gesa, melainkan kita pahami sebagai sebuah paket utuh. Sebab, meski penggunaan ramuan tersebut sering berkaitan dengan ritual dan doa-doa (mantra), temuan ilmiah menguatkan bahwa bahan-bahan alam tersebut memang memiliki potensi medis.
Bagi penulis, temuan dalam studi tersebut telah menawarkan perspektif segar, bahwa warisan lokal bukan hanya sekadar mitos belaka, tetapi juga sebagai sumber refleksi dan analisis akademik yang relevan pada saat ini. Sebab sebuah tradisi tidak semuanya harus dirasionalkan secara tergesa-gesa, melainkan kita pahami dalam logika dan bahasa yang berbeda sekaligus utuh.
Di sisi lain, sebuah tradisi yang sudah mengakar kuat di dalam tubuh masyarakat, telah teruji kuat dalam menjaga moral manusia di tengah tuntutan rasionalitas, di samping ia berpotensi untuk menjembatani antara ilmu modern dan kearifan lokal.
Legowo dalam Memahamai Tradisi dan Modernitas
Dengan demikian, tradisi lokal masyarakat Jawa tidak bisa serta-merta kita nilai sebagai sesuatu yang tidak rasional hanya karena tidak sesuai dengan standar ilmu modern. Praktik-praktik seperti penglaris warung, penghormatan kepada guru di pesantren, hingga mitos tentang Ratu Kidul. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional (Jawa) memiliki cara tersendiri dalam memahami dan merespons realitas di sekitarnya.
Karena dalam menilai tradisi tersebut, mereka bukan hanya sekadar mengartikannya sebagai warisan budaya semata. Tetapi juga memandang bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial, spiritual, dan ekologis yang masih relevan pada saat ini.
Walhasil, menilai tradisi hanya dengan tuntutan rasionalitas modern adalah tindakan yang tergesa-gesa. Sebab, kearifan lokal seperti penglaris warung hingga mitos Ratu Kidul, sejatinya adalah mistisisme yang belum kita terjemahkan dalam bahasa ilmu pengetahuan.
Ia adalah kode etik, moral, dan ekologi yang tersampaikan melalui laku dan simbol. Dengan begitu, sudah saatnya kita membacanya dengan legowo. Yakni melihat tradisi dan modernitas sebagai pelengkap untuk mencapai pemahaman yang utuh antara sains dan kearifan leluhur. []