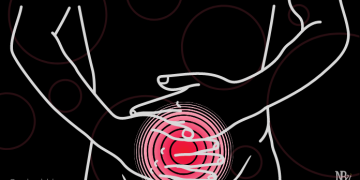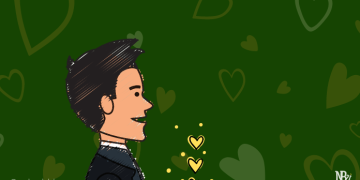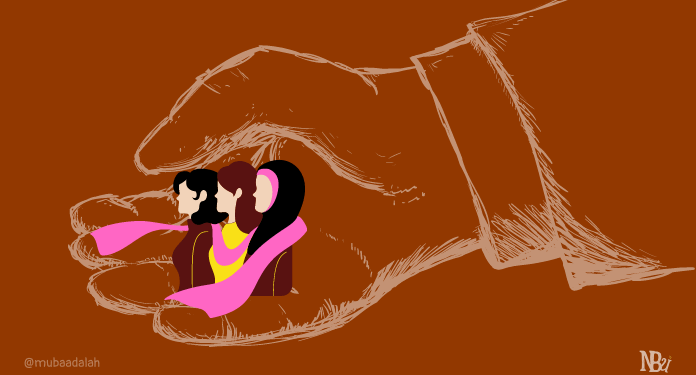Mubadalah.id – Baru-baru ini Netflix merilis sebuah film “A Normal Woman” pada 24 Juli 2025 di Netflix. Film ini menghadirkan tafsir visual yang menggugat konstruksi sosial tentang kesempurnaan perempuan. Dengan Marissa Anita sebagai Milla, pemeran utama dalam film ini yang menarik kita perlahan ke dalam labirin kehidupan glamor yang penuh dengan retakan tersembunyi.
Awalnya tampak indah dan sempurna, tetapi perlahan-lahan keindahan itu berubah menjadi luka yang nyata: dari kulit mulus berubah menjadi penderitaan fisik dan mimpi buruk yang terus menghantui. Kisah Milla tidak berdiri semata sebagai cerita personal. Ia juga menjadi metafora tajam yang menunjukkan bagaimana tekanan sosial terus menyeret perempuan ke dalam standar yang menyesakkan.
Perempuan Di Balik Topeng Kesempurnaan
Film “A Normal Woman” karya Lucky Kuswandi ini secara implisit menunjukkan bagaimana konstruksi sosial terus mendorong perempuan modern masuk ke dalam pola pikir patriarki, bahkan sering kali tanpa mereka sadari. Berpijak pada tesis Simone de Beauvoir mengenai perempuan sebagai The Second Sex, karakter Milla merepresentasikan bahwa perempuan menjadi “yang lain”.
Konstruksi sosial telah memposisikan laki-laki sebagai subjek universal dan perempuan sebagai objek pelengkap. Lingkungan sosial membentuk identitas perempuan dari luar dirinya—melalui harapan, tatapan, dan aturan yang terus menekan dan mengatur hidupnya. Akibatnya, ia semakin jauh dari jati diri yang otentik.
Milla merupakan simbol dari kegagalan struktur sosial dalam memberikan ruang bagi perempuan menjadi subjek. Suami dan mertuanya, masyarakat, bahkan tubuhnya sendiri terus membentuk citra-citra yang mengekang langkah Milla.
Dalam kerangka Beauvoirian, Milla bukanlah subjek otonom, melainkan eksistensi yang tercerabut dari kebebasan memilih. Ruam-ruam dalam tubuhnya menjadi representasi fisik dari tekanan yang tak kasat mata, dari penolakan tubuhnya sendiri terhadap paksaan normalitas.
Apakah Milla Sejatinya Mereproduksi Patriarki Itu Sendiri ?
Film “A Normal Woman” ini menyajikan sebuah ruang reflektif: bagaimana sistem patriarki tidak hanya menciptakan struktur ketimpangan, tapi juga menyusup ke dalam tubuh, psikologi, dan spiritualitas perempuan. Ketika sebagian masyarakat menolak memberi ruang bagi perempuan untuk mendefinisikan eksistensinya, tubuh perempuan pun mengambil alih.
Ia menolak, memberontak, dan berbicara lewat luka yang tak bisa ia sembunyikan. Seperti kata Beauvoir “One is not born, but rather becomes, a woman”. Milla seakan menunjukkan bahwa proses menjadi itu bisa sangat menyakitkan ketika kebebasan tidak ikut menyertainya.
Kondisi yang Milla alami mencerminkan bagaimana perempuan kerap ikut menjaga nilai-nilai patriarki. Bahkan dalam banyak hal, mereka turut memperkuatnya melalui sikap yang tunduk pada standar yang tidak realistis.
Sebagian besar masyarakat—dari berbagai latar dan peran—secara sadar maupun tidak, mendorong tren kecantikan yang melelahkan. Mereka juga menuntut perempuan terus menyesuaikan diri dengan citra ideal yang tidak nyata. Dengan begitu, ketimpangan gender yang telah lama berakar pun terus terpelihara.
Padahal, yang lebih dalam dari persoalan ini adalah hilangnya kebebasan perempuan untuk hidup autentik dan merdeka. Perempuan, dalam diamnya, seolah membenarkan dan mengamini nilai-nilai patriarki yang mengekangnya. Keadaan ini membuat kita menanyakan ulang, sampai kapan perempuan akan terus menjadi cermin harapan dan ekspektasi orang lain, bukan cermin bagi dirinya sendiri.
Milla dan Realitas Perempuan Modern
Milla adalah representasi nyata dari perempuan-perempuan yang dalam kesunyian bergulat dengan luka batin dan tekanan tak terlihat di sekitar kita. Kisahnya juga mencerminkan bagaimana masyarakat terus menuntut perempuan untuk tampil sempurna sesuai standar tertentu
Tuntutan tersebut melahirkan kecemasan, ketakutan akan penolakan, hingga ketidakmampuan untuk mengungkapkan diri yang sebenarnya. Dalam kenyataan sehari-hari, sosok Milla bisa jadi adalah teman, saudara, atau bahkan kita sendiri yang dalam senyap menanggung beban identitas yang tidak utuh.
Perubahan positif hanya mungkin terjadi jika kita bersama-sama sadar dan bersedia mengubah pola relasi sosial menjadi lebih adil dan setara. Kisah Milla menjadi pengingat bahwa realitas perempuan modern adalah refleksi dari pola pikir dan sikap yang telah lama kita jalani. Tugas kita bukan sekadar menyadari, tetapi aktif menciptakan ruang baru yang memungkinkan perempuan hidup tanpa rasa takut akan tuntutan sosial.
Meredefinisi Makan “A Normal Woman”
Saya pernah bertanya-tanya,
“Mengapa perjuangan keadilan gender atau keadilan terkait perempuan terus berlangsung hingga kini, dan isu-isunya selalu sama ?”
“Apakah masih kurang berbagai solusi transformatif yang di-mainstreamingkan?”
Yaps ! saya perlahan menemukan jawaban dari kegelisahan itu. Karena persoalan ketidakadilan ini terus bertransformasi, tetap relevan, dan selalu membutuhkan testimoni perempuan sebagai bukti bahwa persoalan itu memang nyata dan hidup dalam keseharian.
Melalui representasi tokoh Milla, perempuan terus menghadirkan pengetahuan hidup yang tak lekang oleh waktu. Isu yang selalu menjadi pengingat bahwa perjuangan ini belum usai.
“A Normal Woman” menjadi momentum penting untuk mendefinisikan ulang makna normalitas perempuan. Kini normal bukan lagi tentang keseragaman tubuh, kecantikan, atau kesuksesan materi, melainkan tentang autentisitas diri, keberanian dalam ekspresi diri, dan kemerdekaan dari penilaian lain. Scene terakhir dalam film ini, secara lugas menggambarkan hal demikian. Pada akhirnya, Milla memilih kebebasannya sendiri dan menarik diri keluar dari pusaran standar yang mengekang.
Dalam makna baru ini, normal adalah tentang menghormati keberagaman perempuan sebagai subjek yang utuh. Normalitas sejati adalah tentang ruang bagi setiap perempuan bebas mengembangkan potensinya tanpa pembatasan stereotip gender. Normalitas menjadi sesuatu yang cair, dinamis, dan inklusif.
Kita semua, perempuan maupun laki-laki, bertanggung jawab membangun normalitas baru ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah perempuan sudah cukup memenuhi standar tertentu, tetapi apakah kita semua siap menciptakan standar yang lebih manusiawi dan adil.
Perempuan menemukan makna sejati menjadi “A Normal Woman” saat ia berani hidup merdeka dan jujur pada dirinya sendiri. Orang lain pun menghargainya karena keberadaannya yang utuh—bukan karena peran, penampilan, atau tuntutan sosial yang mempersempit kebebasannya. []