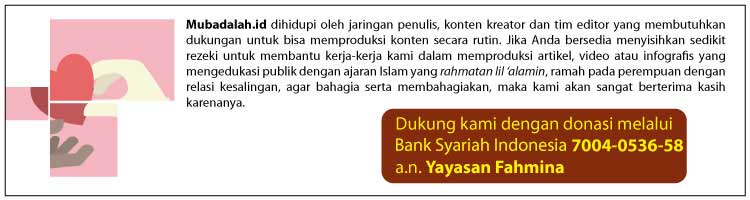Mubadalah.id – Jilbab dalam konteks Islam di Indonesia merupakan fenomena sosial dan keagamaan baru. Mulai berkembang sebagai identitas politik di masa revolusi Iran di paruh tahun 70-an, jilbab kemudian mendapatkan pengentalan teologisnya bersama munculnya teks-teks keagamaan yang melegitimasi keharusan berjilbab. Belakangan bersama munculnya politik identitas Islam, jilbab dengan penanda-penanda sejenis diatur sebagai ketentuan syariat.
Ratusan tahun dalam berkembang Islam di Indonesia, penutup kepala yang dikenakan kaum perempuan, atau disebut kerudung, atau kudung (Jawa) atau tiung (Sunda) atau tengkuluk (Minang) dianggap sebagai identitas Nusantara. Ibu Negara Fatmawati mengenakannya sebagai identitas kebangsaan Indonesia yang baru merdeka.
Kerudung dikenakan Ibu Fat bersama kebaya dan kain batik dalam upacara atau acara resmi kenegaraan. Di era Orde Baru (paruh pertama), ketika Negara melakukan penjarakan terhadap Islam politik, kebaya dikenakan tanpa kerudung ala Ibu Fat. Bahkan kebaya menjadi citra kaum perempuan dalam politik identitas Orde Baru dengan makna sebagai istri pendamping suami.
Selama bertahun-tahun, identitas perempuan Indonesia mengacu kepada dominasi budaya priyayi Jawa yang menggunakan kebaya tanpa kerudung kecuali pada keluarga santri. Bahkan ketika itu, perempuan muda dengan latar belakang NU dan Muhammadiyah tak selalu menggunakan kerudung kecuali bagi yang beranjak sepuh.
Lambat laun bentuk kerudung berubah menjadi jilbab yang lebih tertutup. Pengaruh revolusi Iran sangat tegas membekas di sana. Di Barat, jilbab tak hanya dimaknai sebagai identitas baru warga muslim minoritas tetapi juga simbol ketaatan kepada Islam. Dalam perkembangannya jilbab menjadi fenomena dunia sebagai identitas kultural sekaligus teologis. Bersama munculnya kajian-kajian baru tentang jilbab muncul pula pengentalan teologis yang menganggap jilbab sebagai hal yang diwajibkan mengikuti ketentuan syariat.
Di Indonesia, terinspirasi oleh revolusi Iran, gerakan Salafisme di Timur Tengah, serta gairah keagamaan di Barat plus bisnis garmen dan fashion, jilbab mewujud menjadi fenomena yang rumit: tidak hitam putih, tidak tunggal dan tidak bebas nilai. Namun muncul juga kecenderungan kearah ortodoksi yang ditekankan sebagai aturan keagamaan yang mengikat. Bersama munculnya otonomi daerah, jilbab di beberapa daerah diatur sebagai regulasi daripada sebagai identitas kultural atau pilihan keyakinan.
Hal ini menjadi semakin jelas ketika Aceh menerapkan syariat Islam. Jilbab kemudian menjadi salah satu ketentuan yang menjadi regulasi. Namun sebetulnya begitu menjadi regulasi atau qanun, maka jilbab telah melepaskan “keswadayaan iman” nya menjadi aturan yang memaksa. Dari sisi tata aturan hukum, maka saat itu pula jilbab tunduk pada aturan yang bersifat duniawi sebagaimana layaknya aturan Undang-Undang.
Ketika saya mengikuti kegiatan penguatan perempuan calon anggota parlemen tingkat daerah, saya tak heran bertemu perempuan non-Muslim dari wilayah perbatasan Aceh Singkil yang dengan sengaja menggunakan jilbab. Mereka mengaku merasa nyaman karena dengan memakai jilbab tak merasa dianggap sebagai orang lain dalam pertemuan-pertemuan yang berlangsung di wilayah Aceh.
Itu pula agaknya yang terjadi pada siswi non-muslim di wilayah lain yang menggunakan jilbab sebagai seragam sekolahnya. “Syariatisasi” jilbab secara otomatis gugur ketika jilbab ditetapkan sebagai aturan yang mengikat dalam bentuk regulasi. Hal ini pula yang berlaku pada siswi SMK Negeri 2 Padang sebagaimana pengakuan mereka yang mengenakan jilbab di sekolah. Mereka mengenakannya karena merasa menjadi bagian dari aturan, serta tak nyaman menjadi warga belajar yang berbeda. Siapapun tahu, menjadi berbeda itu tidak nyaman manakala perbedaan itu bukan hal yang dianggap anugerah melainkan rasa gerah.
Perkara jilbab dalam hubungannya dengan ruang publik seperti di lembaga pendidikan sudah berlangsung sejak era Ode Baru. Di bawah politik penyeragaman, sejumlah siswi SMA yang memilih memakai jilbab dipersoalkan secara serius di awal tahun 80-an. Semula – berbeda dengan stuasi sekarang, para siswi berjilbab itu didiskriminasi. Mereka didesak mencopot jilbabnya atau mundur dan pindah sekolah.
Menyadari hak-hak mereka telah dilanggar sejumlah pegiat HAM membelanya dengan argumen kebebasan berkeyakinan sebagai hal yang prinsip dalam hak asasi manusia. Belakangan suasananya berbalik, siswi yang tak berjilbab, meskipun Muslim, telah dikondisikan – untuk tidak dikatakan diintimidasi, untuk memakai jilbab, tak terkecuali siswi non-Muslim.
Sebetulnya tata aturan pemakaian jilbab ini tak selalu jelas regulasinya. Bahkan terkadang sama sekali tidak ada aturan resmi. Paling jauh, ada aturan berupa SK dari Pimpinan Daerah setingkat Bupati atau Walikota. SK itu biasanya meminta siswi menggunakan jilbab sebagai bagian dari disiplin, meskipun pendisiplinan itu tak (selalu) berlaku untuk siswi non-muslim.
Namun seperti telah dikemukakan, tanpa SK sekalipun, penggunaan jilbab niscaya akan dipilih oleh seorang siswi non- muslim jika jilbab digunakan sebagai penanda perbedaan atau bahkan dianggap bentuk pembangkangan bagi siswi yang kebetulan beragama Islam. Padahal, menjadi beda dalam situasi yang gampang membeda-bedakan itu sungguh tak nyaman. Karenanya sama sekali tak heran jika sejumlah siswi di sekolah negeri, seperti di SMK Negeri 2 Padang itu, bahkan yang muslim sekalipun mengaku dengan “sukarela” memakai jilbab.
Lalu bagaimana sebaiknya menyikapi hal ini? Di sini sebetulnya ada pilihan. Bila jilbab dianggap sebagai pilihan keimanan, maka jilbab tak seharusnya menjadi hal yang diwajibkan melainkan sebagai kesadaran pribadi. Namun sebaliknya jika kehendak mewajibkan jilbab diatur sebagai keputusan suatu lembaga seperti sekolah, maka status jilbab tak akan beda dengan seragam. Jilbab dengan sendirinya tak dikaitkan dengan aturan agama melainkan sebagai aturan tata tertib sekolah. Ini tak ubahnya dengan siswa perawat yang pakai topi perawat, atau siswa perhotelan jurusan tata boga yang memakai topi pramusaji.
Dengan kata lain, jika jilbab ditetapkan sebagai kewajiban di sekolah maka pakaian penutup kepala itu harus mengalami desyariatisasi. Dengan demikian jilbab bukan lagi dianggap sebagai kewajiban agama (syar’i) melainkan kewajiban yang berlaku umum bagi semua siswi terlepas dari suku, ras, agama dan keyakinannya. Bahwa bagi siswi Muslim sendiri menganggap jilbab sebagai ketentuan agama, itu menjadi urusan personalnya. Kewajiban sekolah adalah mengatur seragam.
Dan tatkala jilbab menjadi bagian dari seragam maka jilbab harus dijadikan aturan yang mengikat dan secara postitif atau memaksa. Ini sama halnya dengan para pejabat negara yang wajib memakai peci hitam di saat pelantikan atau upacara. Bahwa bagi pejabat yang muslim peci dianggap pakaian keagamaannya, nggih monggo, silahkan saja.
Sekolah, terutama sekolah umum seharusnya hanya memberlakukan aturan yang berlaku sama bagi semua siswa; memakai seragam upacara di hari upacara/ hari Senin, pakai baju olah raga di jadwal olah raga, pakai seragam Pramuka di hari wajib memakai baju Pramuka dan seterusnya.
Tatkala diberlakukan desyariatisasi jilbab, maka jilbab tak lagi menjadi urusan agama melainkan sebagai urusan seragam sekolah. Namun sebaliknya jika jilbab dianggap sebagai keyakinan yang berangkat dari pilihan individu, maka jilbab tak seharusnya menjadi aturan yang dipaksakan. Nah, mau pilih yang mana? []