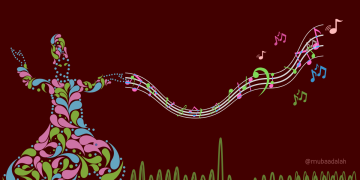Mubadalah.id – Pernahkah kita membayangkan bahwa apa yang selama ini kita sebut sebagai “mitos” justru dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mitigasi dan pencegahan krisis iklim? Selama ini, krisis iklim kerap kita pahami semata-mata sebagai persoalan teknis. Yakni tentang naiknya suhu global, perubahan pola cuaca, degradasi lingkungan, atau berkurangnya keanekaragaman hayati.
Padahal, krisis iklim sejatinya adalah fenomena multidimensional yang tidak hanya berhubungan dengan kerusakan fisik alam. Tetapi juga menyangkut cara manusia membangun relasi simbolik, kultural, spiritual, dan politik dengan lingkungan hidupnya.
Dalam konteks inilah, mitos memperoleh relevansi baru. Mitos dapat kita pahami sebagai narasi tradisional yang hidup dalam ingatan kolektif suatu masyarakat, yang memuat makna simbolis tentang asal-usul alam semesta. Lalu hubungan manusia dengan makhluk lain, serta keberadaan kekuatan adikodrati.
Lebih dari sekadar cerita rakyat, mitos kita yakini sebagai kebenaran kultural yang berfungsi sebagai pedoman moral, penjelas fenomena alam, sekaligus penjaga nilai-nilai sosial. Mitos membentuk identitas kolektif, mengatur perilaku manusia, dan menanamkan etika dalam berelasi dengan alam.
Mitos, Mitigasi dan Krisis Iklim
Buku Mitos, Mitigasi, dan Krisis Iklim karya Nabillah Kurniati dan Dewi Candraningrum hadir menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap krisis ekologis kontemporer. Buku ini mengajak pembaca untuk kembali merawat alam semesta sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat adat. Terutama perempuan, melalui pembacaan ulang dunia mitos.
Alih-alih mengandalkan pendekatan teknokratis atau diskursus kebijakan iklim global yang sering kali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat, buku ini justru berangkat dari narasi mitologis lokal. Yakni kisah Putri Karang Melenu dan Naga Sungai Mahakam.
Pendekatan semacam ini sejalan dengan perkembangan kajian lingkungan kritis yang menempatkan pengetahuan lokal, kosmologi masyarakat adat, serta ingatan kultural sebagai sumber penting dalam memahami krisis ekologis dewasa ini. Dalam kerangka ini, mitos tidak lagi kita posisikan sebagai cerita irasional atau sisa-sisa kepercayaan masa lalu, melainkan sebagai teks kultural yang menyimpan etika ekologis dan memori kolektif tentang hubungan manusia dengan alam (Malinowski, 1926).
Kurniati dan Candraningrum membangun argumen utama bahwa mitos Putri Karang Melenu dan Naga Sungai Mahakam mengandung nilai-nilai ekologis yang relevan untuk kita baca. Ini sebagai bentuk mitigasi kultural terhadap kerusakan lingkungan. Sungai Mahakam tidak kita pahami sekadar sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai entitas hidup yang memiliki makna sosial, spiritual, dan ekologis bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Pendekatan Interdisipliner
Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian budaya lokal, ekofeminisme, dan ekologi politik, buku ini menafsirkan krisis iklim sebagai krisis relasi. Yakni terputusnya hubungan harmonis antara manusia dan alam akibat dominasi logika pembangunan ekstraktif dan eksploitatif (Escobar, 2018).
Dalam perspektif ini, banjir, degradasi daerah aliran sungai, pencemaran, serta konflik ekologis di kawasan Sungai Mahakam kita pahami sebagai konsekuensi dari pengingkaran terhadap etika ekologis yang dahulu hidup dalam narasi mitologis masyarakat setempat.
Lebih jauh, buku ini memperkaya state of the art kajian ekologi–budaya di Indonesia dengan menjadikan mitos lokal sebagai teks sentral dalam membaca krisis iklim.
Mitos tidak sekadar kita perlakukan sebagai warisan budaya yang patut kita lestarikan, tetapi sebagai arsip ekologis sekaligus perangkat kritik terhadap modernitas yang berwatak ekstraktif. Keunikan lainnya terletak pada integrasi perspektif ekofeminisme dalam konteks lokal Kalimantan Timur. Sebuah pendekatan yang masih relatif jarang dalam literatur Indonesia.
Dengan demikian, buku ini dapat kita posisikan sebagai salah satu kontribusi awal yang penting dalam mengembangkan kajian ekofeminisme berbasis narasi lokal dan sungai sebagai ruang hidup. Ia tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga menawarkan arah metodologis baru bagi studi ekologi–budaya di Indonesia. Yakni pendekatan yang menggabungkan mitologi, kritik politik, dan analisis gender dalam satu kerangka yang saling terhubung.
Kalimantan: Keyakinan, Budaya, dan Relasi dengan Iklim
Dalam salah satu sub-babnya, Kurniati dan Candraningrum menggambarkan kehidupan masyarakat Kalimantan yang memiliki keterikatan mendalam dengan alam. Yakni melalui dimensi spiritual, budaya lisan, ritual, dan mitos. Bagi banyak komunitas adat di Kalimantan, alam bukanlah sekadar latar kehidupan, melainkan ruang hidup yang terpenuhi makna dan relasi simbolik.
Suku Dayak, misalnya, memaknai alam Kalimantan melalui simbol Burung Enggang yang merepresentasikan dunia atas, sekaligus menjadi penghubung antara langit dan bumi. Burung ini tidak hanya hadir sebagai simbol estetis, tetapi sebagai penanda kosmologis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Dayak tentang keseimbangan semesta.
Simbolisasi hewan dalam mitos tidak hanya kita temukan pada masyarakat Dayak. Kelompok-kelompok Melayu Kalimantan seperti suku Banjar dan suku Kutai juga mengembangkan simbol-simbol mitologis yang berakar pada ketergantungan mereka terhadap sungai.
Jika masyarakat Dayak memusatkan kosmologinya pada hutan, masyarakat Melayu Kalimantan memusatkannya pada sungai sebagai sumber kehidupan. Dalam konteks ini, Naga mereka posisikan sebagai simbol alam bawah. Penjaga dasar sungai yang tergambarkan dalam wujud besar dan melingkar, sehingga terkenal sebagai Naga Lipat Bumi.
Mitos-mitos yang tumbuh di tanah Kalimantan merupakan hasil perjumpaan kolektif antara manusia, hewan, dan kondisi geografis alam. Ia lahir dari pengalaman hidup sehari-hari, sekaligus menjadi mekanisme sosial untuk membaca tanda-tanda alam, meramalkan bahaya, dan membangun bentuk perlawanan simbolik.
Mekanisme Pengendalian Sosial
Pantangan-pantangan yang terkandung dalam mitos menciptakan konsekuensi kolektif berupa rasa takut dan kepatuhan. Hingga pada akhirnya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial agar manusia tidak melampaui batas ekologis yang telah ditetapkan leluhur.
Kisah Putri Karang Melenu dan Naga Sungai Mahakam, misalnya, tidak dapat terlepaskan dari sejarah Sungai Mahakam dan peradaban budaya Kutai. Sungai ini bukan hanya jalur ekonomi dan transportasi, tetapi juga pusat tumbuhnya peradaban, kekuasaan, dan identitas kultural. Sepanjang aliran Mahakam—dari Kutai Lama, Muara Kaman, hingga Mahakam Hulu—terdapat jejak-jejak budaya lokal yang masih hidup dalam praktik keseharian masyarakat.
Secara implisit, Kurniati dan Candraningrum mengajak pembaca untuk memahami bahwa sungai dan hutan di Kalimantan memiliki keterhubungan yang tidak terpisahkan. Di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pembangunan semestinya tidak mengabaikan keseimbangan ekologis. Hutan tropis Kalimantan dengan tanahnya yang subur dan keanekaragaman hayatinya adalah anugerah yang menuntut tanggung jawab moral dalam pengelolaannya.
Namun, realitas menunjukkan bahwa kerusakan ekologis terus terjadi. Populasi pesut Mahakam, satwa endemik sungai, mengalami penurunan drastis. Ini terjadi akibat tabrakan dengan baling-baling kapal ponton, pencemaran air, limbah industri, polusi bahan bakar, serta dampak perubahan iklim ekstrim.
Dalam konteks ini, kepedulian menjadi prasyarat utama untuk memulihkan luka ekologis Sungai Mahakam. Kepedulian tersebut menuntut perubahan cara berpikir. Meninggalkan pola eksploitasi, manipulasi, dan perusakan alam.
Putri Karang Melenu dan Naga Sungai Mahakam: Mitos, Sejarah, dan Identitas
Kurniati dan Candraningrum tidak sekadar mengajak pembaca mengenal mitos sebagai cerita rakyat, tetapi mendorong pembacaan sejarah yang lebih utuh tentang asal-usul peradaban di Kalimantan Timur. Proses islamisasi sejak abad ke-13 membawa transformasi besar dari kerajaan bercorak Hindu menuju kesultanan Islam. Namun, jejak kepercayaan lama tidak sepenuhnya hilang, melainkan bertransformasi dan berkelindan dengan keyakinan baru.
Kepercayaan terhadap kelahiran Putri Karang Melenu dan keberadaan Naga sebagai penjaga Sungai Mahakam berakar pada pandangan kosmologis tersebut. Putri Karang Melenu diyakini muncul dari dasar Sungai Mahakam—sebuah kelahiran yang tidak lazim dan sarat makna simbolik. Ia dipandang sebagai sosok sakral, karunia bagi masyarakat, dan nenek moyang para raja Kutai.
Dalam pembacaan sejarawan Muhammad Sarip, mitos ini dapat dimaknai secara simbolik. Putri Karang Melenu merepresentasikan penduduk asli Kalimantan, sementara Aji Batara Agung Dewa Sakti—yang dikisahkan turun dari langit—melambangkan pendatang dari Jawa. Pernikahan keduanya mencerminkan pertemuan dua dunia: lokal dan pendatang, bumi dan langit, sungai dan daratan.
Perayaan Erau yang terselenggara setiap tahun menjadi ruang kolektif bagi masyarakat Kutai untuk mengenang kisah Putri Karang Melenu. Dalam perayaan ini, perempuan adat memegang peran strategis sebagai penjaga tradisi, penyambut tamu, dan penggerak harmonisasi budaya. Tradisi Betempong Tawar yang diwariskan dari Putri Karang Melenu menjadi simbol penghormatan, diplomasi, dan keramahan budaya.
Agensi perempuan dalam tradisi ini menunjukkan bahwa perempuan Nusantara memiliki kesadaran diri, kebebasan, dan kekuatan resiliensi budaya. Perempuan bukan sekadar objek glorifikasi, melainkan subjek aktif yang berperan dalam ruang domestik maupun publik, serta dalam pelestarian budaya dan relasi ekologis.
Di sisi lain, mitos tentang Lembuswana dan Naga Sungai Mahakam memperlihatkan bagaimana hewan mitologis diposisikan sebagai simbol kekuatan, perlindungan, dan kesejahteraan. Naga dipandang sebagai penjaga sungai, sekaligus pengingat akan konsekuensi moral jika manusia melanggar etika ekologis. Ketakutan akan bala bencana berfungsi sebagai mekanisme kultural untuk menjaga keseimbangan relasi manusia dengan alam.
Mitigasi Krisis Alam: Keterhubungan dan Kasih Sayang
Kalimantan sering kita sebut sebagai paru-paru dunia, namun kenyataan menunjukkan bahwa deforestasi, krisis air, kepunahan spesies, dan perampasan ruang hidup masyarakat adat terus terjadi. Sungai Mahakam sebagai sungai utama di Kalimantan Timur menjadi saksi dampak pencemaran dan perubahan iklim ekstrem, yang paling dirasakan oleh masyarakat adat di sekitarnya.
Menghadirkan kembali pengetahuan dan praktik masyarakat adat yang memiliki kedekatan kultural dengan alam menjadi salah satu refleksi penting dalam merespons krisis iklim. Mitigasi krisis iklim tidak cukup kita pahami sebagai urusan teknis, tetapi sebagai tanggung jawab etis dan politis yang melibatkan nilai introspeksi, solidaritas, dan demokrasi ekologis.
Pendekatan egaliter yang berpihak pada sosio-kultural menegaskan bahwa bumi adalah tanggung jawab bersama. Mitos Putri Karang Melenu dan Naga Sungai Mahakam merepresentasikan spiritualitas berbasis bumi yang mengajarkan keterhubungan manusia dengan alam. Kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam melahirkan rasa kasih sayang, empati, dan tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan kehidupan.
Kasih sayang terhadap alam bukanlah konsep abstrak, melainkan kemampuan untuk menghargai kehidupan lain sebagaimana kita menghargai kehidupan manusia. Dari kesadaran inilah lahir etika perawatan, welas asih, dan komitmen untuk menjaga bumi sebagai ruang hidup bersama. []