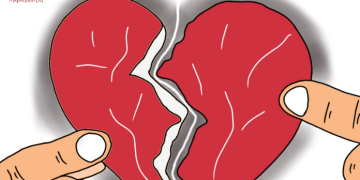Mubadalah.id – Membaca berita situasi dan kondisi sosial politik Indonesia akhir-akhir ini bikin gerah dan resah. Masuk ke Agustus ini, selain polemik pengibaran bendera one piece, alih-alih merah putih untuk merayakan kemerdekaan, juga isu kenaikan pajak di beberapa segmen potensi ekonomi. Paling anyar, kenaikan pajak hingga 250 persen di Kabupaten Pati Jawa Tengah hingga mengundang simpati untuk menggalang aksi pada 13 Agustus 2025 nanti.
Mengapa kita sebagai perempuan harus peduli dengan isu politik? Bagaimana upaya perlawanan perempuan menyikapi situasi ini? Mari kita bahas!
Kita sering masuk dalam logika pemisahan ruang publik dan domestik yang ditetapkan oleh aturan-aturan hukum patriarki dan kebutuhan keberlangsungan kapitalisme. Diktum gerakan feminis sudah berulang kali menegaskan yang personal itu politis. Demikian yang saya baca dari kata pengantar buku “Yang Terlupakan dan Dilupakan: Membaca Kembali Sepuluh Penulis Indonesia.”
Ketika harga cabe naik, pengamat ekonomi-politik heboh. Konon itu urusan personal. Namun di sisi lain pemukulan terhadap pacar atau istri langsung dianggap urusan pribadi. Padahal bisa jadi suami memukuli istri karena sambal yang istrinya buat kurang cabe, akibat harga cabe yang melambung.
Antara Feminisme dan Nasionalisme dalam Sejarah
Ayu Ratih melalui kata pengantar di dalam buku tersebut juga mencatat bagaimana perempuan memperlihatkan kedekatan antara feminisme dan nasionalisme dalam sejarah. Meskipun ada paradoks yang muncul oleh keduanya.
Kesadaran feminis dalam berbagai rupa tumbuh di nusantara bersamaan dengan bangkitnya kesadaran kebangsaan. Ruang-ruang belajar dan bergerak perempuan paling awal memungkinkan karena bantuan para lelaki terdekat. Apakah itu sosok ayah, saudara laki-laki, suami, pacar atau teman-teman sekerja.
Laki-laki yang berpikir tentang kemajuan bangsa, dengan melihat pentingnya peran perempuan terdidik untuk melawan praktik-praktik feodal kolonial yang menindas perempuan. Seperti poligami, perkawinan anak, dan pergundikan.
Kenyataan di atas menunjukkan adanya kerja sama yang baik antara laki-laki dan perempuan. Kata lain, ada kesalingan yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sekaligus juga membebaskan perempuan dari segala macam bentuk penindasan.
Meski demikian, gerakan nasionalisme juga masih membatasi ruang gerak perempuan. Yakni dengan menekankan peran perempuan sebagai “Ibu Bangsa” yang melahirkan dan mendidik putra-putri harapan bangsa.
Menyoal “Ibuisme Negara”
Terkait Ibu Bangsa, begitu banyak tulisan dari masa ke masa yang berisi tentang pemujaan terhadap kerja rumah tangga, di mana justru semakin menjebak perempuan sebatas pada peran tersebut. Ibu-ibu Belanda yang datang berbondong-bondong ke Hindia Belanda pada awal abad ke-20 membawa misi Victorian untuk mendidik ibu-ibu inlander menjadi ibu rumah tangga yang baik.
Proses demikian yang sosiolog Madelon Djajadiningrat namakan sebagai “Pengiburumahtanggaan.” Hal ini mendapat sambutan baik di kalangan ibu-ibu priyayi Jawa dan ibu-ibu terdidik lainnya di luar Jawa.
Lantas di masa pemerintahan Soeharto gagasan keibuan kolonial ini negara adopsi untuk mengatur gerak perempuan yang Soeharto anggap kelewat “liar” pada masa Soekarno. Feminis Julia Suryakusuma menyebut ideologi penaklukan ini dengan sebutan “Ibuisme Negara.”
Strategi Perlawanan Perempuan
Para perempuan pendiri bangsa bukannya tidak tahu bahwa mereka dimanfaatkan untuk menjaga gawang reproduksi sosial. Di antara mereka ada yang nekat merangsek ke daerah musuh, seperti Charlotte Salawati Daud (20 Maret 1909 – 10 Maret 1985) yang menolak ditempatkan di satu sudut berbangsa.
Langkah berbeda Maria Ulfah Santoso (18 Agustus 1911 – 15 April 1988) perlihatkan, yang menganggap konfrontasi terhadap kungkungan dan pembatasan tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Apalagi jika sebagian perempuan percaya bahwa menjadi ibu adalah ruang berjuang utama dalam pendirian bangsa.
Perempuan-perempuan cerdik ini menemukan berbagai strategi untuk memanfaatkan dan mewarnai keragaman ruang nasional. Tujuannya agar suara perempuan selalu terdengar, bahkan dalam suara yang paling lirih sekalipun.
Ya kerja-kerja kepenulisan, menulis dalam senyap sambil merekam beragam peristiwa yang perempuan temui di kehidupan sehari-hari. Bagaimana para perempuan melawan macam-macam upaya patriarki untuk menempatkan pengetahuan perempuan sebagai yang pernah Michael Foucault sebutkan adalah subjugated knowledges, atau pengetahuan yang ditindas. Pengetahuan yang dianggap naif dan tidak memadai untuk menjelaskan suatu fenomena secara kognitif dan ilmiah.
Lantas bagaimana dengan perlawanan perempuan hari ini? Saya melihat ruang perempuan lebih terbuka hari ini, dan lebih banyak kawan yang bisa kita ajak bekerja sama. Dengan cara apapun perlawanan itu, baik aksi, demonstrasi, orasi, audiensi, advokasi ataupun ruang senyap literasi, langkah itu harus tetap tegak berjalan.
Cerita tentang perlawanan perempuan di zaman kiwari ini, kelak akan menjadi sejarah esok hari, sebagaimana yang pernah Charlotte Salawati Daud ataupun Maria Ulfah Santoso lakukan. Mereka telah menorehkan catatan sejarah yang berharga dan penuh makna. Saatnya kini giliran kita. Panjang umur perjuangan! []