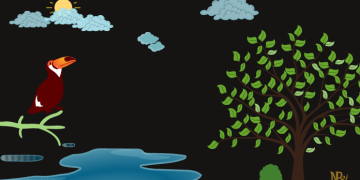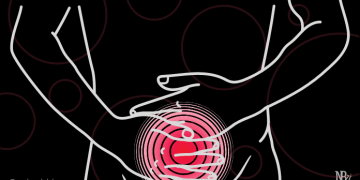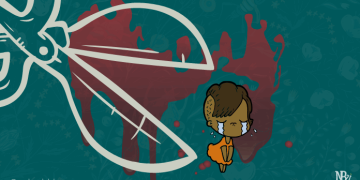Mubadalah.id – Beberapa hari yang lalu, sebuah portal berita nasional menampilkan headline berita bertajuk “Ramai-ramai Guru PPPK di Blitar Izin Ceraikan Suami, Ini Alasannya.”
Dari judul yang sudah dari awal melakukan calling-out terhadap pilihan perempuan tersebut kita sudah dapat menduga bahwa fokus utama pemberitaan ini adalah menyoroti gugatan cerai yang dilakukan perempuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.
Bukan untuk membicarakan faktor yang lebih krusial di balik peristiwa massal tersebut. Seperti adanya alarm disfungsi institusi pernikahan, misalnya. Maka ketika berita tersebut akhirnya menjadi konten media sosial, isi kolom komentarnya tak jauh-jauh dari cemoohan terhadap sikap para perempuan PPPK yang mereka anggap tidak tahu diri. Alasasannya karena meninggalkan pasangan setelah mendapat kehidupan yang lebih layak.
Ada pula yang membawa paradigma keagamaan yang diyakininya, bahwa akibat dari perempuan yang diperbolehkan bekerja di ruang publik akan merusak pernikahan.
Padahal, secara nasional trend perceraian di Indonesia memang cenderung meningkat sejak 5 tahun ke belakang. Jika kita bandingkan dengan angka perceraian tahun 2020 yang hanya mencatat 291.677 kasus perceraian, angka perceraian tahun 2024 meningkat hingga 35%, yaitu sejumlah 394.608 kasus perceraian.
Tingginya Angka Perceraian
Apakah tingginya angka perceraian ini penyebabnya faktor ekonomi? Data dari Goodstats menyebut bahwa alasan ekonomi menduduki urutan kedua terbanyak dalam faktor penyebab perceraian. Alasan ini muncul setelah pertengkaran dan perselisihan yang mendominasi dengan rasio hampir dua kali lipat dari alasan ekonomi.
Dari sini saja kita dapat memperkirakan bahwa komentar warganet terhadap fenomena di atas, yang menduga bahwa para istri di Blitar mengajukan gugatan cerai terhadap pasangannya akibat alasan ekonomi tidak bisa sepenuhnya kita benarkan.
Bahkan jika benar alasan yang mereka kemukakan adalah alasan ekonomi, kita tidak dapat serta merta menyudutkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Terlebih karena meninggalkan pasangannya begitu saja ketika mendapatkan sumber pendapatan yang lebih layak.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kerentanan finansial kerap kali bukan faktor tunggal pemicu perceraian. Dalam banyak kasus kondisi tersebut justru menjadi alasan penunda perceraian bahkan ketika faktor-faktor lain sudah mendahahului.
Dalam kata lain, banyak pasangan yang menunda perceraian demi mempersiapkan kondisi finansial untuk menjalankan proses perceraian dan kehidupan pasca perceraian. Padahal mereka tahu bahwa kondisi rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan.
Hal ini mematahkan anggapan bahwa perempuan bekerjalah yang memicu terjadinya perceraian. Tapi kemandirian finansial mereka tersebut hanya memberikan ruang bagi mereka untuk keluar dari relasi yang tidak sehat atau bahkan disfungsional.
Mempertebal Stigma terhadap Perempuan
Alih-alih menyalahkan perempuan dan mempertebal stigma terhadap perempuan yang memilih bekerja di ruang publik, kita hendaknya lebih banyak membicarakan disfungsi institusi pernikahan dan relasi keluarga yang jarang terlihat sebagai akar masalah.
Bahkan pada berita terkait gugatan cerai pegawai PPPK tersebut, narasumber yang bahkan bukan pihak yang mengajukan gugatan cerai memberikan opini. Bahwa salah satu faktor penyebab maraknya gugatan tersebut adalah gap pendapatan dan jenis pekerjaan suami para penggugat.
Kutipan itu jugalah yang menjadi sasaran amukan warganet dan landasan untuk menghakimi keputusan para penggugat. Padahal, di media sosial maupun lingkungan sekitar, tak jarang kita melihat tanda-tanda disfungsi relasi keluarga seperti pengabaian (termasuk isu fatherless). Penyelesaian konflik yang buruk bahkan hingga kekerasan yang berujung pada terancamnya nyawa.
Hal-hal tak kasat mata ini kerap kali dianggap tak ada sehingga juga tidak mereka perhitungkan lebih lanjut sebagai salah satu faktor perceraian. Karena nyatanya, daripada menelusuri akar masalah yang dapat kita cegah dan kita petakan secara struktural, jauh lebih mudah dan murah untuk menyalahkan perempuan yang kita anggap sebagai figur tunggal yang bertanggung jawab terhadap fungsi keluarga terutama di ranah domestik.
Alarm bagi Penyelenggara Negara
Tingginya angka gugatan perceraian tersebut juga seharusnya menjadi sebuah alarm bagi penyelenggara negara. Yakni untuk melihat bahwa mereka gagal mengintervensi persiapan pernikahan secara struktural.
Sekalipun sejumlah lembaga telah menyelenggarakan pendidikan pra nikah, nyatanya hal tersebut tak efektif untuk mengenali kesiapan calon pengantin serta mengenali tanda bahaya ataupun isu-isu yang seyogyanya dapat kita tengahi sebelum memasuki jenjang pernikahan.
Namun karena kita terbiasa autopilot, sehingga mempertanyakan hal sistemik tidak menjadi default kita ketika melihat sebuah fenomena massal terjadi. Kita justru sibuk mencari individu yang dapat dipersalahkan. Dalam banyak hal individu tersebut adalah perempuan yang tak mampu menjaga keutuhan keluarga.
Padahal salah satu tujuan terbentuknya keluarga adalah menjadi ruang kolaborasi yang dapat mendukung potensi anggota keluarga di dalamnya. Bagi muslim, tujuan ini termaktub dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (litaskunuu ilaiha), dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
Kalimat tersebut mensyaratkan adanya proses terus menerus yang harus kita upayakan. Maka jika terjadi disfungsi di dalamnya sehingga mengakibatkan tak tercapai tujuan terbangunnya keluarga, seharusnya evaluasinya tidak hanya kita bebankan kepada satu pihak saja. []