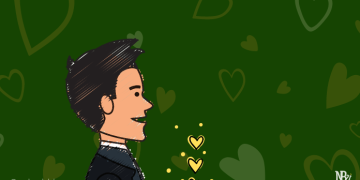Mubadalah.id – Hingga saat ini masih saja lini masa saya ramai akan berita penanganan kerumunan yang berkaitan dengan Tragedi Kanjuruhan yang memilukan. Berbagai acara musik yang dianggap tidak terkendali segera pihak kepolisian hentikan karena trauma penanganan massa yang tidak sempurna.
Berada di posisi yang serba salah, Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah kadung memiliki citra yang dipandang sebelah mata namun tetap harus menjalankan tugas dalam memastikan kerumunan tidak bersifat mematikan.
Bagaimana masyarakat tidak meremahkan, gas air mata yang aparat kepolisian tembakkan menjadi alat pembunuh 135 orang pada 1 Oktober yang lalu. Tindakan yang katanya sudah sesuai prosedur tersebut menambah kebobrokan citra kepolisian yang seolah-olah tidak ada habisnya. Pasalnya pada tahun ini keburukan polisi turut terkuak melalui film dokumenter Kilometer 50 oleh Tempo pada 15 September yang lalu.
Film tersebut mengungkap penembakan sepihak yang pihak kepolisian lakukan terhadap anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di tahun 2020. Sebanyak 6 orang anggota FPI meninggal di kilometer ke-50 ruas jalan tol Jakarta – Cikampek. Dan tentunya rakyat Indonesia tidak akan melupakan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, atau Brigadir J oleh atasannya, mantan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, pada bulan Juli 2022.
Menurut Amnesty International, lethal force atau kekerasan yang mematikan seharusnya menjadi senjata terakhir yang pihak kepolisian gunakan. Namun, dari tiga contoh kasus di atas, nampaknya tidak demikian penerapannya di Indonesia.
Kekerasan sebagai Penyelesaian Masalah bagi Polisi
Desember 2021 saya ngobrol dengan seorang teman yang berkantor di tengah kota Jakarta. Hari itu bertepatan dengan Reuni 212 yang asal muasalnya adalah aksi bela agama oleh FPI. Teman saya kemudian ingat cerita rekan kerjanya yang pernah terjebak di tengah kemacetan akibat demonstrasi 212 besar-besaran tahun 2018 silam. Pasalnya rekannya tersebut sedang mengantarkan jenazah ayahnya untuk dikuburkan. Walau sesama Islam, rekan kerja teman saya merasa sangat dirugikan.
Sebanyak lebih dari 700 orang Laskar FPI juga pernah melumpuhkan bandara Soekarno-Hatta di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya menyebabkan kemacetan, mereka juga berkerumun dan sebagian tidak mengenakan masker ketika menyambut imam besar mereka, Habib Rizieq, pulang ke Indonesia November 2020 yang lalu.
Memang tingkah laku FPI tidak selalu menyenangkan. Namun apakah pendisiplinan harus dilakukan dengan kekerasan hingga pembunuhan? Pada film Kilometer 50, Usman Hamid, selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyampaikan adanya kejanggalan dalam penembakan yang terjadi.
Mulai dari kronologi yang ditutup-tutupi hingga pensterilan tempat kejadian perkara (TKP) yang tidak dilakukan sesuai prosedur. Pada konferensi pers pihak kepolisian menunjukkan barang bukti senjata api milik FPI. Namun saksi lain menyatakan bahwa dia tidak melihat adanya senjata api milik FPI sama sekali di TKP. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan terhadap cara kepolisian dalam menyikapi organisasi masyarakat yang dianggap mengganggu ketentraman.
Penggunaan Kekerasan
Penggunaan kekerasan tidak dilakukan kepada masyarakat sipil saja. Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo menjadi bukti bahwa kekerasan juga terjadi di dalam tubuh kepolisian sendiri. Brigadir J tewas dengan 7 luka tembakan di tubuhnya.
Motif pembunuhan mereka isukan mulai dari pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, hingga perselingkuhan yang pasangan suami istri tersebut lakukan. Konflik yang seharusnya dapat mereka pecahkan menggunakan perangkat hukum dan undang-undang malah mereka selesaikan dengan jalan kekerasan.
Kini perhelatan sepak bola menjadi korban kebrutalan polisi berikutnya. Pada tragedi Kanjuruhan, alasan pihak kepolisian yang mengecewakan masyarakat adalah prosedur penembakan gas air mata yang katanya wajar mereka lakukan. Akan tetapi, kurangnya perhitungan membuat ratusan orang, termasuk 35 orang anak-anak menjadi korban.
Dalam satu tahun saja, sudah ada tiga bukti bobroknya institusi kepolisian di negara ini. Layakkah mereka berdiam diri?
Empati dan Edukasi sebagai Solusi
Sebagai institusi yang sangat maskulin, perubahan sudut pandang cara kerja kepolisian dapat menjadi salah satu saran. Empati serta edukasi dapat menjadi kunci untuk masalah ini.
Misalnya FPI, jika kita telusuri ternyata ada unsur kekecewaan politik yang membuat mereka secara radikal membela diri. Selama Orde Baru presiden Soeharto membatasi segala ekspresi keagamaan di kegiatan bermasyarakat termasuk FPI.
Selain dibatasi ekspresi dan kegiatannya, cikal bakal perlawanan FPI adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Sehingga ketika Soeharto lengser, era Reformasi menjadi kesempatan bagi mereka untuk muncul dan menjadi organisasi masyarakat yang mandiri.
Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan FPI ternyata merambah ke urusan-urusan yang lain. Salah satunya adalah menjadi ‘polisi moral’ yang hobi sweeping tempat-tempat hiburan malam. Bahkan tak jarang patroli mereka tersebut dibarengi dengan tindakan perusakan. Maka premanisme ikut menjadi citra FPI hingga dibubarkannya mereka pada Desember 2020 yang lalu. Lantas apakah penembakan terhadap mereka layak dibenarkan?
Memang mengambil keputusan secara politis tidak selalu menjadi ranah polisi. Sehingga salah satu strategi pihak kepolisian yang dapat mereka lakukan adalah memahami sejarah dan latar belakang organisasi masyarakat seperti FPI. Selain koordinasi setiap kegiatan di muka publik, edukasi dan terciptanya dialog seharusnya dapat menjadi ide selanjutnya.
Imam besar dan pejabat-pejabat FPI lainnya paling paham agenda politik apa yang mereka lakukan. Namun para jamaah dan pengikutlah yang butuh dialog dan diskusi mengenai Islam yang moderat dan tidak merugikan orang lain. Esensi dari FPI yang melawan penindasan dari penguasa yang tidak adil harus mereka kembalikan.
Pun tidak dapat terwujud, membuntuti serta menembaki Laskar FPI ketika akan menghadiri pernikahan anak dari imam besar mereka tentu tidak tepat. Empati terhadap isu keluarga oleh polisi tidak terlihat di sini.
Dekonstruksi Sudut Pandang
Begitu pula dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Jika memang ada isu perselingkuhan, apakah 7 peluru yang bersarang di tubuh korban bisa menyelesaikan masalah? Lalu jika benar ada kasus kekerasan seksual, mengapa tidak langsung menggunakan UU TPKS sebagai alat hukum terduga pelaku? Apabila alasannya adalah aib dan malu, maka isu sensitif gender seperti kekerasan seksual masih menjadi PR bagi kepolisian di negara ini.
Perihal penanganan pertandingan sepak bola, seorang sahabat bercerita bahwa pertandingan yang ia hadiri pada 2011 silam juga polisi disiplinkan menggunakan gas air mata. Padahal para penonton tidak melakukan kekerasan dan vandalisme apapun. Mereka hanya mengekspresikan rasa senang dengan wajar, semangat, dan lantang.
Pemahaman akan pack mentality dari penonton sepak bola harus kita pelajari dengan baik oleh pihak kepolisian. Euphoria yang seringkali terlihat berbahaya mungkin bisa kita siasati dengan gertakan serta pemisahan yang membuat potensi keroyokan berkurang, tata ruang stadion yang membatasi pergerakan penonton, dan penyelenggara yang memperbanyak tim pengamanan.
Maka pihak kepolisian tidak perlu memfasilitasi rasa takut mereka sendiri akan jumlah yang kalah banyak dari penonton. Sehingga gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan tidak lagi menjadi solusi.
Konsultasi dan sensitivity training yang memakan waktu panjang memang tidak mungkin kita lakukan dalam waktu yang singkat dan padat. Dekonstruksi sudut pandang kepolisian yang patriarki juga sangat kita butuhkan. Tanpa adanya usaha untuk memahami masyarakat secara menyeluruh, maka adaptasi slogan “Mengayomi dan Melayani” yang mereka adaptasi dari UUD 1945 Pasal 30 ayat 4 nampaknya harus kita revisi. []