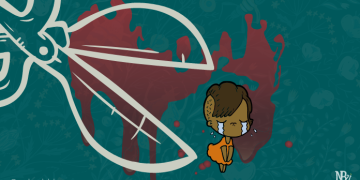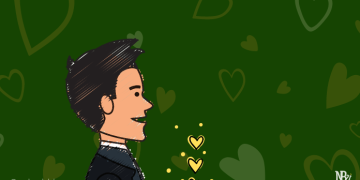Mubadalah.id – Baru-baru ini video vokalis Aftershine berinisial H beredar di berbagai platform media sosial. Namun sayangnya kolom komentar di konten-konten tersebut bukan berisi apresiasi terhadap musik ataupun vokal H. Ia justru menjadi korban pelecehan seksual secara verbal oleh warganet.
Komentar-komentar menjijikkan yang mengarah kepada seksualisasi terhadap sang vokalis yang kebanyakan dilontarkan oleh perempuan membanjiri akun mereka. Parahnya lagi, hal ini seperti turut didukung oleh banyak perempuan lain. Mereka seolah menikmati cara seksualisasi terhadap H melalui pelecehan verbal di kolom komentar.
Hal serupa juga sempat kutemui di kolom komentar konten-konten atlet laki-laki
Komentar terhadap bentuk tubuh mereka yang mengarah kepada seksualisasi juga nampak dinormalisasi oleh para penggemar perempuan. Padahal di waktu yang sama, para perempuan yang lain barangkali tengah berusaha sembuh dari trauma akibat pelecehan seksual.
Barangkali atas dasar hal tersebut pula, lahir komentar seperti “kalau di balik gendernya pasti langsung kita teriaki pelecehan seksual.” Karena memang yang terjadi kita seolah menetapkan standar ganda, bahwa komentar bernada seksualisasi kepada perempuan adalah pelecehan, tetapi jika kita lontarkan kepada laki-laki maka bukan pelecehan. Padahal, kepada siapapun komentar seksualisasi kita lontarkan, hal tersebut tetaplah pelecehan seksual.
Standar ganda itu tanpa sadar di kemudian hari justru akan menjadi boomerang bagi sesama perempuan. Misalnya dalam hal pencegahan kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO),
Bukan tidak mungkin akan ada invalidasi terhadap pelaporan KBGO melalui komentar jahat seperti “kalau pelakunya ganteng pasti nggak lapor.” Dan sejenisnya.
Empati terhadap Korban
Kita perempuan biasanya lebih mudah berempati terhadap perempuan lain yang menjadi korban kekerasan seksual. Tapi kenapa empati yang sama tidak bisa kita berikan kepada laki-laki korban kekerasan seksual? Apakah kita menganggap bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban, karena mereka pasti menikmati seksualisasi yang kita lakukan tanpa izin terhadap mereka?
Jika benar demikian, nampaknya kita perlu segera berbenah. Karena sikap tebang pilih tersebut tidak akan membawa kebaikan apapun selain justru menggerogoti gerakan kolektif perempuan dari dalam.
Di saat perempuan banyak menyuarakan pemenuhan hak seperti instrumen penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual, tapi sebagian dari kita justru melanggengkan bentuk kekerasan seksual dan bahkan menjadi pelakunya.
Terlebih bagi kita perempuan yang nantinya memilih untuk menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Akan berbahaya jika sejak mula kita menormalisasi kekerasan seksual atau bahkan menjadi pelakunya.
Ketidakpekaan kita bisa menjadikan kita lalai mendidik anak-anak kita supaya tidak menjadi pelaku kekerasan seksual dan juga tak mampu mengajarkan cara mencegah diri menjadi objek seksual oleh orang tak bertanggung jawab. Karena kita sendiri sebagai orang tuanya tak memiliki pemahaman yang baik untuk memberikan pendidikan tentang kekerasan seksual kepada anak.
Hifdzun Nafs
Jangan lupakan juga bahwa korban tetaplah korban. Apapun gendernya, potensi trauma tetap ada. Bahkan di tengah iklim maskulin yang toksik. Trauma pada laki-laki korban kekerasan seksual lebih rentan diinvalidasi oleh lingkungan sekitarnya. Akibatnya, akses terhadap bantuan hukum dan psikologis juga jadi lebih sulit didapatkan.
Kita juga perlu mengingat kembali bahwa dalam ajaran moral apapun, termasuk agama, kita diajarkan untuk saling menghormati hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang aman tanpa kekerasan dan pelecehan yang merendahkan martabat mereka. Menormalisasi kekerasan seksual verbal, berarti juga menabrak sumber nilai moral yang kita yakini.
Dalam Islam, kita mengenal maqashid syariah yang salah satu pilarnya adalah “hifdzun nafs” atau menjaga diri dan jiwa sesama manusia. Amanat tersebut berimplikasi pada keharusan kita menjaga martabat sesama manusia dengan tidak merendahkan harga diri dan menjadikannya objek seksual semata. []