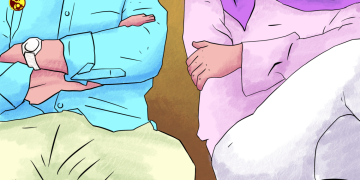Mubadalah.id – Beberapa waktu lalu, saya sempat membaca tulisan dari Faqihuddin Abdul Kodir yang mendiskusikan makna ghadd al baṣr dalam QS. al-Nūr [24]: 30-31. Pada esai tersebut, Faqihuddin berargumen bahwa ghadd al-baṣr tidak hanya berurusan dengan penundukan pandangan fisik. Namun, perintah ini juga berkaitan erat dengan bagaimana manusia mengendalikan cara pandangnya terhadap yang-lain.
Dalam konteks relasi bersama lawan jenis, makna ghadd al baṣr merupakan bagian dari etika yang menekankan urgensi untuk memandang perempuan sebagai subjek utuh yang memiliki dimensi intelektual, moral, sosial, hingga spiritual, begitupun sebaliknya.
Alih-alih memosisikan salah satu jenis kelamin sebatas objek seksual semata, perintah ghadd al baṣr justru bermaksud untuk menata pandangan umat manusia agar memandang setiap individu, tak terkecuali perempuan, sebagai agen kehidupan yang dapat berkontribusi bagi penjagaan, penguatan, dan perwujudan kebaikan dan ketakwaan di muka bumi.
Keragaman Makna Ghadd al Basr dalam Tafsir Modern
Penting untuk kita kemukakan bahwa pemaknaan progresif dan resiprokal seperti ini belum begitu familiar bagi beberapa kalangan Muslim di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang justru menjadikan ayat ini sebagai landasan untuk melarang interaksi antara laki-laki dengan perempuan di ruang publik, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain-lain.
Padahal, jika mengikuti alur argumen Faqihuddin, yang ia kehendaki dari ayat ini adalah upaya untuk menciptakan suatu budaya dan tatanan publik yang etis. Artinya, interaksi antar lawan jenis tidak perlu kita negasikan untuk menghindari peristiwa amoral. Namun, interaksi tersebut mesti kita bingkai dalam suatu perspektif etis yang mengapresiasi keutuhan masing-masing individu dalam relasionalitasnya satu sama lain.
Tulisan ini kemudian bertujuan untuk mengeksplorasi makna QS. al-Nūr [24]: 30-31 yang terekam dalam kitab-kitab tafsir modern. Secara spesifik, saya hendak mengajak pembaca untuk menelusuri bagaimana para komentator Al-Qur’an mengembangkan pemaknaan terhadap ghadd al baṣr dalam konteks modern.
Tidak hanya itu, saya akan menunjukkan bahwa terdapat kekayaan produk makna dari pergulatan hermeneutis mereka terhadap perintah ghadd al-baṣr yang dapat kita kembangkan untuk menghasilkan suatu perspektif etis.
Dengan mengulas keragaman makna dalam tafsir modern, tulisan ini kita harapkan dapat memberikan intensif terhadap pengembangan sentimen moral dan kultivasi keutamaan etis bagi umat Muslim. Terutama dalam melihat relasi antar laki-laki dan perempuan di ruang publik.
Ghadd al-Baṣr dan Respons atas Modernitas Kolonial Barat
Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana Hamka menafsirkan perintah ghadd al baṣr. Dalam Tafsir al-Azhar (2001, pp. 4923–4931), Hamka memulai diskusinya dengan menyatakan bahwa aktivitas reproduksi merupakan sesuatu yang niscaya bagi umat manusia dalam rangka mempertahankan keberadaan spesies mereka di bumi.
Dalam konteks ini, makna ghadd al baṣr merupakan tuntunan etis dari agama agar setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, senantiasa memelihara kehormatan diri. Selain itu menjamin kebersihan jiwanya dengan bertanggung jawab secara moral, terutama dalam aspek reproduktif tersebut.
Pada saat yang sama, Hamka mengusulkan tinjauan krits terhadap pergaulan modern dari peradaban Barat yang begitu bebas dan permisif. Normalisasi seks bebas, bagi Hamka, terbukti telah mendatangkan berbagai penyakit yang mengerikan bagi umat manusia. Hamka juga menyebut sejumlah praktik seksual menyimpang yang lahir dari normalisasi semacam ini.
Lebih jauh lagi, Hamka mengidentifikasi bahwa krisis semacam ini tidak dapat terpisahkan dari ide-ide filosofis yang melatari peradaban Barat modern.
Ia lalu menyoroti pandangan psikoanalisis Sigmund Freud yang menyatakan bahwa asal-usul dari seluruh aktivitas manusia adalah energi seksual terpendam (libido) (Thurschwell, 2000). Karena agama ia pandang lahir dari fenomena Oedipus Complex dan cenderung menekan fitrah alamiah manusia, menjalankan ajarannya. Bagi Freud, hanya akan mengantarkan seseorang pada berbagai jenis penyakit jiwa.
Merespons gagasan tersebut, Hamka menulis bahwa ajaran agama, dalam hal ini ghadd al baṣr, tidak sedang hendak menegasikan dorongan instingtif manusia. Namun, ia bermaksud untuk mengaturnya dalam bingkai etika. Alih-alih membiarkan manusia terjebak pada kebebasan semu yang destruktif, agama datang untuk menjaga kemuliaan manusia dan mengantarkan mereka pada puncak kemanusiaan.
Agensi Moral Perempuan
Menarik untuk kita catat bahwa ketika membingkai perintah ghadd al baṣr dalam kerangka tanggung jawab moral, Hamka juga mengafirmasi agensi moral perempuan dengan menyatakan bahwa Tuhan memerintahkan jiwa perempuan untuk berkembang dan menuju kesempurnaannya sama seperti Tuhan memerintahkannya kepada jiwa laki-laki. Hamka bahkan melihat kejumudan dalam dunia Islam yang membatasi realisasi diri perempuan, baik pada ruang yang sakral maupun profan.
Hamka kemudian menutup ulasannya dengan mengajak umat Muslim untuk kembali kepada jalan tengah yang moderat. Yaitu, mewujudkan suatu budaya publik yang tidak mengurung dan menindas perempuan di satu sisi. Namun pada sisi lain, mengembangkan pikiran dan sikap bertanggung jawab dalam rangka membangun suatu tatanan masyarakat yang etis, beriman, dan bertakwa.
Selanjutnya, kita akan mengelaborasi penafsiran Sayyid Qutb terhadap ghadd al-baṣr (2003, pp. 2507–2513). Penulis Fī Ẓilāl Al-Qur’ān itu mengawali interpretasinya dengan menegaskan bahwa fokus Islam adalah kultivasi keutamaan etis dengan berfokus pada wiqāyah (pencegahan), bukan pada ‘uqūbah (hukuman).
Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang bersih dan beradab. Berkenaan dengan masalah reproduksi, Islam sama sekali tidak memerangi dorongan alamiah manusia sehingga mengancam kelanjutan hidup mereka di bumi.
Akan tetapi, Islam hendak menata dan memastikan terciptanya suatu atmosfer yang bersih bagi setiap individu. Dengan kata lain, Islam berusaha untuk mempromosikan suatu relasi yang etis dan damai bagi mereka. Bukan mengajarkan suatu bentuk asketisme yang menjauhkan diri dari interaksi dengan manusia.
Bagi Qutb, masyarakat ideal menurut Islam adalah masyarakat yang bersih dan tidak disibukkan oleh perkara hasrat biologis dan nafsu instingtif belaka. Penataan terhadap kecenderungan alamiah manusia akan mengantarkan setiap orang dalam berbagai lapisan masyarakat untuk berkontribusi terhadap pembangunan peradaban yang aman dan damai.
Menilik Perintah Ghadd al Basr
Pada titik ini, perintah ghadd al basr merupakan norma yang dapat mengkultivasi keutamaan etis. Pemaknaan yang menempatkan ghadd al baṣr sebagai etika keagamaan juga dapat kita jumpai dalam tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr (1984, pp. 203–205) karya Ibn ‘Asyur.
Dengan membiasakan diri mengikuti perintah tersebut, seseoang akan memiliki disposisi mental yang mampu menilai sesuatu secara bijak dan tepat. Selain itu menghindarkannya dari keburukan-keburukan moral. Qutb kemudian menegaskan bahwa makna ghadd al basr akan mengantarkan umat Muslim menuju kehormatan dan jati diri mereka yang sejati.
Imajinasi masyarakat semacam ini tidak dapat terpisahkan dari sikap intelektual Qutb yang resisten dan sangat anti terhadap apa saja yang datang dari Barat. Ia berpendapat bahwa westernisasi secara ekstensif menyebarluaskan pergaulan bebas yang merusak moralitas masyarakat Muslim.
Tidak hanya itu, westernisasi bahkan memberi dampak pada diseminasi paham materialisme yang dapat mengantarkan manusia pada tajrīd (pelepasan) dari nilai-nilai keutamaannya dan mengantarkannya kepada kondisi yang lebih hina dari hewan.
Sejalan dengan Hamka, Qutb juga mengkritik pandangan Freud yang sangat permisif bagi segala bentuk ekspresi dan praktik seksual, tanpa memikirkan konsekuensi medis dan spiritualnya.
Dalam hal ini, Qutb menulis, “saya telah melihat bagaimana suatu negara yang begitu permisif (terhadap hasrat dan kenikmatan duniawi) berusaha melarikan diri dari ikatan segala jenis aturan sosial, etis, religius, dan kemanusiaan sekaligus beralih kepada gaya hidup yang justru mengingkari asas kehidupan umat manusia.”
Dengan mengidentikkan Barat sebagai Jahiliyyah modern, Qutb melihat budaya eksesif Barat yang melumrahkan hal-hal yang diharamkan dalam hukum agama dan tidak dibenarkan dalam konstruksi etika. Hingga pada akhirnya akan mendatangkan berbagai penyakit masif, baik terhadap sisi psikologis maupun biologis manusia.
Ghadd al-Baṣr: Kultivasi Keutamaan Etis Umat Beriman
Mari beralih kepada para komentator Al-Qur’an modern dari tradisi Islam Syi’ah. Dalam al-Amṡal, Nasr Makarim Syirazi (2013, pp. 53–54) mengeksplisitkan kembali bahwa surat al-Nūr memusatkan perhatian pada ‘iffah (keluhuran budi/keutamaan etis) dan kesucian manusia.
Dengan mengidentifikasi makna ghadg al basr sebagai ‘pengurangan’, ‘perendahan’, dan ‘reduksi’, Syirazi memahami bahwa ayat ini tidak sedang memerintahkan manusia untuk menutup mata. Namun, perintah tersebut mengingatkan umat beriman agar tidak tenggelam dalam memandang yang-lain. Sehingga terhindar dari perspektif negatif dan amoral. Artinya, pandangan berikut interaksi terhadap lawan jenis di ruang publik itu dibolehkan sejauh tidak disertai dengan pandangan tidak etis yang merendahkan orang lain.
Makna semacam ini juga Mohsen Qeraati kemukakan (Qera’ati, 2014, pp. 151–153). Bahkan, Qera’ati menyatakan secara jelas bahwa makna ghadd al baṣr merupakan salah satu prinsip mendasar bagi keimanan seseorang. Sekaitan dengan ini, keutamaan seorang beriman dapat terukur dari sejauh mana ia mampu mengendalikan impuls-impuls instingtifnya.
Menurut Qera’ati, ketakwaan, sebagai keluhuran budi manusia, itu mulai dari bagaimana cara seseorang memandang. Pandangan yang bersih adalah muqaddimah (pendahulu) bagi al-akhlāq al-karīmah. Maka dari itu, bentangan pandangan yang tidak disertai dengan perspektif etis akan menghalangi pertumbuhan tatanan publik yang matang dan rasional.
Senada dengan Qera’ati, penulis Taqrīb Al-Qur’ān ilā al-Ażhān, M. al-Husaini al-Syirazi (2003, pp. 695–696), menandaskan bahwa maksud dari perintah ghadd al-Baṣr adalah untuk menyucikan jiwa manusia dan mengkultivasi keutamaan etis.
Min Wahy al Qur’an
Karya tafsir terakhir yang akan saya ulas adalah Min Waḥy Al-Qur’an karangan M. Husain Fadhlullah (1998, pp. 288–289). Terlebih dahulu, Fadhlullah menguraikan bahwa tujuan Islam adalah menginjeksikan nilai keutamaan ke dalam diri manusia, menyucikan jiwanya, dan mendidik karakternya.
Relasi antar manusia, termasuk dengan lawan jenis, terbingkai sedemikan rupa oleh Islam agar dorongan natural mereka tertata dengan baik. Muaranya adalah dunia bermoral yang dihuni oleh orang-orang dengan berbudi luhur.
Fadhlullah juga berusaha menjawab sejumlah kesalahpahaman dari sebagian pandangan yang berpendapat bahwa Islam mengabaikan individualitas perempuan dan membatasi kebebasan mereka. Kontras dengan itu, Islam justru mengapresiasi dimensi maskulinitas dan feminitas manusia secara seimbang dengan membingkainya ke dalam konstruksi etika yang universal, tandas Fadhullah.
Ia kemudian menyatakan bahwa relasi antara perempuan dengan laki-laki, terkhusus pada lembaga pernikahan, itu berdasarkan pada ikhtiyār (memilih yang baik) yang penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam hal ini, agama justru mendorong setiap individu untuk berelasi dengan pakem etika yang objektif.
Merestorasi Etika Keagamaan
Sekaitan dengan makna ghadd al baṣr, Fadhullah menyadur hadis ahl al-bait dari al-Kāfī yang menyatakan bahwa apa yang tidak diperbolehkan adalah pandangan penuh hasrat dan syahwat yang merendahkan perempuan, begitupun sebaliknya. Maksudnya, perintah ghadd al baṣr memperingatkan umat beriman untuk tidak menempatkan manusia sebagai objek seksual pemenuh nafsu belaka.
Fadhllah, seperti Makarim Syirazi, sama sekali tidak melarang interaksi sosial. Yang ia tekankan adalah bagaiman seseorang dapat menata pikiran dan emosinya sehingga dapat memandang orang lain secara etis. Maka dari itu, menjaga pandangan berarti menuntut penilaian etis setiap individu sebagai agen epistemis agar mereka senantiasa menyelaraskan diri dengan realitas moral yang universal.
Saya akan mengakhiri tulisan ini dengan kembali menegaskan bahwa pergulatan interpretatif dari para mufasir modern mencerminkan bagaimana mereka bergumul secara aktif terhadap realitas aktual dunia modern. Berhadapan dengan dominasi modernitas Barat yang menghadirkan sejumlah dilema moral bagi umat Muslim. Mereka hendak mengembalikan fungsi Al-Qur’an sebagai hudan (petunjuk) agar dapat memberikan respons yang memadai.
Selain merestorasi etika keagamaan yang dipandang objektif dan universal dan signifikan bagi laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu masyarakat etis. Pemaknaan terhadap makna ghadd al basr juga kita jadikan sebagai perangkat untuk mengkritik pikiran dan praksis dunia Barat. []