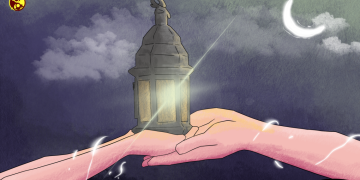Mubadalah.id – Dulu, saat masih kecil, saya hobi mengoleksi mobil-mobilan. Mobil Remot jadi salah satu yang pernah saya punya. Kalau ingatan masih sempurna, harga Mobil Remot yang saya beli di tahun 2003 itu berada di kisaran angka Rp 150 ribuan. Nominal yang cukup besar bagi anak seusia saya waktu itu. Di masa itu, ketika anak-anak memiliki mainan ‘mewah’, maka anak yang lain (teman sebayanya) akan iri dan meminta orang tua untuk membelikannya.
Begitu pun hari ini, kita melihat tren sepeda listrik yang lagi ramai di masyarakat. Meski ya kabar adanya barang ini sudah muncul sejak masa pandemi. Tapi, di kampung, kini tampak baru ramai. Para orang tua seperti berlomba-lomba membelikan sepeda listrik untuk anaknya.
Polanya sama, ada anak yang sudah punya sepeda listrik, lalu teman-temannya merasa iri dan akhirnya para orang tua pun membelikannya. Bagi orang tua yang kompeten secara finansial, tentu tak jadi persoalan. Namun bagaimana dengan yang defisit ekonomi? Tentu harus banting tulang lebih kejam terlebih dahulu.
Tren Sepeda Listrik
Di level alit, saya melihat fenomena orang-orang membeli sepeda listrik ini tidak lebih dari sekadar mengikuti tren saja. Bahasa lainnya, agar tetap eksis dalam kehidupan. Mumpung lagi viral dan banyak yang punya, akhirnya yang lain pun ikut-ikutan, biar tidak ketinggalan zaman.
Pola tersebut sama seperti tren yang biasa terjadi di masyarakat. Seperti tren joget-joget di medsos, misalnya, yang banyak diikuti tidak hanya oleh kaum muda, tapi juga orang dewasa. Belakangan, fenomena ‘ikut-ikutan’ tersebut oleh Patrick J. McGinnis disebut sebagai Fear of Missing Out (FOMO).
Tren sepeda listrik kini sedang jadi primadona di perkotaan hingga di desa-desa. Harganya yang nggak mahal-mahal amat membuat transportasi yang lahir di era banjir informasi ini banyak peminatnya. Lebih-lebih, penggunaannya juga cukup simple, sehingga seorang anak tak perlu belajar berhari-hari untuk bisa mengoperasikannya.
Konsumsi dan Simbol Eksistensi
Apa yang terjadi di lingkungan kita, terutama soal konsumsi masyarakat hari ini, secara tidak langsung juga mempertegas Teori Jean Baudrillard. Dia seorang sosiolog dan filsuf Prancis. Jean Baudrillard berbicara tentang teori masyarakat konsumsi, yang menurutnya, konsumsi dalam masyarakat modern telah beralih dari nilai guna (use value) dan nilai tukar (exchange value) ke nilai simbolik (symbolic value).
Di mata Baudrillard, sosok yang hidup di era 1928-2007, konsumsi tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi sarana untuk membedakan diri, menunjukkan status sosial, dan mengikuti tren yang sedang populer.
Nah, tren masyarakat mengonsumsi sepeda listrik belakangan ini juga sekaligus ingin menunjukkan status sosialnya. Orang yang berduit, misalnya, lebih-lebih yang melek media sosial, tentu tak ingin dianggap kuno karena tak membeli sepeda listrik. Karena hal ini merupakan bagian dari keinginan tuk menunjukkan eksistensi dan mengikuti tren yang sedang populer.
Sepeda listrik, dan tren lain yang sedang masyhur, bagi orang yang mengikutinya, adalah simbol untuk menunjukkan kepercayaan dan keberadaan diri. Soal sepeda listrik maupun motor listrik yang katanya adalah transportasi ramah lingkungan, masyarakat kita tampaknya tak berpikir sejauh itu.
Lain hal di level alit, lain pula di ranah elite. Pemerintah, dalam hal ini, membangun narasi bahwa pembuatan sepeda listrik memiliki beberapa tujuan utama. Yaitu mengurangi polusi, menghemat energi, dan mendorong konversi energi di sektor transportasi. Sepeda listrik juga dianggap sebagai solusi efisien dan ramah lingkungan untuk mobilitas perkotaan.
Kemudahan dalam pengaplikasian sepeda listrik oleh masyarakat bak dua sisi mata uang. Di satu sisi, membahayakan jika tak mereka gunakan pada usia yang tepat. Di lain sisi, memudahkan dan tanpa asap kendaraan.
Sepeda Listrik, Apakah Ramah Lingkungan?
Secara teoritis, sepeda listrik memang dianggap ramah lingkungan. Hal ini karena sepeda jenis ini tidak menghasilkan emisi gas buang saat kita gunakan. Ini tentu akan mengurangi polusi udara dan jejak karbon dibandingkan dengan kendaraan bermotor konvensional yang sering kita pakai.
Sepeda listrik ketika kita operasikan, ia bisa berjalan lebih cepat daripada sepeda biasa, dan tidak mengeluarkan asap yang bisa menimbulkan polusi udara. Itu benar. Namun, kita juga perlu menelaah lebih lanjut terkait bagaimana proses produksi baterai sepeda listrik.
Dari literatur yang saya temukan, sepeda listrik secara umum menggunakan jenis Baterai lithium-ion. Teknologi ini menawarkan kombinasi daya yang tinggi, umur pakai yang panjang, dan berat yang relatif ringan.
Akan tetapi, dalam proses produksinya, ternyata tidak serta merta bisa kita sebut ramah lingkungan. Sebab, untuk memproduksi battery lithium, bahan baku seperti lithium, nikel, dan kobalt harus ditambang.
Proses penambangan tersebut dapat memiliki efek negatif terhadap alam. Penambangan lithium sering melibatkan penebangan hutan dan polusi air, sementara penambangan nikel dan kobalt dapat mengakibatkan kerusakan lahan dan pencemaran limbah.
Ini cukup ironis. Ketika sepeda listrik kita gaung-gaungkan sebagai kendaraan yang bersahabat dengan lingkungan, di lain sisi ternyata proses pengambilan bahan dasar baterai-nya sendiri tidak terlalu pro terhadap lingkungan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sepeda listrik tidak sepenuhnya ramah lingkungan.
Lalu, Apa?
Mari kita coba telaah dari segi maqashid syariah. Dalam hal ini, saya coba menggunakan prinsip Hifdz Nafs dan Hifdz Mal. Melalui perspektifnya Al Ghazali, Hifdz Nafs adalah tentang menjaga dan memelihara jiwa, baik dalam hal fisik maupun spiritual.
Dalam konteks pemakaian sepeda listrik, maka aspek keselamatan dalam berkendara merupakan hal yang lebih kita utamakan. Ini penting dan jangan diabaikan supaya tercipta ekosistem yang ramah dan nyaman untuk masyarakat. Para orang tua yang secara sadar “memberi hadiah” sepeda listrik untuk anak-anaknya, juga jangan sampai melepas begitu saja.
Anak-anak rentan sekali melakukan kecerobohan dalam berkendara. Maka, penting bagi orang dewasa untuk perketat pengawasan. Jangan sampai anak dibebaskan berkendara di jalan (apalagi jalan raya) tanpa pendampingan.
Lebih gawat lagi, emosi serta karakter anak-anak yang cenderung tidak stabil, memungkinkan dirinya untuk ngebut. Selain dapat mengancam nyawa sendiri dan orang lain, juga tidak sejalan dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah.
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020, pengguna sepeda listrik minimal harus berusia 12 tahun, dengan catatan pengguna yang berusia 12 hingga 15 tahun harus didampingi orang dewasa. Meski begitu, realitanya di lapangan, anak yang masih berusia 7-10 tahun pun sudah mengendarai sepeda listrik.
Anak-anak seusia segitu cenderung kurang waspada terhadap situasi jalan raya yang bisa berubah dengan cepat. Hal ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Terlebih, bahaya utama sepeda listrik ternyata adalah kemampuannya mencapai kecepatan tinggi hingga 40km/jam.
Melihat dari Kacamata Maqashid Syariah
Jika sudah membahayakan di jalanan, tentu ini bertentangan dengan prinsip Hifdz Nafs. Di mana prinsip ini menekankan pentingnya memelihara dan melindungi kehidupan manusia dari ancaman yang dapat membahayakan, mengancam atau mengganggu kelangsungan hidupnya. Termasuk aktivitas anak kecil menggerakkan kendaraan di jalanan yang bisa membahayakan lalu lintas sekitar.
Dalam hal ini, orang tua wajib berperan penting. Jangan sampai rasa kasih sayang kepada anak berujung pada penyesalan. Ini juga menjadi pengingat bagi diri kita, bahwa berkendara yang aman adalah bagian dari Hifdz Nafs karena melibatkan perlindungan terhadap nyawa pengendara dan penumpang, serta keselamatan orang lain di atas aspal.
Begitu pun, berkendara dengan baik membantu melindungi kendaraan dan harta benda dari kerusakan atau kehilangan akibat kecelakaan (hifz mal). Prinsip hifzh maal berarti memastikan bahwa kegiatan berkendara tidak merugikan harta benda, baik milik diri sendiri maupun orang lain. Jadi, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Mari, main sepeda-sepedaan dulu. []