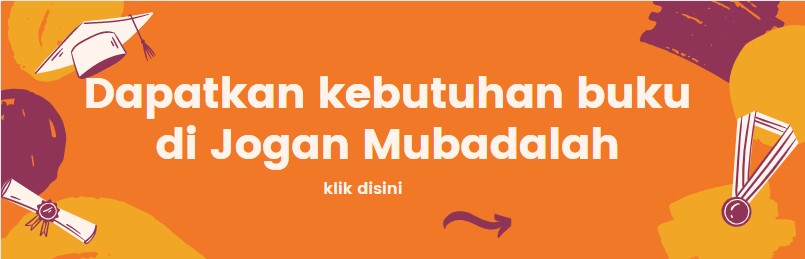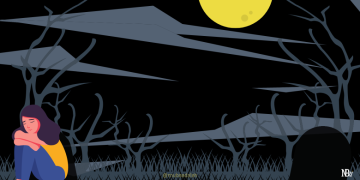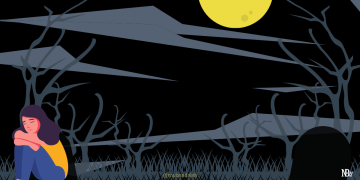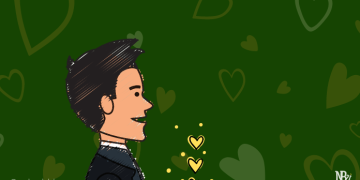Mubadalah.id – Suara ombak di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, tak lagi memberi rasa lega bagi para nelayan. Bagi mereka, laut kini menyimpan ketidakpastian. Hasil tangkapan yang dulu melimpah, kini menyusut drastis. Bukan karena musim, tapi diduga akibat limbah dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon yang berdiri megah di tepi pesisir, hanya beberapa kilometer dari kampung mereka.
“Dulu rajungan sama kerang ijo banyak sekali. Sekarang, 30 sampai 50 persen sudah hilang,” ujar Yadi, Kepala Desa Waruduwur, sambil menatap garis pantai yang kini keruh kecokelatan.
Waruduwur adalah desa pesisir yang strategis. Letaknya tak jauh dari jalur Pantura dan Laut Jawa, membuat sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari hasil laut. Sebagian menjadi petani sawah dan petani tambak garam, tetapi nelayan tetap menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Hasil tangkapan utama mereka beragam: ikan, rajungan, hingga kerang hijau. Bukan hanya nelayan yang hidup dari laut—para perempuan di desa pun banyak bekerja sebagai pengupas rajungan dan kerang hijau, dengan penghasilan harian yang bisa mencapai Rp300 ribu.
“Kalau rajungan banyak, kerja dari pagi sampai malam pun nggak terasa capek,” kata Citra, pengupas rajungan. “Tapi sekarang orderan sepi, bahan bakunya saja susah.”
Jejak PLTU di Pesisir Cirebon
PLTU Cirebon 1 dengan kapasitas 1 x 660 MW diresmikan pada 18 Oktober 2012 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu, Jero Wacik. Berlokasi sekitar 10 kilometer di timur Kota Cirebon, pembangkit ini diklaim mampu menambah pasokan listrik hingga 5.500 GWh per tahun.
Namun, di balik klaim pasokan energi, warga Waruduwur merasakan konsekuensi lain: perubahan ekosistem laut, pencemaran air, dan penurunan hasil tangkapan.
Limbah pembakaran batu bara diduga menjadi penyebab utama kerusakannya. Menurut laporan bandungbergerak.id, industri batu bara kerap menghasilkan limbah yang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya. Limbah tersebut bisa mencemari sungai, laut, dan sumber air tanah.
Bagi nelayan, tanda-tanda kerusakan laut terlihat jelas. Air yang dulunya biru jernih kini sering berwarna kehitaman, terutama setelah hujan deras.
“Setiap hujan turun, limbah batu bara dibuang. Air laut jadi hitam, ikan-ikan mati,” kata Rasmudin, nelayan Waruduwur. “Mungkin orang-orang PLTU mikirnya kita nggak ngerti. Padahal kita yang tiap hari ada di laut tahu persis bedanya.”
Perubahan warna air dan berkurangnya populasi hewan laut membuat banyak nelayan harus melaut lebih jauh, menghabiskan waktu dan bahan bakar lebih banyak, hanya untuk pulang dengan tangkapan yang tak sebanding.
Kemudian, tak hanya lingkungan yang terkena imbas. Asap hasil pembakaran batu bara juga menjadi ancaman kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.
Menurut laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), polusi udara dari PLTU dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma, gangguan jantung, serta berdampak pada kesuburan.
“Banyak ibu-ibu di sini yang sering batuk-batuk dan sesak. Kalau kena angin laut yang bercampur debu batu bara, makin parah,” kata Rasmudin.
Penghasilan Nelayan Menurun Drastis
Ketika laut tercemar, efek domino pun terjadi pada ekonomi desa. Penghasilan nelayan menurun drastis, pengupas rajungan kehilangan bahan baku, dan usaha kecil di sekitar pesisir ikut merosot. Bagi masyarakat yang hidup dari siklus laut, kerusakan ekosistem berarti hilangnya napas ekonomi.
Namun ironisnya, sebagian warga memilih untuk diam. “Ada yang merasa ya sudahlah, mau bagaimana lagi. PLTU ini besar, kita nggak bisa melawan,” tutur Yadi, sang kepala desa.
Oleh karena itu, dengan adanya PLTU di Waruduwur menjadi peringatan bahwa pembangunan infrastruktur besar tanpa kajian dampak lingkungan yang matang bisa menciptakan kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan yang panjang. Apalagi, di tengah tuntutan energi nasional, transisi ke sumber energi yang lebih bersih menjadi semakin mendesak.
“Kalau laut ini mati, kami pun mati,” kata Rasmudin lirih. []