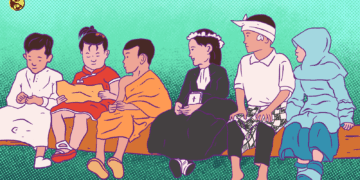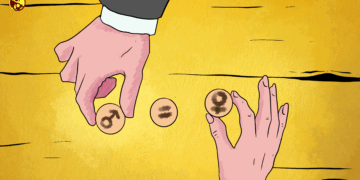Mubadalah.id – Proses berdirinya Indonesia adalah dialog keberagaman. Dialog yang membuat masyarakat yang berbeda-beda mau mengaku bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Yaitu, Indonesia. Namun, tidak perlu meng-glorifikasi kerukunan, perjalanan 80 tahun Indonesia; 17 Agustus 1945 – 2025, bukannya tanpa konflik antarsesama bangsa.
Konflik Kepentingan hingga Pembantaian
Mengupayakan kerukunan dalam keberagaman memang tidaklah mudah. Terlebih, jika kepentingan politik dan ekonomi telah mewarnai perbedaan. Demikian kondisi pasca Indonesia merdeka, dihiasi berbagai konflik kepentingan antara golongan nasionalis, agama, dan komunis.
Di antara yang terkenal adalah peristiwa Madiun tahun 1948. Kita tahu ini sebagai peristiwa pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia). Namun, pada dasarnya, sebab perbedaan kepentingan antara elit ketiga kubu, yang akhirnya berbuah kontak senjata.
Berbagai ketegangan terus terjadi, membuat Bung Karno kepikiran mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menandai perubahan arah demokrasi Indonesia, dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin (1959-1966). Pada masa ini, Bung Karno mengajukan konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
Niat Bung Besar untuk menyatukan ketiganya. Namun, upaya keberagaman ini gagal. Malah yang terjadi peristiwa berdarah G-30 S (Gerakan 30 September 1965, oleh Bung Karno Gestok; Gerakan 1 Oktober).
Benarkah PKI dalang dari peristiwa itu? Ada beberapa buku yang saya baca seolah mempertanyakannya. Namun, pengetahuan yang sudah sangat umum, yang kita tahu selama ini, PKI lah pelakunya.
Pemimpin yang berkuasa selanjutnya, yang kebetulan sangat nasionalis, nampaknya sudah menyerah pada perbedaan ini. Atau, tepatnya tidak ingin ada rival kepentingan. Tidak seperti figur nasionalis sebelumnya, Sukarno, yang ingin NASAKOM, Suharto memilih menghapus komunis dari negeri ini.
Untuk itu, harga yang perlu dibayar sangat mahal. Adalah pembantaian. Mereka yang terindikasi komunis, yang tertuduh dalang G-30 S, tidak boleh lagi ada di Indonesia. Atas nama stabilitas, mereka dibunuh. Robert Cribb, dalam “Unresolved Problems in the Indonesian Killings of 1965-1966,” menyebut setidaknya ada sekitar 200.000, atau perkiraan paling banyak sekitar 1 juta, korban gerakan pembersihan ini.
Angka fantastis, yang cukup membuat kita berpikir ulang; siapa sebenarnya villain dalam peristiwa 1965-1966?
Dari Diskriminasi Etnis hingga Konflik Agama
Rezim pun berganti. Kali ini, di masa Orba, kata mereka sudah stabil dan aman. Ikhtiar merawat kerukunan juga ada. Misalnya, Keputusan Menag No. 70 Tahun 1978, yang mengatur aktivitas siar agama harus berdasarkan pada semangat kerukunan, rekonsiliasi, toleransi, dan saling hormat antarpemeluk agama-agama yang berbeda.
Namun, bicara keberagaman masa Orba, kita juga tidak dapat mengabaikan Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang pembatasan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina.
Rezim yang parno dengan kebangkitan PKI, entah sadar atau tidak (kemungkinan sadar), mengeluarkan regulasi yang mendiskriminasi etnis Tionghoa umumnya, dan umat Khonghucu khususnya. Puncak diskriminasi etnis ini pada insiden 1998, banyak perempuan Tionghoa yang menjadi korban kekerasan seksual. Kala itu, yang terjadi bukan sekadar krisis moneter, tapi juga krisis keberagaman dan kemanusiaan.
Damai Orba hanya sekadar kesunyian di permukaan, belum tentu benar-benar keberagaman. Boleh jadi, karena adanya tekanan militeristik memaksa orang-orang untuk pura-pura rukun. Dalam kajian konflik sosial, ini namanya konflik laten (yang tersembunyi). Kata Imam Tolkhah, dalam Guard the Religious Conflict: in Strengthening National Integration, di bawah permukaan potensi konflik sosial sebenarnya masih meluap.
Tidak heran, di era Reformasi, ketika rezim berganti, berbagai gerakan radikal dan konflik sosial menjamur di banyak tempat. Ada yang gesekannya kecil masih terkendali. Kacaunya, ada yang besar tidak terkendali, seperti konflik Ambon dan Poso yang berujung pada pertumpahan darah antara umat Muslim dan Kristiani.
Hingga saat ini, berbagai konflik sosial masih terus mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Dalam konteks antarumat beragama, misalnya, Setara Institute pada 29 Juli 2025 merilis data “Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) tahun 2024.” Dalam catatan mereka, sepanjang tahun 2024, telah terjadi 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran KBB di Indonesia.
Kita Ini Sama-sama Orang Indonesia, Kan?
Masalahnya bukan pada perbedaan. Menjadi berbeda, tidak berarti harus bermusuhan. Ego kebenaran dan kepentingan yang berulang kali membuat bangsa ini gagal menjalin hubungan sebagai satu masyarakat Indonesia.
Saya jadi ingat kata-kata Karen Armstrong, dalam Fields of Blood, bahwa perang disebabkan “oleh ketidakmampuan kita untuk melihat hubungan. Hubungan kita dengan situasi ekonomi dan sejarah kita. Hubungan kita dengan sesama kita. Dan di atas semua itu hubungan kita dengan ketiadaan. Dengan kematian.”
Berbagai konflik yang mewarnai perjalanan 80 tahun Indonesia, pada dasarnya sebab ketidakmampuan melihat dan menjalin hubungan sebagai sesama bangsa. Itu yang membuat bangsa ini berulang-ulang kali pecah.
Upaya seperti moderasi beragama yang sering Kemenag mainstream-kan. Konsep ma’ruf, mubadalah, dan keadilan hakiki yang KUPI kemukakan. Dan berbagai pendekatan penyelesaian konflik lainnya. Pada dasarnya, adalah untuk mengupayakan kemampuan menjaga hubungan baik sebagai sesama manusia. Kemampuan melihat dan memahami bahwa meski berbeda kita ini sama-sama orang Indonesia. []