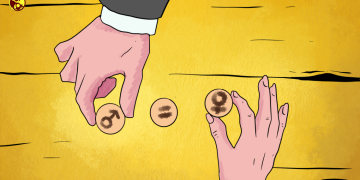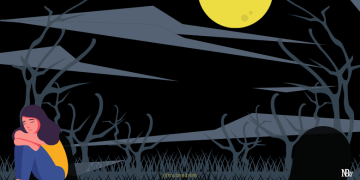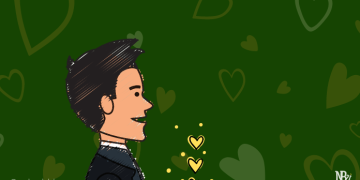Mubadalah.id – Pergantian mendadak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal September 2025 memunculkan guncangan yang jauh lebih besar daripada rotasi kabinet. Bagi banyak orang, sosok Sri Mulyani identik dengan kredibilitas fiskal, disiplin anggaran, dan integritas. Tidak heran jika pencopotannya membuat publik resah, investor cemas, dan pasar keuangan bergejolak.
Reshuffle ini terjadi di tengah meningkatnya kekecewaan rakyat terhadap kebijakan fiskal negara. Ketidakpuasan itu meledak setelah terungkapnya besarnya tunjangan hunian anggota DPR sekitar Rp50 juta per bulan. Kebijakan ini kontras dengan kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi kenaikan harga bahan pokok.
Gelombang protes mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, yang kita kenal dengan “17+8 Tuntutan”, menjadi simbol keresahan nasional.
Pertanyaannya apakah pergantian Sri Mulyani benar-benar menjawab persoalan rakyat, atau justru memperlihatkan krisis legitimasi pemerintah di hadapan publik?
Krisis Kepercayaan Publik
Dalam politik modern, kepercayaan publik adalah fondasi utama relasi antara negara dan warga. Menurut Fukuyama, ketidakpercayaan tidak menyediakan lingkungan yang kondusif untuk maju. Melalui penelitian yang ia tuangkan dalam buku Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity, Fukuyama memperlihatkan ada korelasi antara masyarakat yang hight trust dan low trust dengan kemakmuran sosial dan kemajuan ekonomi.
Sebaliknya, dalam negara-negara yang low trust, ketidakpercayaan tersebar luas dan membebani seluruh bentuk aktivitas ekonomi dan politik dengan sejenis pajak tertentu yang tidak harus terbayar oleh masyarakat yang hight trust.
Karena tidak percaya, orang-orang akan mengakhiri kerjasama mereka yang terbangun di bawah sistem aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan formal, yang harus dinegosiasikan, disepakati, digugat, dan terlaksana, bahkan kadang-kadang dengan cara-cara koersif.
Bagi banyak orang, Sri Mulyani adalah simbol kredibilitas fiskal. Ia pernah berani menolak proyek ambisius yang ia anggap membebani APBN, mengurangi subsidi BBM untuk menutup defisit. Bahkan ia berhadapan dengan elite politik ketika melawan mafia pajak. Ketika figur semacam ini disingkirkan, siapa lagi yang bisa kita percaya menjaga uang mereka?
Krisis kepercayaan ini berbahaya. Weber menekankan bahwa legitimasi negara tidak hanya berdiri di atas hukum formal atau kekuasaan, tetapi juga pada rasa adil yang rakyat rasakan. Tanpa legitimasi moral, negara kehilangan wibawanya, sekalipun memiliki kekuatan militer dan hukum.
Keadilan Fiskal yang Terabaikan
Masalah utama dalam polemik ini adalah keadilan fiskal. Dalam teori ekonomi publik, pajak seharusnya terkelola berdasarkan asas keadilan yang mampu memberi lebih, sementara yang lemah terlindungi. John Rawls dalam A Theory of Justice menjelaskan prinsip difference. Kebijakan adil adalah kebijakan yang menguntungkan kelompok paling lemah.
Sayangnya, arah kebijakan fiskal Indonesia sering kali berjalan terbalik. Rakyat kecil menanggung beban pajak lebih besar melalui konsumsi sehari-hari, sementara kelompok elite menikmati fasilitas melimpah. Kenaikan PPN 12 persen, misalnya, dianggap teknis oleh pemerintah, tetapi nyata terasa di masyarakat. Harga kebutuhan pokok naik, daya beli menurun, dan angka kemiskinan semakin bertambah.
Ironisnya, di saat yang sama DPR menikmati tunjangan dengan jumlah berpuluh kali lipat dari gaji rakyatnya, di luar gaji dan fasilitas lainnya. Ketimpangan inilah yang melahirkan kemarahan publik. Kontras antara beban rakyat dan privilege elite menunjukkan bahwa keadilan fiskal masih jauh dari prinsip Rawls maupun amanat konstitusi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.
Dampak Sosial yang Lebih Luas
Kebijakan fiskal tidak pernah netral. Ia berkelindan dengan realitas sosial sehari-hari. Buruh yang gajinya terpotong pajak penghasilan, ibu rumah tangga yang harus memutar otak karena harga kebutuhan naik, dan pelaku UMKM yang terbebani biaya produksi semua merasakan dampaknya langsung.
Ketidakadilan fiskal juga berdampak pada relasi sosial. Masyarakat merasa ada jarak yang semakin lebar antara negara dan rakyat. Jurang ini diperparah dengan gaya komunikasi politik yang sering mengabaikan aspirasi warga. Alih-alih membuka ruang dialog, kebijakan fiskal justru diputuskan secara top-down tanpa partisipasi bermakna.
Politik dan Krisis Legitimasi
Reshuffle Sri Mulyani memperlihatkan bahwa politik kerap lebih berpihak pada stabilitas elite daripada keadilan rakyat. Rousseau dalam The Social Contract menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan lahir dari kontrak sosial. Kesepakatan bahwa rakyat menyerahkan sebagian haknya dengan syarat negara melindungi kepentingan mereka. Jika negara gagal memenuhi syarat itu, kontrak sosial pun runtuh.
Dan sekarang, krisis legitimasi ini semakin nyata. Program seperti makan siang gratis bisa saja menyenangkan sesaat, tetapi tidak menyentuh akar masalah ketimpangan. Sementara itu, kebijakan strategis seperti reformasi pajak progresif atau pengendalian anggaran pejabat justru tidak berjalan secara serius.
Mengembalikan Kepercayaan Publik
Ada beberapa langkah mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pertama, transparansi anggaran harus diperkuat dengan membuka data penggunaan APBN secara real-time kepada masyarakat.
Kedua, fasilitas pejabat negara perlu negara tinjau ulang agar sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat. Ketiga, pajak progresif harus diperluas, barang mewah, keuntungan perusahaan besar, dan aset nonproduktif harus dikenai pajak lebih tinggi daripada kebutuhan pokok rakyat.
Lebih dari itu, kebijakan fiskal harus melibatkan partisipasi publik. Suara buruh, perempuan, nelayan, dan petani perlu terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan. Tanpa itu, kebijakan fiskal hanya akan menjadi alat elite untuk mempertahankan kekuasaan.
Belajar dari Kesalingan
Pada akhirnya, krisis ini bukan hanya soal reshuffle menteri, tetapi tentang rapuhnya relasi negara dan rakyat. Relasi itu seharusnya berjalan dua arah, saling melindungi dan menguatkan. Di sinilah nilai mubadalah atau kesalingan penting kita ingat.
Negara tidak bisa hanya menuntut rakyat membayar pajak, sementara hak-hak mereka terabaikan. Sebaliknya, rakyat juga tidak mungkin terus percaya jika pemerintah tidak memberi bukti keadilan. Kesalingan menuntut adanya timbal balik yang adil. Pajak yang dibayar rakyat kembali dalam bentuk layanan publik yang nyata. Sementara pejabat negara menunjukkan empati dengan hidup sederhana dan berpihak pada yang lemah.
Reshuffle Sri Mulyani bisa kita baca sebagai ujian sejarah. Apakah pemerintah memilih jalan politik yang menutup telinga dari rakyat, atau menjadikannya momentum untuk membangun kembali kontrak sosial yang setara. Jika nilai kesalingan kita tegakkan, negara dan rakyat bisa berdiri sebagai mitra, bukan musuh. Tetapi jika tidak, krisis kepercayaan ini akan terus membesar, dan legitimasi negara akan semakin runtuh. []