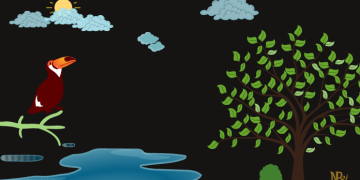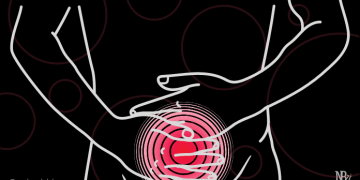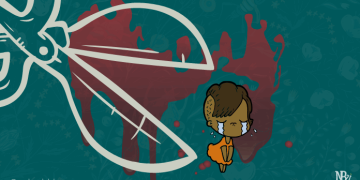Mubadalah.id – “Mas Tegar di mana? Repot atau tidak? Tolong antarin saya ke kamar mandi.” Kala lain, “Mas Tegar kamu di mana ? apakah boleh saya minta tolong diantarkan ke meja makan,” ucap Mas Arya, seorang penyandang tuna netra saat berada di suatu forum konsolidasi penyandang disabilitas.
Waktu ISOMA tiba saatnya peserta istirahat. Ketika saya sedang duduk di kursi ruangan tiba-tiba ada seorang pemuda berperawakan tinggi menghampiri saya. Ia menepuk pundak saya dan menunjukkan ketikan di HP nya. “Mas boleh kenalan? Saya Akbar, 22 tahun dari Sidoarjo”. Rupanya ia penyandang tuna rungu dan tuna wicara sehingga hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan ketikan di HP.
Saya pernah terjebak dalam pergulatan batin yang dalam. Saya seringkali berfikir “untuk apa saya dilahirkan seperti ini?” kerap menghampiri, menimbulkan rasa hampa dalam diri saya. Namun, titik balik terbesar dalam hidup saya justru datang ketika saya mulai terlibat langsung dengan komunitas penyandang disabilitas lainnya.
Bahkan, saat saya mendengar permintaan tolong dari Mas Arya yang tuna netra, atau melihat semangat juang teman-teman penyandang disabilitas lainnya, perspektif saya berubah total. Di saat-saat seperti itulah, saya yang sering merasa tidak berguna dan dianggap tidak mampu, justru menemukan tujuan yang jelas. Saya bisa membantu menuntun mereka, melayani mereka. Itu adalah anugerah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Dalam kehidupan yang sering kali diwarnai oleh prasangka dan hambatan fisik, perjalanan hidup saya adalah bukti nyata bahwa “keterbatasan bukan halangan untuk bermimpi dan mengabdi.”
Dari juara kelas di bangku SD, juara pidato tingkat kota hingga lolos ke provinsi, hingga kini menjadi seorang aktivis gerakan inklusi disabilitas. Ini adalah narasi saya tentang menggapai asa di tengah bayang-bayang pengasingan sosial.
Pandangan Victor Frankl
Victor Frankl, seorang psikiater dan korban selamat Holocaust mengatakan bahwa makna hidup dapat ditemukan bahkan dalam penderitaan terberat, dan motivasi utama manusia adalah pencarian makna.
Saya merasa telah menemukan makna itu: dari rasa terasing, saya beralih menjadi pemberi kekuatan. Saya belajar untuk tidak menunggu pujian orang lain untuk bangga pada diri sendiri, tetapi menemukan kebanggaan itu melalui kontribusi kepada sesama.
Perjalanan ini kemudian membawa saya pada ruang-ruang yang lebih luas. Saya bersyukur bisa berdiskusi dengan para akademisi dari UNAIR, beradu pikiran dengan Ibu Reni, Anggota DPRD Kabupaten Kediri dan juga bersama Gus Barok, ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.
Karena dari setiap pertemuan ini adalah kesempatan berharga untuk menyuarakan mimpi besar kami: mewujudkan Indonesia yang inklusif, ramah, adil, dan setara bagi semua, melalui siaran radio dan berbagai forum lainnya.
Pengalaman bersama teman-teman disabilitas mengajarkan saya sebuah arti kehidupan yang dalam. Seringkali saya ingin mengeluh. Tetapi lalu teringat akan kesunyian yang teman tuli rasakan, atau kegelapan yang teman tuna netra hadapi setiap harinya.
Namun, mereka tidak seberisik keluh kesah saya. Renungan ini menguatkan pesan B.J. Habibie, bahwa hidup haruslah memberi manfaat sebesar-besarnya. Mereka adalah pengingat terbaik bagi saya untuk selalu melihat ke bawah dan bersyukur.
Pada akhirnya, saya sampai pada sebuah keyakinan yang teguh: tidak ada yang terlahir sia-sia. Disabilitas yang saya sandang bukanlah akhir segalanya, melainkan perbedaan yang memberi warna unik dalam hidup saya.
Inilah ajakan saya: mari kita rangkul mereka yang memiliki ujian berbeda. Karena dalam diri mereka seringkali tersimpan ketabahan dan semangat yang luar biasa. Melalui perjuangan ini, asa akan terus menggapai, membuktikan bahwa dalam keterbatasan sekalipun, cahaya kemanusiaan tak pernah padam. []