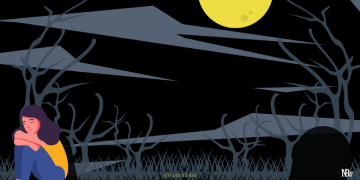Mubadalah.id – Pagi di pesantren selalu memiliki ritme yang khas. Suara azan yang menggema, langkah kaki santri yang bergegas ke kelas, dan aroma kitab kuning yang memenuhi udara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun pada 13 Oktober 2025, ketenangan ini tersentuh oleh layar televisi jutaan rumah tangga.
Program Xpose Uncensored di Trans7 menayangkan segmen yang menyorot kehidupan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, dengan narasi yang memicu kontroversi. Tayangan itu menyiratkan kiai hidup bermewah-mewah dan mengeksploitasi santri, bahkan menyinggung praktik “perdagangan amplop” yang jauh dari kenyataan.
Reaksi publik pun deras. Tagar #BoikotTrans7 meledak di media sosial, mencerminkan kekecewaan kolektif masyarakat terhadap tayangan yang menodai simbol keagamaan. Kritik datang dari santri, alumni Lirboyo, ulama, hingga lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Mereka menuntut stasiun televisi meminta maaf secara terbuka dan menegaskan komitmen pada etika penyiaran. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki tanggung jawab moral yang besar. Tayangan yang menyinggung pesantren bukan sekadar salah konteks, tetapi mengabaikan sejarah panjang lembaga yang menjadi pilar pendidikan dan moral masyarakat.
Sebagai konteks, pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah dan doktrin pesantren dijelaskan secara mendalam dalam buku Doktrin dan Pemahaman Keagamaan di Pesantren karya Syarif Hidayatullah (2020), yang menegaskan fungsi pondok pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan moral.
Sejarah Panjang Pondok Pesantren
Selain itu, sejarah panjang pesantren juga membuktikan peranannya dalam perjuangan bangsa. Ahmad Royani (2018) menulis bahwa santri aktif melawan penjajah Belanda dan Jepang, berperan dalam mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai bentuk perlawanan. Nilai-nilai keberanian, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan di pesantren membentuk santri yang cerdas akademik sekaligus beradab dan patriotik, yang seharusnya dihormati media.
Sejak abad ke-14, pesantren telah menjadi pusat pendidikan agama, sosial, dan budaya. Santri belajar membaca Al-Qur’an, memahami fikih, tasawuf, serta nilai kepemimpinan dan manajemen sosial. Pesantren juga mengajarkan kemandirian dan disiplin sosial. Karena itu, kritik yang tidak berdasar dan bersifat sensasional menimbulkan luka kolektif, bukan hanya bagi santri tetapi juga bagi publik yang menghargai norma kesopanan dan adab.
Media modern memiliki peran strategis yang sama pentingnya: membentuk opini, karakter, dan budaya publik. Namun obsesi pada rating dan sensasi membuat batas etika mudah dilanggar. Tayangan yang menyinggung pesantren menunjukkan bagaimana sensasi bisa mengalahkan moralitas dan fakta, dan hiburan yang seharusnya mencerahkan justru meninggalkan luka sosial. Kritik masyarakat bukan hanya soal konten yang salah, tetapi juga tentang pengabaian prinsip editorial yang etis.
Redaksi seharusnya menimbang framing, narasi, dan pemilihan kata agar tidak menyinggung simbol yang dijunjung masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU Penyiaran yang menekankan bahwa seluruh tayangan harus menghormati nilai-nilai agama, moralitas, dan kepentingan publik.
Selain itu, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI yang menegaskan penghormatan terhadap nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan, serta larangan merendahkan martabat individu atau kelompok tertentu.
Pendidikan Moral
Fenomena pemberitaan Lirboyo ini juga membuka diskusi lebih luas tentang pendidikan moral di masyarakat modern. Media dan platform digital adalah arena pembentuk karakter, opini, dan budaya.
Jika hiburan terus dikembangkan tanpa memperhatikan etika, masyarakat akan terbiasa pada relativisme moral, di mana simbol penting dianggap main-main. Kesantunan publik, yang seharusnya menjadi norma sosial, perlahan terkikis. Luka yang muncul bersifat kolektif karena setiap individu yang menghargai norma ini merasakannya.
Namun, luka ini bisa menjadi titik refleksi. Media perlu meneguhkan etika produksi, termasuk pelatihan sensitif terhadap budaya, nilai moral, dan sejarah pesantren. Redaksi harus mempertimbangkan fakta, framing, dan dampak konten terhadap simbol yang dihormati masyarakat.
Publik harus kritis, menuntut pertanggungjawaban, tetapi tetap beradab. Lembaga pendidikan dan komunitas moral harus mengingatkan pentingnya kesantunan, adab, dan penghormatan terhadap simbol budaya. Sinergi ini memungkinkan masyarakat dan media berjalan seiring, menjaga marwah nilai sosial sambil tetap memanfaatkan hiburan secara positif.
Adab dan Etika
Kasus framing Lirboyo ini menegaskan bahwa adab dan etika komunikasi hidup dalam praktik sehari-hari. Ketika media mengabaikannya, yang muncul bukan hanya luka individu, tetapi luka kolektif yang menandai kerentanan moral masyarakat. Luka ini bisa menjadi panggilan untuk memperkuat pendidikan etika, kesadaran sosial, dan norma kesopanan, agar masyarakat tidak hanya menilai, tetapi aktif membangun ruang publik yang beradab.
Tanggung jawab atas kesantunan publik bukan milik satu pihak saja. Media harus belajar menghormati nilai sosial, publik harus kritis tetapi tetap beradab, lembaga pendidikan dan komunitas moral harus meneguhkan adab dan etika.
Ketika semua pihak berjalan beriringan, luka kolektif bisa berubah menjadi pelajaran berharga, memperkuat kesadaran etika, dan menumbuhkan rasa hormat yang konsisten. Kesantunan yang hidup, adab yang dijaga, dan etika yang dijunjung akan menjadi fondasi komunikasi dan budaya yang beradab, sebagaimana pesantren telah membuktikan selama berabad-abad. Dari pendidikan, pembinaan moral, hingga perjuangan kemerdekaan bangsa. []