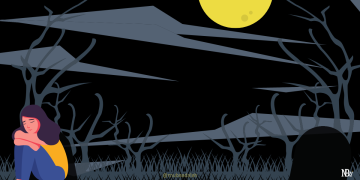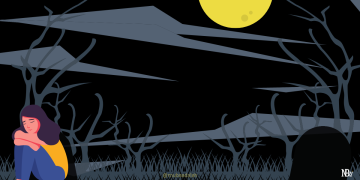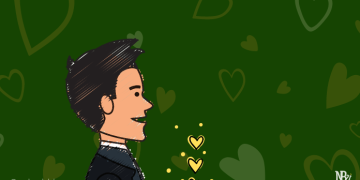Mubadalah.id – Tulisan ini barangkali tidak sejalan dengan norma etika publik yang dewasa ini menghabisi Trans7 habis-habisan. Seruan boikot, geruduk, narasi tandingan, hingga tuntutan permohonan maaf dengan segala rupanya menjadi iman yang hampir-hampir mutlak.
Tapi, bagaimana jika kita sedikit menggeser sudut pandang? Misalnya, bagaimana seandainya publik melihat produk tayangan Trans7 sebagai bagian dari kebebasan pers? Sungguhkah kritik mereka salah?
Luka Kita
Di dunia yang kian paralaks, kiranya penting untuk tak buru-buru “menghabisi”. Apalagi gemeruduk memboikot, menggeruduk, bahkan menyegel. Tentu, sebagaimana pesantren ajarkan, akhlak selalu lebih dahulu sebelum ilmu (al akhlaq qabla al ‘ilm).
Namun, gegara sebuah “luka”, kaidah yang mulanya acap menggaung itu kini lenyap ditelan api amarah. Pesantren menunjukkan wajah garang dengan ragam atribut dominasinya.
Alih-alih berkenan berinterospeksi atas kritik publik sebagaimana tayangan Trans7, intensi penolakan dan “bersih-bersihlah” yang justru mengemuka. Tentu, ini tak sama sekali menyentuh ranah substansial.
Dunia terbuka, dunia hujan kritik
Sejatinya, keterbukaan dunia berkat globalisasi dan advansi teknologi memang berkonsekuensi pada mudahnya kritik mencuat. Hari ini, pesantren dengan segala pola eksklusivitasnya, tak lagi bisa menghindar.
Sorot publik, baik individu maupun media, senantiasa mengawasi. Terlebih, dengan maraknya laporan kekerasan seksual yang muncul dari balik tirai pesantren, hasrat publik untuk membuka tabir penutup itu kian menggelegak saja.
Trans7, dengan segala potensi luputnya, berani mengambil posisi kritis itu. Padahal, selama ini, tak pernah ada media manapun yang berani mengambil posisi pinggir jurang sebagai kritikus pesantren.
Gaung suara pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa berkualitas seakan menjadi tembok pelindung. Seakan tak ada yang salah dari pesantren. Dus, kesempurnaan milik para santri, kyai, ajengan, gus, ning, dan apapun!
Transformasi akhlak humanis
Pesantren sejatinya tengah berada pada arus menuju transformasi akhlak. Kritik media, seperti Trans7, tak lain merupakan bagian dari colekan untuk membuka mata kita bersama.
Yakni, kita perlu memandang akhlak dalam kerangka yang berbeda. Akhlak tak lagi boleh sekadar mewajah sebagai bentuk pendisiplinan tubuh.
Kita mesti beranjak dari sekadar sikap menunduk, merangkak, berjalan tak membelakangi, atau mencium tangan dan kaki guru. Namun, akhlak menjelma sebagai kesadaran eksistensial akan pentingnya penghormatan kepada sesama manusia.
Melampaui pendisiplinan tubuh
Akhlak dalam pemahaman pendisiplinan tubuh tak bakal menyentuh aspek paling ruhaniah dari diri seseorang. Praktiknya, sebagaimana kita lihat bersama, seseorang dapat sedemikian hormat kepada sosok tertentu. Namun, di lain saat, ia bisa sebegitu garang kepada orang lain.
Demikianlah, bahwa kita memerlukan transformasi paradigma pendidikan akhlak. Telah banyak para ahli yang mengemukakan tahapan pendidikan karakter pada anak. Sebutlah Piaget, Vygotski, juga Glaserfeld.
Kita bisa sejenak tak melulu mengglorifikasi Az Zarnuji lewat Ta’lim al Muta’allim-nya. Toh, seandainya Az Zarnuji hidup di era hari ini, sangat mungkin ia menulis redaksi yang berbeda perihal proses pembentukan akhlak.
Akhlak egaliterian
Kritik Trans7, terlepas dari kemungkinan kealpaan dan keluputannya, mestinya kita respon sebagai “sengatan” menuju akhlak egaliterian. Yakni, mendudukkan akhlak sebagai pondasi membangun masyarakat setara.
Selama ini, dalam narasi feodalisme misalnya, akhlak lebih menjelma sebagai interaksi stratifikatif nan kastaisme. Padahal, Islam datang sebagai agama pembebasan yang mengentaskan manusia dari perjenjangan antar-makhluk.
Kiranya, publik pesantren hari ini bisa berkaca pada catatan budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Ia menulis perihal egaliteranisme pesantren di kolom Majalah Tempo beberapa waktu silam.
Teladan Gontor
Cak Nun mencontohkan bagaiamana Pesantren Gontor tak memberlakukan tradisi doktrin penghormatan. “Santri bebas menentukan kiainya sendiri,” tulis bekas mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM itu.
Contoh minor seperti yang Cak Nun ungkapan ke publik menunjukkan bahwa pesantren tak semuanya seperti yang Trans7 gambarkan. Karenanya, resistensi ideal dari tayangan tersebut ialah berbenah.
Ya, cukup berbenah atas segala carut-marut yang ada. Tak perlu denial, apalagi menyerukan seruan boikot produk. Kita, sebagai sesama insan pesantren, bisa menunjukkan akan cara merespon kritik dengan cara elegan.
Siapa tahu, lewat respon elegan itu, kelak pesantren melahirkan media televisi nasional yang bahkan melampaui Trans7. Syaratnya satu: melawan dengan elegan, bukan grusa-grusu berpayung kemarahan! []