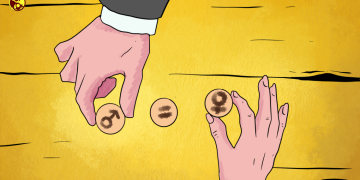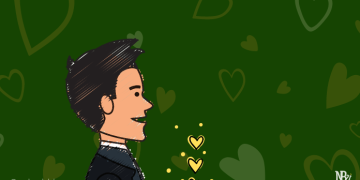Mubadalah.id – Isu mengenai kesaksian perempuan dalam hukum Islam masih menjadi perbincangan panjang dan tak jarang memunculkan kontroversi. Di sebagian masyarakat Muslim, pandangan bahwa kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki sering kali diterima begitu saja sebagai ketentuan mutlak dari syariat.
Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, pandangan semacam ini tidak lahir dari teks-teks suci semata. Melainkan dari cara baca dan konstruksi sosial yang patriarkal serta kurang mempertimbangkan konteks historis dan sosial dari ayat maupun hadis yang bersangkutan.
Nyai Hj. Badriyah Fayumi dalam tulisannya di Kupipedia.id menegaskan bahwa pemikiran yang misoginis terkait kesaksian perempuan sangat dipengaruhi oleh cara pembacaan yang tekstual terhadap teks-teks keagamaan.
Menurutnya, produk-produk fikih yang memberlakukan ketentuan dua banding satu (2:1) untuk semua bentuk kesaksian perempuan. Serta membatasi kesaksian perempuan hanya dalam urusan utang-piutang dan harta benda, adalah konsekuensi logis dari pembacaan literal terhadap ayat dan hadis tanpa memperhatikan asbāb an-nuzūl (sebab turunnya ayat), asbāb al-wurūd (sebab munculnya hadis), dan konteks sosial yang lebih luas.
Dalam konteks ini, ayat yang paling sering menjadi dasar adalah QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbicara tentang kesaksian dalam urusan utang-piutang:
“…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai…”
Pembacaan tekstual terhadap ayat ini menghasilkan kesimpulan bahwa nilai kesaksian perempuan hanya setengah dari laki-laki. Bahkan membatasi wilayah kesaksian perempuan hanya pada urusan keuangan.
Kasus Pidana
Dari sinilah muncul pandangan bahwa dalam kasus-kasus pidana, seperti hudūd atau qishāsh, kesaksian perempuan dianggap tidak sah.
Namun, menurut Nyai Badriyah, cara baca seperti ini perlu kita kritisi dan buka ruang reinterpretasi. Sebab, ayat tersebut berbicara dalam konteks spesifik yaitu transaksi utang-piutang pada masa ketika perempuan belum banyak terlibat dalam urusan publik, termasuk administrasi keuangan.
Dengan demikian, ketentuan dua perempuan untuk satu laki-laki bukanlah ukuran nilai moral atau intelektual, melainkan langkah antisipatif agar kesaksian menjadi lebih akurat di tengah kondisi sosial saat itu.
Lebih jauh, Nyai Badriyah mengingatkan bahwa dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat lain yang juga berbicara tentang kesaksian, seperti QS. An-Nisa (4):15, QS. Al-Maidah (5):106, QS. An-Nur (24):4, dan QS. Ath-Thalaq (65):3).
Namun, menariknya, ayat-ayat ini tidak menyebutkan adanya pembatasan gender dalam kesaksian. Dalam konteks ini, dapat kita simpulkan bahwa al-Qur’an sendiri tidak secara universal membatasi kesaksian perempuan. Melainkan berbicara sesuai konteks peristiwa dan kebutuhan sosial yang terjadi saat wahyu turun. []