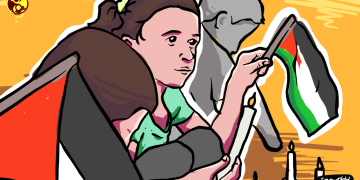Mubadalah.id – Sebagai orang awam yang baru mengenal isu disabilitas, saya sempat tertegun ketika mengikuti webinar dari Ibu Ro’fah, PhD. Saya tidak menyangka beliau membuka pembicaraan bukan dengan teori hukum atau dalil fikih, melainkan dengan membahas makna dari sebuah kata. Awalnya saya bingung, apa hubungannya makna dengan isu disabilitas? Tapi setelah dijelaskan, saya mulai paham bahwa justru di situlah akar persoalannya.
Iya, kata blio, bagaimana kita menyebut sesuatu akan memengaruhi cara kita memperlakukannya. Karena itu kontestasi makna bukan sekadar urusan bahasa, tapi juga soal kuasa dan cara pandang. Dari sanalah saya sadar, perubahan istilah dari “cacat” ke “disabilitas” bukan perkara sepele, melainkan langkah penting untuk mengubah cara masyarakat memaknai kemanusiaan secara lebih utuh.
Pun, kadang perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil, termasuk dari sebuah kata. Sebab, bahasa bisa memuliakan, tapi juga bisa melukai. Begitu pula dengan istilah disabilitas dan cacat. Dua kata yang tampak mirip, namun membawa pandangan yang sangat berbeda terhadap manusia yang menyandangnya.
Dalam percakapan sehari-hari, kata cacat masih sering terdengar, entah di media, ruang publik, atau lembaga resmi. Padahal di baliknya tersimpan cara pandang lama yang menempatkan difabel sebagai “yang kurang” atau “yang tidak sempurna.” Sebaliknya, istilah disabilitas lahir dari kesadaran baru bahwa setiap manusia memiliki keberfungsian berbeda, dan perbedaan itu tak seharusnya menghapus martabatnya.
Penyebutan disabilitas menawarkan cara pandang yang lebih adil: bahwa yang perlu diubah bukan tubuh seseorang, melainkan sistem sosial yang belum ramah. Hambatan bukanlah milik individu, tetapi hasil dari relasi sosial yang timpang, trotoar yang tak ramah kursi roda, ruang publik tanpa penunjuk braille, atau sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus. Iya, masalahnya bukan “cacat tubuh,” melainkan “cacat sistem dan pikiran.”
Ketika Bahasa Mengubah Cara Pandang
Bahasa tidak pernah netral. Ia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan wadah tempat manusia membangun makna dan realitas sosial. Setiap kata membawa nilai, cara pandang, dan posisi kuasa di dalam masyarakat. Karena itu, bagaimana kita menamai sesuatu akan menentukan bagaimana kita memperlakukannya.
Dalam konteks disabilitas, perubahan istilah dari cacat ke disabilitas menunjukkan pergeseran kesadaran. Kata cacatmerepresentasikan cara pandang lama yang menilai tubuh dari ukuran “sempurna” atau “tidak sempurna”. Sebaliknya, istilah disabilitas lahir dari pemahaman baru bahwa setiap manusia memiliki perbedaan kemampuan, dan hambatan justru muncul dari lingkungan yang belum ramah dan adil.
Menurut Pierre Bourdieu, Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi modal simbolik yang memperkuat atau memecah dominasi dalam struktur sosial. Dalam hal ini, penyebutan “disabilitas” menjadi langkah simbolik untuk membongkar pandangan lama yang menempatkan difabel sebagai objek belas kasihan. Ia menggeser narasi dari “kekurangan” menjadi “keberagaman”.
Dengan demikian, perubahan istilah ini bukan sekadar perkara linguistik, tetapi juga tindakan sosial. Bahasa menjadi ruang perjuangan, tempat masyarakat menegosiasikan nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, ketika bahasa berubah, cara kita melihat dan memperlakukan manusia pun ikut berubah.
Islam dan Bahasa yang Memuliakan
Dalam pandangan Islam, keberagaman manusia adalah bagian dari tanda kebesaran Allah, bukan alasan untuk saling merendahkan. Setiap perbedaan—baik fisik, kemampuan, maupun latar belakang—adalah bagian dari sunnatullah yang mesti diterima dengan lapang hati.
Al-Qur’an mengingatkan kita, “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13). Artinya, ukuran kemuliaan manusia tidak pernah ditentukan oleh tubuh, rupa, atau kemampuan, melainkan oleh ketakwaan dan keikhlasan hatinya.
Lebih dari itu, para ulama menegaskan pentingnya adab dalam bertutur. Sebab, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cermin dari akhlak. Kata-kata yang kasar, merendahkan, atau menyinggung martabat seseorang bisa menjadi bentuk kezaliman yang halus dan amat menyakitkan. Maka, menjaga lisan berarti juga menjaga kehormatan sesama manusia. Pun itu juga bagian dari iman.
Dari sinilah, memilih kata “disabilitas” alih-alih “cacat” bukan sekadar urusan istilah, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai Islam: memuliakan manusia sebagaimana Allah memuliakannya. Bahasa menjadi jembatan kasih, bukan tembok jarak. Ia bukan hanya mengubah cara kita berbicara, tetapi juga cara kita memandang dan memperlakukan sesama dengan penuh hormat dan empati.
Menjaga Makna, Merawat Kemanusiaan
Penyebutan “disabilitas” sejatinya bukan sekadar urusan istilah modern atau perubahan bahasa yang mengikuti zaman. Ia adalah upaya menjaga makna agar tetap berpihak pada kemanusiaan. Di dalamnya ada kesadaran bahwa setiap kata membawa nilai, dan setiap nilai mencerminkan cara kita memperlakukan sesama. Dengan memilih kata yang memuliakan, kita sedang menegaskan bahwa setiap manusia, apa pun kondisinya, berhak atas penghormatan yang sama tanpa stigma dan tanpa diskriminasi.
Pada akhirnya, perjuangan menuju masyarakat inklusif tidak berhenti pada perubahan istilah, tetapi berlanjut pada perubahan cara pandang. Sebab, bahasa hanyalah pintu masuk menuju hati dan tindakan. Inklusivitas sejati lahir ketika kita mampu melihat manusia bukan dari kekurangannya, tetapi dari martabat dan potensinya.
Dan mungkin, dari hal sederhana seperti memilih kata yang tepat, kita sedang menanam benih kemanusiaan. Sebuah langkah kecil yang jika bisa kita rawat bersama, maka akan tumbuh menjadi “pohon besar” bernama keadilan dan kesetaraan. []