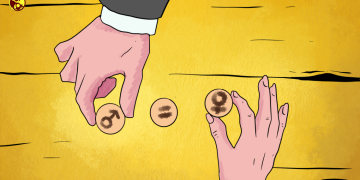Mubadalah.id – Aku sering merasa, kata toleransi sekarang terlalu ramai. Ia muncul di spanduk, seminar, poster kampanye, bahkan jadi jargon kebajikan yang orang-orang rebutkan. Kayaknya, semua orang ingin terlihat toleran. Semua ingin tampak sebagai pihak yang paling dewasa dalam menghadapi perbedaan. Padahal, dalam hidup sehari-hari, toleransi sering kali jauh lebih sederhana, dan justru karena itu, ia tidak selalu kasat mata.
Aku pun pernah ada di fase itu. Atau mungkin masih. Sampai akhirnya aku belajar satu hal: toleransi yang paling jujur biasanya tidak perlu kita umumkan. Ia tidak butuh panggung. Ia bekerja diam-diam, dalam cara kita tidak terganggu oleh keberadaan orang lain yang berbeda dari kita. Bukan karena kita sudah memahami semua perbedaan itu. Bukan karena kita setuju. Tapi karena kita tidak merasa terancam.
Toleransi sebagai Sikap Batin
Buatku, toleransi bukanlah paham besar. Ia bukan ideologi. Ia bahkan tidak selalu berkaitan dengan wacana akademik atau teologis yang rumit. Toleransi adalah sikap batin yang sangat personal. Intinya sederhana: Lapang dada. Ketika aku tidak risih dengan keyakinan, kebiasaan, atau tradisi orang lain yang berbeda dariku. Itu saja.
Aku tidak perlu kok sampai ikut merayakan. Tidak harus memahami secara mendalam. Tidak juga wajib membela di setiap forum. Cukup tidak mengusik, tidak merendahkan, dan tidak merasa perlu “membenarkan” mereka dengan ukuranku sendiri.
Dalam pengertian ini, toleransi tidak selalu aktif. Ia sering kali pasif. Tapi bukan pasif yang apatis, melainkan pasif yang sadar akan batas. Aku tahu di mana wilayahku. Aku tahu di mana wilayah orang lain. Dan aku memilih untuk tidak melanggarnya. Maka, toleransi tidak selalu tampak heroik. Kadang ia hanya hadir dalam bentuk paling sederhana: membiarkan orang lain hidup dengan caranya, tanpa merasa terganggu oleh fakta bahwa caranya tidak sama denganku.
Ketika Toleransi Terlalu Dibebani
Masalahnya, kini toleransi jadi terlalu banyak makna. Ia seperti paksaan untuk menjadi bukti moral. Jadi beban. Kadang, harus selalu spektakuler. Bahkan, ada juga yang menjadikannya sebagai alat pembenaran diri: lihat, aku toleran, berarti aku sudah paling benar, kan?
Di titik ini, aku khawatir toleransi justru kehilangan hakikatnya. Karena seharusnya, toleransi bukan soal menjadi lebih unggul dari yang lain. Ia bukan kompetisi siapa paling terbuka. Ia juga bukan pengakuan bahwa semua keyakinan harus kita setujui. Toleransi tidak menuntut persetujuan. Ia hanya menuntut ketidak-bermusuhan.
Aku bisa tidak setuju, tapi tetap tidak mengganggu.
Boleh berbeda, tanpa merasa perlu mengoreksi.
Berhak untuk berjarak, tanpa harus memusuhi.
Dan menurutku, di situlah toleransi menemukan bentuknya yang paling jujur.
Batas Toleransi
Namun, aku juga belajar bahwa toleransi punya batas. Ia berhenti pada wilayah kenyamanan personal. Ia tidak selalu cukup untuk menjawab persoalan yang lebih besar: ketimpangan, ketidakadilan, diskriminasi, dan relasi kuasa.
Toleransi bisa membuatku tidak risih dengan perbedaan. Tapi ia tidak otomatis membuatku peka pada struktur yang menindas atas nama perbedaan itu sendiri. Di sinilah kita sering keliru. Kita merasa sudah “selesai” hanya karena tidak terganggu. Padahal, ketidak-risihan personal tidak selalu berarti keadilan sosial.
Dan di titik inilah, pembicaraan tentang pluralisme menjadi penting.
Pluralisme Bukan Sekadar Toleransi
Pluralisme bukan sekadar versi “lebih keren” dari toleransi. Ia bukan toleransi yang diperbesar. Pluralisme adalah paham, sebuah cara pandang terhadap kenyataan sosial.
Kalau toleransi bertanya: apakah aku nyaman dengan perbedaan?
Pluralisme bertanya: bagaimana perbedaan itu diakui, diatur, dan diperlakukan secara adil dalam kehidupan bersama?
Pluralisme mengakui bahwa perbedaan bukan anomali. Ia bukan gangguan yang harus diredam agar harmoni tetap terjaga. Perbedaan adalah fakta sosial, bahkan fakta kemanusiaan. Karena itu, pluralisme tidak berhenti pada perasaan individu. Ia masuk ke wilayah relasi sosial, kebijakan, pendidikan, dan bahkan teologi. Dalam pluralisme, perbedaan tidak hanya “diterima”, tapi juga sah dan setara.
Dari Nyaman ke Bertanggung Jawab
Di titik ini, aku sadar: toleransi membuat kita nyaman, tapi pluralisme menuntut kita bertanggung jawab.
Intinya, pluralisme mengajak kita bertanya:
Siapa yang selama ini paling sering diminta toleran?
Pihak mana yang keyakinannya dianggap “normal”, dan mana yang terus-menerus diminta menyesuaikan diri?
Siapa yang punya kuasa mendefinisikan batas kewajaran?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa kita jawab hanya dengan sikap pribadi. Ia membutuhkan kesadaran kolektif. Itulah mengapa pluralisme selalu beririsan dengan keadilan. Ia tidak cukup puas dengan hidup berdampingan secara damai, kalau kedamaian itu kita bangun di atas ketimpangan.
Dalam Konteks Keberagamaan
Dalam konteks keberagamaan, perbedaan antara toleransi dan pluralisme sering kali makin terasa. Toleransi memungkinkan kita berkata: silakan kamu beriman dengan caramu, aku dengan caraku. Pluralisme mendorong kita melangkah lebih jauh: bagaimana relasi antariman ini dibangun tanpa hierarki, tanpa klaim superioritas sosial, dan tanpa peminggiran.
Beberapa pemikir, seperti Nurcholish Madjid, pernah menegaskan bahwa pluralitas adalah sunnatullah, kenyataan yang tidak bisa diingkari. Tapi mengakui pluralitas berbeda dengan mengelolanya secara adil. Di situlah pluralisme bekerja.
Pluralisme tidak meminta kita mengaburkan keyakinan. Ia juga tidak memaksa semua agama menjadi sama. Justru sebaliknya: pluralisme meminta kita jujur pada perbedaan, tanpa menjadikannya alasan untuk mendominasi.
Aku percaya, tidak semua orang harus menjadi pluralis dalam pengertian paham. Tidak semua orang punya akses, waktu, atau kebutuhan untuk masuk ke perdebatan itu. Tapi rasanya penting untuk jujur pada istilah. Karena pluralisme bukan hanya soal niat baik. Ia soal keberpihakan.
Belajar Bersikap Secukupnya
Mungkin, yang kita butuhkan hari ini bukan semakin banyak jargon, tapi semakin banyak kejujuran.
Kejujuran untuk mengakui:
Aku toleran sejauh aku tidak terganggu, dan aku masih belajar untuk adil di tengah perbedaan. Toleransi yang sunyi itu tidak salah, ia justru pondasi. Pluralisme yang bekerja itu tidak mudah, tapi ia perlu. Dan di antara keduanya, akhirnya kita belajar satu hal penting: hidup bersama bukan soal siapa paling benar, tapi siapa yang paling bersedia tidak melukai. []