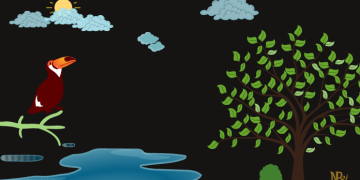Mubadalah.id – Sudah hampir dua pekan Sumatra dan Aceh berselimut duka. Puing-puing bangunan berserakan tak mengenal tempat. Rumah-rumah tertimbun tanah hampir menyentuh atap. Banyak nyawa yang hanya tinggal jasad.
Parahnya lagi, tumpukan potongan kayu hasil kerakusan segelintir orang memadati pemukiman warga. Semua itu bukan lagi isyarat, melainkan penampakan nyata yang menggambarkan bahwa bencana Sumatra adalah luka semua rakyat Indonesia.
Penyebab bencana Sumatra adalah kombinasi manusia dan alam
Banyak pakar dan peneliti mengurai penyebab banjir bandang yang terjadi di provinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Selain faktor alam, manusia turut menyumbang kerusakan ekologis secara masif.
Setelah melansir dan menghimpun data dari berbagai media, berikut penyebab bencana Sumatra versi alam. Curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir di Pulau Sumatra tergolong tinggi karena Siklon Tropis Senyar, yaitu mencapai lebih dari 300 milimeter setiap hari. Kondisi ini dinilai ekstrem untuk wilayah tropis.
Dari sisi topografi, wilayah terdampak termasuk dataran rendah yang menjadi hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Yaitu tempat berkumpulnya aliran air dari dataran tinggi. Selain itu, jenis tanah di sana adalah tanah lempung yang sulit menyerap air.
Pendangkalan sungai ikut memperparah kondisi tersebut. Sendimen yang terbawa dari hulu, sampah rumah tangga, dan perubahan bentuk sungai menyebabkan kapasitas menampung air berkurang.
Nah, yang bikin bencana ini memiliki daya rusak besar adalah pengelolaan hutan yang jauh dari makna kelola itu sendiri. Deforestari hutan besar-besaran untuk perkebunan sawit, penambangan, penyalahgunaan lahan, dan pembalakan liar. Ironinya kerakusan membabi buta hingga membabat hutan lindung. Sudah sangat jelas hutan lindung untuk dilindungi, namun malah sebaliknya.
Hutan yang sudah ratusan tahun memiliki ekosistem tersendiri. Akarnya yang besar dan kuat mampu menampung air dalam skala besar. Dedaunan yang rimbun berfungsi menahan air agar tidak langsung jatuh ke tanah. Jika penopang ekosistem sudah rusak dari hulu, maka hilir tinggal menunggu dampak buruknya.
Ekoteologi bukan lagi wacana melainkan keharusan
Gelondongan kayu yang terbawa derasnya banjir bandang hingga menghamtam pemukiman warga adalah bukti, bahwa kerakusan manusia turut memperparah bencana Sumatra. Kalah telak, pemerintah tidak bisa lagi berkelit untuk menutupi kegagalannya dalam amanat menjaga hutan.
Berdasarkan data dari global forest watch, pada periode 2015-2024 Indonesia termasuk ke dalam sepuluh negara deforestasi terbesar di dunia yaitu kurang lebih 10 juta hektar. Sehingga Indonesia menduduki posisi kedua setelah Brazil.
Melalui data di atas, pemerintah harus sadar bahwa narasi ekoteologi bukan lagi wacana, melainkan keharusan. Beberapa bulan lalu, Kementerian Agama mengampanyekan ekoteologi sebagai identitas insan yang berketuhanan. Berangkat dari itu pemerintah harus bekerja sama dalam merealisasikan ekoteologi, khususnya mengembalikan hutan kepada fungsi asalnya. Bukan lagi melihat hutan dari kacamata ekonomi semata.
Ekoteologi merupakan interpretasi nilai-nilai Alqur’an terhadap kelestarian lingkungan. Manusia mengemban tugas khalifatullah fil ardh. Yaitu wakilnya Allah untuk menjaga keseimbangan ekosistem bumi.
Pemerintah yang memiliki wewenang lebih atas pengelolaan dan konservasi hutan harusnya mengoptimalkan tanggung jawab tersebut sebaik mungkin. Boleh memanfaatkan hutan sebagai sumber daya, namun secukupnya. Jangan berlebihan, apalagi sampai menyengsarakan rakyat.
Bencana Sumatra mengingatkan kita pada tafsir dari Qs Ar-Rum ayat 1.
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ٤١
Artinya “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.
Tobat ekologis melalui ekoteologi
Pemerintah yang berbuat kerusakan, namun rakyat yang harus merasakan akibatnya. Ini sangat tidak fair. Pemerintah harus segera melakukan tobat ekologis sebelum semuanya terlambat terlalu jauh.
Ekoteologi menawarkan kerangka etis untuk membenahi kebijakan lingkungan. Yaitu dengan mengelola hutan dengan penuh rasa hormat, menjadikan komunitas adat sebagai mitra konservasi, dan menolak pembangunan yang mengorbankan keseimbangan ekologis.
Sumatra pernah menjadi contoh harmonisasi hutan dan manusia. Namun ketika nilai itu digantikan dengan logika ektraktif dan kebijakan perizinan yang permisif, keseimbangan ekosistem di sana mulai runtuh. Akibatnya, bencana terus berulang dan skalanya jauh lebih besar.
Hubungan manusia memiliki dua sisi yaitu vertikal (kepada tuhan) dan horizontal (kepada sesama makhluk ciptaan-Nya). Alam merupakan bagian dari makhluk-Nya yang harus kita jaga sebagai bentuk komunikasi yang baik.
Setelah bantuan logistik, layanan kesehatan, akses jalan dan komunikasi, serta evakuasi korban, pemerintah harus mulai menata ulang dari akar masalahnya langsung. Yaitu mengembalikan hutan ke dalam fitrahnya dan mengelolanya dengan berbasis ekoteologi. []