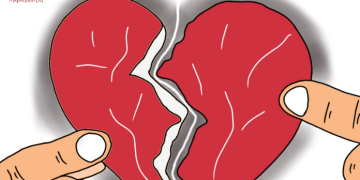Mubadalah.id – Beragamnya istilah tentang politik, iklim yang berubah secara cepat, dan konflik agraria yang tak kunjung usai, muncul wacana yang merangkai dua persoalan besar. Ketidakadilan gender dan kerusakan lingkungan. Gerakan Ekofeminisme hadir sebagai pendekatan dalam merespon ketidakadilan perempuan dengan eksploitasi alam—secara perlahan mendapatkan tempat dalam perdebatan diruang publik Indonesia.
Namun disisi lain, gerakan ekofeminisme berjalan di bawah bayang-bayang politik, kebijakan negara, korporasi perkebunan dan pertambangan hingga konflik agraria yang memecah belah konsentrasi gerakan komunitas.
Dalam hal ini, penulis berupaya memotret ekofeminisme tumbuh, dan tuntutan yang ia gagas. Selain itu bagaimana politik nasional dapat mempengaruhi (atau menghalangi) perjalanan dari gerakan ekofeminisme di Indonesia.
Penjelasan teoritis, ekofeminisme lahir dari pemikiran feminis yang menyoroti akar masalah lingkungan bukan hanya menyoal teknis atau ekonomi, melainkan masalah relasi kuasa berbasis gender.
Vandana Shiva, tokoh ekofeminisme asal India menjelaskan bahwa marginalisasi perempuan dan perusakan keanekaragaman hayati berjalan beriringan. Sistem patriarki dan kapitalisme ekstraktif—menempatkan alam dan perempuan pada posisi rentan dan dieksploitasi. Sederhananya, ketika sistem menganggap tubuh perempuan dan tubuh bumi sebagai “sumber” yang dapat tereksploitasi, maka kerusakan ekologis dan ketidakadilan gender saling menguat.
Ekofeminisme Bertumbuh di Indonesia
Diskusus mengenai ekofeminisme di Indonesia menjadi perhatian penting bagi kalangan akademik dan aktivis dalam dua dekade terakhir. Kemunculan publikasi riset dan studi lokal mulai menguraikan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu bagaimana kebijakan lingkungan seringkali abai dalam menggunakan sudut pandang gender.
Misalnya, kajian hukum dan sosial mengangkat soal kebijakan pengelolaan hutan, dan reklamasi. Atau bahkan tentang tambang yang mengabaikan peran perempuan sebagai penjaga mata pencaharian keluarga dan pengetahuan lokal yang krusial bagi keberlanjutan.
Indonesia merupakan negara dengan hutan tropis yang luas—namun tekanan deforestasi benar-benar nyata adanya. Global Forest Watch mengungkapkan hilangnya hutan alam dalam skala besar pada tahun terakhir. Lonjakan deforestasi pada 2023 ditengarai terkait konvensi lahan untuk perkebunan, pertambangan dan infrastruktur.
Selain itu, kerusakan juga dapat menghantam komunitas lokal yang bergantung hidupnya pada tanah. Perempuan seringkali terdampak dalam kehilangan mata pencaharian, akses air, dan ketahanan pangan rumah tangga.
Kerentanan terhadap Bencana
Lalu dampak lain adalah meningkatnya kerentanan terhadap bencana. Misalnya, penggundulan hutan memperbesar risiko banjir dan longsor. Tentunya terdapat beban perawatan, pemulihan ekonomi keluarga dan beban kerja domestik yang lebih besar pada perempuan.
Hal ini memperjelas alasan mengapa perspektif gender tak dapat terpisah dari kebijakan lingkungan yang berkeadilan. Contoh konkretnya, kekuatan perempuan dalam konservasi: AP News melaporkan bahwa tim patroli berbasis perempuan di Aceh berhasil menekan laju deforestasi di kawasannya melalui patroli, pendekatan komunitas dan advokasi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan bukan sekadar retorika, melainkan strategi efektif dalam pengelolaan hutan.
Kemudian, perempuan bergerak dalam bentuk protes lokal terhadap proyek ekstraktif. Kasus Wadas merupakan bukti perlawanan warga (termasuk perempuan) terhadap penambangan batu andesit yang mengancam lingkungan dan sumber penghidupan. Kasus ini menjadi studi kasus kajian ekofeminisme.
Perempuan dapat memainkan peran sentral dalam mempertahankan ruang hidup secara kolektif serta menyusun perjuangan sebagai isu keadilan ekologis dan gender. Fenomena ini menjadi diskursus dalam kajian dan riset akademik sebagai wujud ekspresi ekofeminisme di Indonesia.
Ekofeminisme dalam Bayang Politik
Politik nasional berperan besar dalam menyoal isu lingkungan—khususnya dalam gerakan ekofeminisme. Politik yang pro-ekstraksi—secara intensif menjalankan agenda investasi besar di sektor sawit, pulp & paper, pertambangan. Hingga akhir-akhir ini soal nikel—yang berbenturan dengan tuntutan hak masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan.
Seringkali kebijakan yang memberikan izin konsesi luas tanpa konsultasi bermakna dengan perempuan dan komunitas lokal (masyarakat adat). Hal ini mengakibatkan perpindahan mata pencaharian dan erosi penghidupan masyarakat tradisional. Dalam banyak kasus, aturan perizinan dan tata ruang tidak memasukkan pendekatan gender, sehingga “keadilan lingkungan” tidak ada roh semangat dimensi feminisnya.
Selain itu, wacana keamanan dan kriminalisasi terhadap warga sipil yang protes digunakan untuk meredam perlawanan rakyat (termasuk perempuan). Sehingga gerakan yang berangkat dari ekofeminisme berhadapan dengan risiko represi.
Kasus konflik agraria menunjukkan bagaimana negara dan korporasi berpotensi dapat mempolitisasi perlawanan rakyat. Lantas menempatkan aktivis perempuan pada posisi yang rentan terhadap intimidasi dan kriminalisasi.
Strategi Gerakan Ekofeminisme di Indonesia
Oleh karena itu, strategi yang kita tempuh dalam gerakan ekofeminisme di Indonesia, dapat kita lakukan dengan cara: Pertama, advokasi kebijakan sebagai bentuk upaya pengakuan peran perempuan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam serta memasukkan perspektif gender dalam tata ruang, pengelolaan hutan dan perizinan.
Sejumlah peneliti dan organisasi perempuan mendesak penyusunan kebijakan yang sensitif gender melalui Nationally Determined Contributions (NDCs) dan program kehutanan.
Kedua, pemberdayaan lokal melalui program pelatihan kepemimpinan perempuan di komunitas pesisir, hutan dan agraria (contohnya program akselerator perempuan lingkungan) dengan memperkuat kapasitas aksi kolektif dan menyediakan model alternatif dalam pengelolaan sumber daya berbasis komunitas.
Womens Earth Alliance berkantor di Amerika Serikat, melaporkan program inisiatif pelatihan yang melibatkan ratusan perempuan untuk berbagi praktik adaptasi dan konservasi.
Ketiga, ligitasi dan dokumentasi sebagai bukti dampak lingkungan yang menempatkan perempuan sebagai pelaku utama, serta hukum untuk menuntut pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan.
Keempat, aliansi luas dengan membangun koalisi antara organisasi perempuan, kelompok adat, organisasi lingkungan, akademisi dan jaringan internasional. Aliansi menjadi penting agar tuntutan yang terbawa dalam gagasan ekofeminisme tidak tersisih sebagai isu yang sempit, melainkan masuk dalam agenda perubahan struktural.
Tantangan: Apa yang Harus Dilakukan?
Meskipun ekofeminisme menjadi gerakan yang positif dalam penegakkan keadilan lingkungan—menghadapi kritik dan dilema. Beberapa versi ekofeminisme dalam kacamata essensialis—memposisikan perempuan sebagai “lebih dekat dengan alam” secara esensinya, memperkuat stereotip gender hanya terpahami secara tradisional dan menutup ruang untuk kritik terhadap peran gender yang berbeda.
Oleh karena itu, versi yang berkembang di Indonesia lebih banyak berusaha menyatukan perspektif interseksional: mengaitkan gender dengan kelas, etnisias, dan status hukum (misalnya hak atas tanah) untuk memahami siapa yang dirugikan oleh ekstraksi dan kebijakan publik. Kajian lokal menegaskan perlunya pendekatan yang tidak simplistik dan selalu menanyakan siapa yang kita beri suara dan siapa yang tersisihkan.
Sehingga tujuan untuk keadilan ekologis yang adil gender. Langkah yang dapat kita lakukan di antaranya: Pertama, menggunakan perspektif gender secara eksplisit dalam perencanaan tata ruang, izin pertambangan/perkebunan, dan rencana aksi iklim nasional. Kedua, mendorong partisipasi bermakna perempuan—bukan hanya “representasi” simbolis dalam pengambilan keputusan lokal dan nasional menyoal sumber daya alam.
Ketiga, perkuat perlindungan hukum untuk aktivis lingkungan perempuan agar tak mudah dikriminalisasi. Keempat, mengakui dan mendanai prakarsa lokal perempuan sebagai solusi konservasi yang efektif, daripada mengutamakan solusi top-down—yang seringkali gagal dalam memperhitungkan realitas gender. Kelima, mendorong kajian akademi dan data terpilah gender di lingkungan yang menjadi dasar kebijakan berbasis bukti.
Ekofeminisme sebagai Lensa Politik dan Praktis
Ekofeminisme di Indonesia bukan sekadar teori berbasis akademik—melainkan dapat kita gunakan dalam lensa politik melalui dinamika kuasa, kebijakan, dan praktik ekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan perempuan dan bumi secara bersamaan.
Dalam konteks politik di Indonesia yang memberi ruang bagi investasi besar dan pembangunan infrastruktur, gerakan ekofeminisme hadir sebagai pengingat moral dan praktis: keadilan lingkungan mustahil tercapai tanpa keadilan gender.
Perempuan bukan hanya korban pasif dari kerusakan ekologis—melainkan menjadi penjaga pengetahuan, pelaku konservasi, dan penggerak solusi kolektif. Mengakui dan memperkuat peran ekofeminisme secara praksis berarti memperjuangkan keadilan melalui masukan terhadap kebijakan publik, bukan hanya sekadar retorika belaka. []