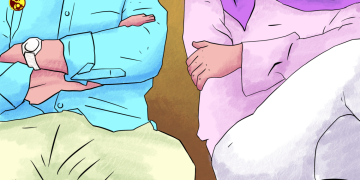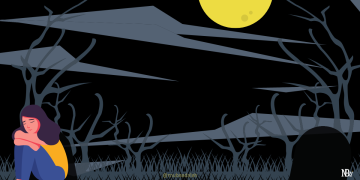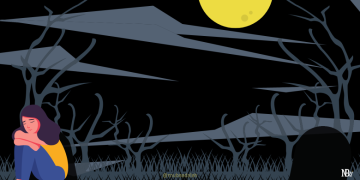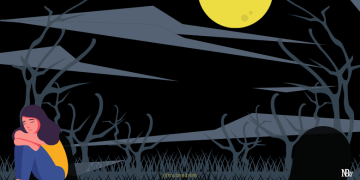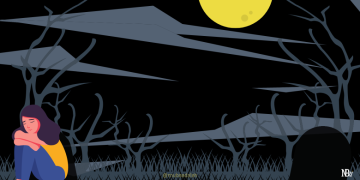Mubadalah.id – Media sosial ramai memperbincangkan sebuah adegan Gus Elham Yahya sebagai pendakwah yang sedang mencium anak kecil. Video lainnya menunjukkan unsur cat calling pada jamaah perempuan cantik, yang menghadiri pengajian Gus Elham tersebut. Video lain juga memperlihatkan Gus yang unjuk kebolehan menyanyi lagu dangdut dengan duduk di kursi majelis pengajiannya.
Berita ini mencuat, dan mayoritas kontra akan perilaku sosok Gus Elham Yahya. Selain sedang mencium pipi anak kecil dengan terjadi lebih dari sekali, video lainnya menunjukkan Gus yang sedang berada di tengah kerumunan para perempuan muda yang mengaguminya, bak selebritas.
Dalam dakwah, konten dan peran sosial, gelar Gus bisa memberi keunggulan simbolik berupa trust dan otoritas. Istilah Gus atau Gawagis adalah gelar kehormatan yang lazim di lingkungan pesantren di Jawa sebagai panggilan untuk putra-putri ulama Kyai atau Ibu nyai. Tindakan mencium anak kecil berulang kali adalah sebuah pelanggaran etika, adab dan potensi pelecehan.
Fenomena “Gus ngartis” semakin terasa. Sebutan Gus, seharusnya melekat pada warisan keilmuan, keteladanan, dan perjuangan sosial kiai pesantren, kini tereduksi menjadi label “selebritas.” Media sosial berubah menjadi panggung pamer dan validasi, bukan lagi ruang refleksi ilmu dan kritik sosial.
Grooming Behavior yang Mendapat Kritik Serius
Grooming behavior adalah proses manipulatif oleh pelaku kekerasan seksual untuk mendekati, memengaruhi, dan mengendalikan korban, terutama anak-anak atau remaja. Memiliki tujuan akhir yaitu melakukan pelecehan atau eksploitasi seksual.
Trah kiai dengan sebutan Gus memiliki peran sosial, budaya, ekonomi, dan media, panggilan hanya terjadi khusus di masyarakat pesantren dan komunitas Islam di Jawa. Gelar ini punya muatan simbolik, sosial, dan budaya yang melekat.
Masalah muncul ketika sebutan “Gus” dipakai sebagai modal branding personal, sementara substansi keilmuan dan kepekaan sosial mulai kabur. Tidak lagi bicara amar ma’ruf nahi munkar, maqasidu syari’ah, maslahatu amah atau ubudiyah melainkan dakwah menyesuaikan pasar melalui kata-kata manis, gombalan viral, atau gimmick khas influencer.
Alhasil, Gus lebih mirip selebritias ketimbang pewaris tradisi intelektual pesantren. Akibatnya, daya kritis ikut menghilang. Trah keturunan kiai yang awalnya menjadi harapan akan hadirnya sosok penerus dalam penegas moral dan pengingat keadilan memudar. Usai pengajian malah sibuk berpose bersama para lawan jenis, lalu menormalisasi mencium pipi anak kecil, di tengah maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, sungguh ironis.
Kondisi ini berbahaya, ketika seseorang yang memiliki relasi kuasa dengan melakukan hal yang tabu. Masyarakat kehilangan salah satu sandaran sebagai penjaga moral masyarakat melalui agama. Sebaliknya, publik hanya mendapat pertunjukan “kesalehan visual” seseorang yang bergelar Gus. Simbol status sosial tersebut menjadi identitas prestise. Simbol ini menjadi modal sosial yang menarik, hingga terjadinya desakralisasi gelar dan fungsionalisme kosong.
Memaknai Ulang Gelar Gus sebagai Trah Kiai
Gelar Gus sebagai “status sosial kosong” tanpa kontribusi nyata. Ketika sebuah popularitas menjadi. Dalam Islam, semua manusia sama, dan yang membedakannya adalah tingkat ketakwaan. Gelar Gus dalam konteks ini menjadi dogmatis, bebas kritik serta memperkuat budaya “kultus figur”.
Gelar “Gus” sering menjadi bobot simbolik yang lebih tinggi dibanding “Ning”. Dalam banyak konteks, peran kepemimpinan publik lebih sering memilih Gus untuk menjadi rujukan daripada Ning. Ning sering berada di dalam peran domestik atau pendidikan dalam pesantren, sehingga pengaruh publik terbatas jika perbandingannya dengan kiprah Gus.
Ketika Gus tampil dengan gaya hidup glamor, mobil mewah, barang bermerek, muncul pertanyaan: apakah gaya itu konsisten dengan pesan dakwah yang menekankan kesederhanaan. Ada ketegangan antara ekspektasi masyarakat terhadap kesederhanaan ulama vs kenyataan gaya hidup Gus tertentu. Potensi elitisme, apabila Gus menjadi simbol status tinggi, memunculkan sekat sosial antara santri “kelas bawah” dan “kelas atas”, mengarah ke kasta internal.
Harapan bahwa santri harus “naik kelas” agar layak mengikuti gaya Gus dapat membebani masyarakat secara ekonomi dan social. Fenomena Gus seharusnya tidak hanya menjadi glamor simbolik, tapi harus memiliki kontribusi nyata, substansi ilmiah, keagamaan, dan sudah seharusnya peran Gus membawa makna yang konstruktif.
Gus dan Relasi Kuasa dalam Isu Kekerasan Seksual
Otoritas keagamaan, melalui gelar Gus berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan yang memancing terjadinya kekerasan seksual. Grooming behavior bisa terjadi secara langsung maupun terselubung. Video gus Elham saat mencium anak kecil dengan mengulum pipi adalah sesuatu yang sensitif, dengan melibatkan anak di bawah umur, di depan public dan dalam sorotan kamera.
Label Gus seharusnya menjadi perwakilan otoritas moral, spiritual, dan sosial. Supaya memiliki pengaruh terhadap jamaah, terutama santri dan masyarakat awam. Sayangnya relasi sosial ini bersifat patriarkal dan hierarkis, di mana jamaah memosisikan diri sebagai pihak yang harus taat, manut, atau sami‘na wa aṭa‘na.
Menurut teori Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya berada di tangan penguasa politik, tetapi juga melekat pada pengetahuan, wacana, dan otoritas moral. Dalam konteks “Gus”, ada tiga bentuk relasi kuasa yang sering muncul. Pertama, potensi terjadinya kuasa simbolik karena gelar Gus adalah sebagai gelar terhormat karena keturunan kiai, atau wali. Jamaah sulit mengkritik dan menolak perilaku “Gus” meski bahkan jika terjadi perilaku yang tidak senonoh.
Kedua adalah kuasa spiritual, di mana Gus mendapat anggapan memiliki karomah atau barokah. Sehingga perintah dalam sebuah permintaan sentuhan, masyarakat menganggap sebagai bagian dari “ritual” mendapatkan karomah dan sulit untuk menghindarinya. Terlihat pula di beberapa video viral, menampilkan sosok Gus Elham yang menyentuh air minum dari jamaahnya. Jamaah dengan sangat bangga menerima air tersebut.
Ketiga, kuasa sosial-ekonomi, di mana Gus punya akses terhadap pendidikan, ekonomi dan status sosial tinggi. Sehingga memunculkan ketergantungan, terutama pada jamaah perempuan atau dhuafa. Jamaah sulit menolak perilaku tersebut, sama dengan menolak rezeki. Terlihat dalam video anak kecil tersebut tidak nyaman, namun berubah menerima ciuman karena mendapat uang saku sebagai imbalan bersedia mendapat ciuman di pipi. Video lainnya, jamaah dengan paras yang cantik sedang bertanya, namun justru menerima cat callling.
Jeratan Hukum terhadap Kekerasan Seksual oleh Tokoh Agama
Kekerasan seksual tidak selalu berupa paksaan fisik, tetapi sering muncul melalui manipulasi spiritual. Contohnya, pelaku yang meyakinkan korban bahwa tindakan tertentu seperti mencium adalah normal dan wajar. Pemanfaatan posisi kuasa seperti sosok Gus menganggap dirinya “berhak” melakukan kontak fisik karena statusnya lebih tinggi.
Hal demikian adalah bagian gaslighting religius, di mana korban menjadi merasa berdosa atau tidak sopan jika menolak. Beberapa kasus di pesantren menunjukkan bahwa pelecehan bisa terjadi oleh tokoh dengan gelar “Gus”, dan sulit tindak lanjut ke ranah hukum karena korban takut menjadi sosok yang mencemarkan keturunan ulama atau menodai nama baik pesantren. Kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan pelaku bergelar Gus di Jombang dan di Trenggalek.
Menurut Kimberlé Crenshaw dalam perspektif feminisme interseksional, memberi penekanan bahwa perempuan di lingkungan religius mengalami penindasan berlapis. Penyebab terjadinya kekerasan seksual antara lain penyebabnya gender, kelas sosial, dan posisi religius. Karena posisi Gus berada dalam relasi kuasa, maka tanggung jawab etik dan hukumnya lebih besar, bukan sebaliknya.
Anak bukanlah objek rasa gemas manusia dewasa. Anak adalah makhluk yang harus mendapat perlindungan. Pendidikan perlindungan anak berawal dari kesadaran diri, bahwa setiap bentuk pelecehan, sekecil apa pun, tidak boleh mendapat ruang. Baik di rumah maupun ruang publik seperti di sekolah, pesantren atau panggung dakwah. Dalam hal ini, kita harus memahami pokok persoalan. Para GUs seharusnya tahu bahwa setiap anak punya hak atas tubuhnya sendiri.
Dalam pendekatan sosio-legal, kekerasan seksual oleh tokoh agama tidak hanya pelanggaran moral saja. Terjadinya kekerasan seksual di pesantren oleh tokoh agama adalah bentuk pelanggaran kepercayaan publik dan hukum pidana, hal ini tertulis dalam Undang-Undang Tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022. []