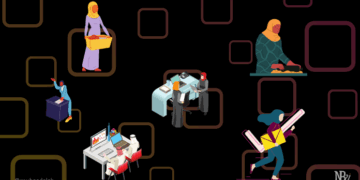Mubadalah.id – Murni berdiri di depan pintu rumah kontrakan, memegang kantong belanjaan majikannya. Wajahnya letih, rambutnya basah oleh keringat meski senja sudah turun. Di dalam rumah yang pengap, Rara—anak semata wayangnya—berusaha keras mengerjakan PR sekolah sambil mengipas adiknya yang sedang panas tinggi.
Jam dinding sudah menunjuk pukul delapan malam. Murni baru pulang setelah bekerja sejak fajar menyingsing. Hari-hari seperti ini sudah bertahun-tahun dijalaninya. Ibunya dulu juga pekerja rumah tangga. Jalan hidup yang tampaknya diwariskan begitu saja tanpa sempat dipertanyakan.
“Yang penting halal,” kata ibunya dulu, dan kini Murni mengulang kalimat yang sama, meski dalam hatinya, ada jeritan yang tak pernah padam: “Jangan sampai anakku seperti aku.”
Namun kenyataan berbicara lain. Upah jauh dari UMR, tanpa kontrak yang jelas, tanpa jaminan kesehatan atau hak cuti. Jika sakit, tetap harus bekerja. Jika tak kuat lagi, langsung diganti tanpa pesangon, tanpa ucapan terima kasih.
Suatu malam, tubuh Murni tumbang di rumah majikannya. Dilarikan ke rumah sakit, namun sudah terlambat. Paru-parunya rusak, tubuhnya kalah oleh kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun.
Di rumah duka yang sederhana, Rara memandangi jasad ibunya dengan mata kosong. “Aku nggak tahu harus bagaimana lagi,” bisiknya pada seorang kerabat yang memeluknya erat.
***
Di gedung parlemen, seorang anggota DPR memandangi layar ponselnya. Berita tentang Murni terpampang jelas: PRT meninggal akibat kelelahan, meninggalkan dua anak yang terlantar. Di bawahnya, berita lain muncul—tentang RUU Perlindungan PRT yang lagi-lagi tertunda pembahasannya.
Tangannya mengepal. Dia teringat percakapan beberapa bulan lalu dengan seorang konstituen yang menceritakan nasib saudaranya, seorang PRT yang hidup tanpa perlindungan hukum sedikit pun.
Hari itu, anggota DPR itu berdiri di tengah sidang, memegang map tebal RUU Perlindungan PRT, dan dengan suara lantang, ia meminta agar pembahasan segera diprioritaskan. Sorak sorai menyambut, ketok palu akhirnya menggema. Di layar berita malam itu, terpampang wajah-wajah bahagia PRT yang akhirnya merasa terakui dan terlindungi.
Namun suara alarm mendadak membuyarkan semuanya.
Anggota DPR itu terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu. Ia melirik meja di samping ranjang—di situ map RUU Perlindungan PRT masih tergeletak, utuh, belum ia sentuh lebih jauh. Di layar ponselnya, pesan terbaru dari kolega parlemen: “Bahas RUU PRT? Belum prioritas, Bro. Fokus dulu ke yang lain, arah pimpinan juga belum jelas.”
Dia memejamkan mata, dada sesak. Mimpi yang barusan hadir begitu nyata—tapi ternyata hanya mimpi. Realitasnya jauh lebih keras: rekan-rekan sesama anggota parlemen, para ketua partai, bahkan pemerintah sendiri, tak benar-benar memperlihatkan keberpihakan yang serius.
Di meja kerjanya, ia duduk terpaku, memandangi map RUU yang kini terasa semakin berat. Bagaimana menyadarkan mereka semua? pikirnya. Bagaimana memaksa nurani untuk berbicara di ruang-ruang kekuasaan itu?
Tak ada jawaban malam itu. Hanya buntu yang makin menyesakkan.
Di luar, fajar mulai menyingsing. Dan entah di sudut mana kota ini, seorang Rara yang lain tengah bersiap menggantikan ibunya—memulai lagi lingkaran pekerja rumah tangga yang tak kunjung putus.
***
Di dalam ruang kerjanya yang hening, sang anggota dewan menggenggam map RUU itu erat-erat. Matanya kosong menatap halaman-halaman yang penuh dengan janji-janji perlindungan yang tak kunjung ditepati. Kegetiran menggulung di dadanya—karena sesungguhnya, bukan hanya dia yang gagal.
Ia tahu, dirinya, kawan-kawan di parlemen, para ketua partai, dan terutama pimpinan DPR serta para menteri di kabinet, bahkan presiden yang selalu berbicara tentang keadilan sosial—mereka semua telah membiarkan lingkaran setan ini terus berputar. Mereka semua ikut bertanggung jawab atas setiap Murni yang tumbang, atas setiap Rara yang kehilangan masa depan, atas setiap pekerja rumah tangga yang hidup tanpa perlindungan.
Dan pagi itu, satu-satunya yang tersisa hanyalah diam. Diam yang pahit, diam yang sarat dosa bahkan nestapa—karena kekuasaan tanpa keberpihakan adalah pengkhianatan yang nyata. Dia merasakanya, serasa-rasanya. []