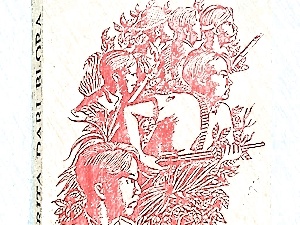Mubadalah.id – Pada periode antara 1945-1949, Pramoedya Ananta Toer menulis beberapa cerpen yang kemudian dibukukan dalam ‘Cerita dari Blora’. Kumpulan cerpen ini memotret kesengsaraan penduduk Blora, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Salah satu cerpen Pram yaitu ‘Inem’ saya baca kembali pada awal tahun 2018 ini.
Membaca cerpen ini, saya makin mengagumi sosok Pram dan kemampuannya memotret realitas atau lebih tepatnya, menyuguhkan realitas dengan kekayaan perspektif, utamanya perspektif gender.
Melalui cerpen ini, Pram meneguhkan dirinya sebagai sastrawan pembela hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan.
Ia lantang mengkritik relasi gender yang tidak setara dan menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua.
Baca juga: Menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan dengan Mubadalah
Inem, tokoh utama dalam cerpen Pram adalah seorang gadis kecil yang dinikahkan saat masih kanak-kanak oleh orangtuanya.
Alasan pernikahan ini klasik, yaitu kemiskinan. Kemelaratan mendorong orang tua Inem menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga.
Ada juga faktor lain bernama asas kepatutan yang dijunjung tinggi oleh hampir semua tokoh manusia dewasa dalam cerpen.
Pada usia 9 tahun, Inem kemudian menjadi janda setelah mengalami berbagai bentuk pelecehan oleh suami, orang tua, maupun anggota keluarga lainnya.
Baca juga: Menghentikan Petaka Pernikahan Anak
Siklus kemiskinan pun tak berhasil diputus oleh Inem dan keluarganya.
Keluarga Inem makin miskin karena menanggung utang biaya pesta perkawinan dan Inem pun makin babak belur, secara fisik dan mental, karena ia dianggap sebagai beban sekaligus aib keluarga.
Ada kesedihan mendalam yang menggelayut saat saya membaca kembali kisah Inem.
Kesedihan ini tentunya tak akan saya rasakan kalau pengalaman hidup saya tidak bertalian dengan kisah dalam cerpen Pram itu.
Sayangnya, realitas Inem masih saya temui hingga hari ini, setengah abad setelah Pram menulis ‘Inem’.
Anak-anak perempuan kita masih dikawinkan dengan berbagai dalih: agama, budaya, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Semuanya berkelindan jadi satu.
Baca juga: Nikah Muda; Relationship atau Relationshit?
Untuk membayangkannya dalam angka, UNICEF menghitung bahwa 1 dari 9 anak perempuan di negeri ini menikah sebelum berusia 18 tahun.
Mereka yang menikah dini empat kali lebih rentan untuk putus sekolah, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan mengalami komplikasi saat mengandung serta melahirkan.
Dalam perjuangan menuntut kesetaraan, para aktivis perempuan mengusulkan bahwa penggunaan istilah yang disepakati bersama dapat membantu para perempuan menamai bentuk-bentuk penindasan maupun kekerasan yang mereka alami.
Penamaan memberikan pemahaman dan mendorong pengakuan yang luas atas realitas hidup perempuan.
Pram memang tak secara khusus menamai realitas hidup Inem dalam cerpen yang ditulisnya, namun berpuluh-puluh tahun kemudian, Lies Marcoes dari Rumah KitaB menamainya untuk mendorong perubahan cara pandang maupun perilaku kita dalam menghadapi suatu persoalan.
Baca juga: Kyai Husein: Nikah Muda Tidak Maslahat
Bagi Lies Marcoes, Inem-Inem masa kini adalah korban dari fenomena yatim piatu sosial, yaitu hilangnya fungsi perlindungan bagi anak-anak yang seharusnya dijalankan tak hanya oleh orang tua, namun juga oleh komunitas sekitar.
Makna dari istilah ini tentu lebih luas dari sekadar tak berayah dan tak beribu.
Ia mencakup pengakuan bahwa kita sebagai sebuah komunitas sosial tak lagi menjalankan fungsi perlindungan. Dan harga yang harus kita bayar untuk itu amat sangat mahal: masa depan anak-anak kita.[]