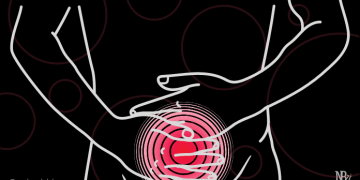Mubadalah.id – Suatu hari di Depok, saya mendengar kalimat yang terdengar biasa: “Ayo mampir, di sini ada SPG (Sales Promotion Girl) yang cantik-cantik.” Kalimat itu meluncur ringan, seolah tak menyisakan soal. Namun, justru karena kelumrahannya, kita layak mempertanyakannya. Sebab di balik ajakan sederhana itu, tersimpan cara pandang yang problematik terhadap tubuh perempuan dan relasi kerja.
Ucapan tersebut tidak sedang menawarkan kualitas produk, harga bersaing, atau pelayanan ramah. Ia justru menempatkan kecantikan perempuan sebagai daya jual utama. Di sini sangat jelas bagaimana budaya “patriarki” mereduksi perempuan. Dalam konteks ini, perempuan bukan sebagai subjek kerja yang profesional, melainkan sebagai alat untuk menarik konsumen. Praktik semacam ini menandai relasi yang timpang.
Kerja yang Kehilangan Martabat Relasional
Islam membangun relasi, termasuk relasi kerja dan ekonomi, dengan prinsip kesalingan (mutuality). Tidak boleh ada pihak dengan dalih apapun untuk merendahkan pihak lain.
Ketika tubuh perempuan menjadi umpan dagang, di sanalah relasi kehilangan kesalingannya. Keuntungan ekonomi mengalir ke pemilik usaha atau brand, sementara perempuan menanggung beban simbolik. Penampilan menjadi indikator nilai, bukan kompetensi. Kerja yang seharusnya menjadi sumber kehormatan, justru mempersempit makna “perempuan” sebagai subjek penuh.
Padahal dalam Islam, kerja adalah bentuk kemuliaan manusia. Nabi Muhammad saw bersabda
Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. (HR Bukhari)
Sangat jelas! bagaimana rupa bukan menjadi tolak ukur nilai kerja, melainkan dari usaha dan kejujuran. Praktik promosi berbasis tubuh perempuan jelas bertentangan dengan prinsip ini.
Bahasa yang Menormalisasi Objektifikasi Perempuan
Bahasa bukan sekadar alat komunikasi; ia membentuk kesadaran sosial. Frasa “SPG cantik” terdengar sepele karena sudah terlalu sering terulang di telinga khalayak. Namun pengulangan itulah yang menormalisasi objektifikasi.
Perempuan dipandang sebagai tampilan visual yang bisa dipamerkan, dinilai, dan digunakan untuk memancing transaksi. Identitas mereka sebagai pekerja dengan keterampilan komunikasi, pengetahuan produk, dan kemampuan melayani pelanggan menjadi tak terlihat dan terabaikan.
Dalam perspektif keadilan gender, ini adalah bentuk objektifikasi. ini berarti gagal memanusiakan manusia. Al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa Allah SWT memuliakan manusia dengan segala potensi yang melekat pada diri mereka (QS. Al-Isra: 70), tanpa syarat fisik tertentu. Ketika menjadikan kecantikan tubuh perempuan sebagai standar nilai, di situlah logika pasar mampu mereduksi anugerah kemuliaan itu.
Antara “Pilihan” dan Ketimpangan Struktural
Sering kali kritik terhadap praktik ini mendapat bantahan dengan narasi yang keliru, “Mereka kan mau.” Makanya, tidak cukup berhenti pada permukaan pilihan individual. Kita juga perlu melihat struktur yang membentuk pilihan tersebut.
Ketika lapangan kerja mensyaratkan standar fisik tertentu—usia, warna kulit, bentuk tubuh—memaksa perempuan beradaptasi agar tetap punya akses ekonomi. Persetujuan yang lahir dari keterbatasan pilihan, biasanya, tidak terlepas dari ketidakadilan struktural.
Di sinilah eksploitasi bekerja secara halus. Tidak selalu melalui paksaan langsung, tetapi lewat sistem yang membuat tubuh perempuan menjadi modal utama untuk bertahan hidup. Ini bukan sekadar soal individu, melainkan soal sistem yang memerlukan koreksi bersama.
Penting diperhatikan, kritik atau koreksi ini tidak diarahkan kepada SPG sebagai individu. Mereka adalah pekerja yang berjuang dalam sistem yang tersedia. Jika menyalahkan perempuan justru memperpanjang ketidakadilan.
Yang perlu kita kritik adalah sistem pemasaran dan cara pandang yang; mengukur nilai kerja dari penampilan, mengabaikan kompetensi dan profesionalisme, serta menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain secara simbolik.
Promosi yang Lebih Berkeadilan
Islam menaruh perhatian besar pada etika relasi. Al-Qur’an mengingatkan agar manusia tidak saling merendahkan (QS. Al-Hujurat: 11). Dalam konteks ini, merendahkan bukan hanya lewat hinaan verbal, tetapi juga melalui praktik sosial yang mengabaikan martabat.
Menjadikan tubuh perempuan sebagai alat promosi berarti memindahkan nilai manusia ke level komoditas. Etika berelasi ini seharusnya hadir bukan hanya dalam ruang ibadah, tetapi juga dalam praktik muamalah lain di kehidupan sehari-hari.
Sudah saatnya kita bertanya: mungkinkah melakukan promosi tanpa mengorbankan martabat? Jawabannya tentu mungkin dan sangat bisa. Pelaku usaha bisa melakukan strategi menjual produk lewat kualitas, pelayanan, kejujuran, dan profesionalisme—bukan lewat eksploitasi tubuh.
Perempuan bukan etalase dagang. Mereka adalah mitra kerja, subjek bermartabat, dan manusia utuh. Dalam etika relasi dalam ketenagakerjaan, keuntungan sejati bukan hanya soal laba ekonomi, tetapi tentang bagaimana membangun relasi secara adil dan saling memuliakan.
Jika keadilan adalah tujuan, maka cara mencapainya pun harus adil. []