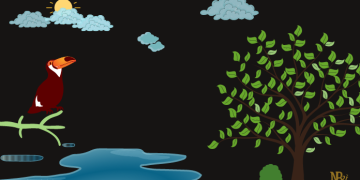Mubadalah.id – Maulid Nabi Muhammad ﷺ bukan sekadar perayaan lahirnya seorang manusia agung, melainkan pengingat hadirnya cahaya bagi kaum tertindas. Nabi lahir di tengah masyarakat jahiliyah yang sarat ketidakadilan.
Budak diperlakukan sebagai barang, perempuan dipandang rendah bahkan dikubur hidup-hidup, anak yatim ditelantarkan, dan fakir miskin dibiarkan kelaparan. Kehadiran Nabi menandai revolusi moral: agama turun bukan untuk melanggengkan status quo, membiarkan penindasan, tetapi untuk melindungi mereka yang lemah.
Sejak awal, kehidupan Nabi merefleksikan realitas itu. Beliau lahir sebagai yatim, lalu menjadi piatu pada usia muda. Yatim adalah simbol ketidakberdayaan—kehilangan sandaran, dianggap beban, hidup dalam keterbatasan.
Dari rahim kerentanan itulah Allah melahirkan pemimpin agung. Karena pengalaman itu, Nabi memiliki kedekatan khusus dengan anak yatim. Beliau bersabda: “Aku dan orang yang menanggung anak yatim akan berada di surga seperti ini,” sambil merapatkan jari telunjuk dan tengah (HR. Bukhari).
Hadis ini sering kita pahami sebatas janji pahala di akhirat, padahal juga mengandung pesan sosial yang radikal. Nabi yang lahir yatim mengingatkan kita: siapa pun yang punya kelebihan—harta, ilmu, akses—wajib menggunakan privilege-nya untuk memberdayakan yang lemah.
Menanggung anak yatim berarti tidak hanya menanti ganjaran di akhirat, tapi juga menghadirkan keadilan di dunia. Nabi sendiri menunjukkan bahwa keberdayaan sejati adalah berpihak: berdiri di barisan yang lemah, dan menjadikan kelebihan sebagai sarana mengangkat martabat orang lain.
Memaknai “Yatim”
Dalam konteks hari ini, “yatim” bisa kita maknai lebih luas sebagai rakyat yang tidak memiliki sandaran, karena negara—yang seharusnya menjadi “orang tua”—sering mangkir dari tanggung jawabnya. Maka, ikut menyuarakan suara rakyat, melakukan aksi, atau menghadirkan ruang agar jeritan mereka terdengar, adalah wujud nyata kepedulian terhadap “yatim” masa kini: mereka yang kehilangan penopang, tetapi tidak boleh kehilangan pembela.
Wajah profetik Nabi terlihat dalam keseimbangan sikapnya. Beliau lembut dan penuh kasih kepada rakyat kecil. Seorang pemuda pernah meminta izin berzina, Nabi tidak menghardiknya, melainkan mengajaknya berpikir dengan dialog yang menyentuh. Ketika seorang Badui kencing di masjid, Nabi tidak mencaci, tetapi menegur dengan tenang dan memberi solusi. Kasih sayang beliau nyata, terutama kepada mereka yang polos dan rentan.
Namun kelembutan itu bukan kompromi terhadap ketidakadilan. Nabi justru sangat tegas kepada mereka yang menyalahgunakan kuasa. Kisah perempuan Quraisy dari Bani Makhzum adalah pelajaran abadi. Setelah mencuri, para tokoh elit mencoba melobi agar hukumannya diringankan.
Nabi menolak keras: “Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah, bila orang terpandang mencuri, mereka biarkan. Bila orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.” (HR. Bukhari-Muslim). Prinsip Nabi jelas: hukum tidak boleh jadi alat membela elit sambil menindas rakyat kecil.
Menguji Nilai Kemanusiaan
Sayangnya, yang terjadi hari ini sering sebaliknya. Kita begitu lembut kepada pemerintah yang menggunakan kekuasaan untuk melakukan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Kita mudah memaklumi kebijakan yang menekan, bahkan menutup mata pada praktik korupsi.
Tetapi justru keras kepada rakyat kecil yang bersuara. Mereka yang turun ke jalan menuntut keadilan sering dilabeli anarkis, pencuri, kasar, atau berkata kotor—padahal aksi-aksi itu tidak lahir dari ruang hampa. Sikap mereka adalah buah dari sistem yang korup dan penuh ketidakadilan.
Di tengah ketidakadilan itu, perhatian publik pun kerap timpang. Kehilangan seorang pejabat terhadap barang tersier—sebuah lukisan pribadi, misalnya—dapat memicu empati luas. Sementara rakyat kecil yang kehilangan kebutuhan primer—beras, susu, ongkos sekolah, bahkan tanah dan hutan—sering kita anggap hal wajar, seolah bagian dari nasib.
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini distinction: kelas elit mampu mengangkat pengalaman pribadi mereka menjadi sesuatu yang mahal dan bermakna. Sebaliknya, pengalaman rakyat miskin yang penuh penderitaan jarang kita hargai. Padahal, justru di situlah nilai kemanusiaan diuji: apakah kita bisa melihat jeritan rakyat kecil sebagai sesuatu yang layak kita perjuangkan.
Meneladani Nabi
Dalam pandangan Nabi, orang miskin bukan sekadar “objek belas kasihan,” melainkan sahabat dan barisan yang beliau pilih. Nabi pernah berdoa: “Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud).
Ini bukan glorifikasi kemiskinan, melainkan penegasan keberpihakan: Nabi ingin berada bersama mereka, bukan menjauh di menara gading.
Karena itu, Maulid Nabi bukan hanya perayaan nostalgia, melainkan pengingat arah. Meneladani Nabi berarti menata kembali keseimbangan profetik: lembut pada rakyat kecil, tegas pada kekuasaan yang zalim. Menyempurnakan akhlak bukan sekadar memperindah bahasa, tetapi keberanian berpihak.
Jika agama ingin tetap hidup, ia harus membumi. Ia harus hadir di tengah rakyat kecil, mendengar suara mereka, meski bahasanya kadang keras. Sebab bahasa keras itu adalah jeritan ketidakadilan yang selama ini membebani mereka.
Nabi tidak lahir di istana, melainkan di pangkuan seorang ibu yang kehilangan suami, untuk menjadi pelindung bagi mereka yang kehilangan sandaran. Cahaya itu masih menyala—dan tugas kitalah untuk meneruskannya. []