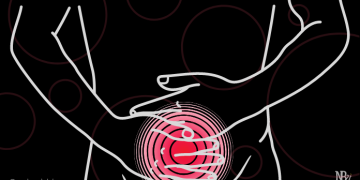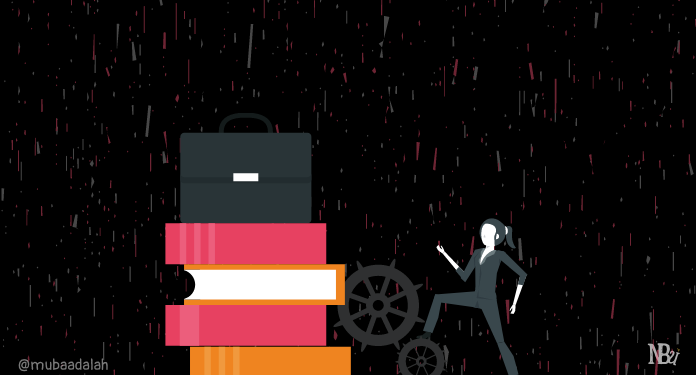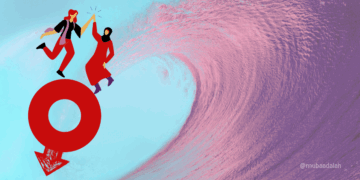Mubadalah.id – Di saat penulis mengikuti Seminar Nasional Lustrum XV dan Dies Natalis ke-75 Universitas Gadjah Mada (UGM), di Balai Senat, satu tahun yang lalu dengan topik Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian dalam konteks “Masa Depan Demokrasi Indonesia”, Kamis 28 November 2024.
Dewi Candraningrum, sebagai narasumber pada Panel Kedua, bersama Zainal Arifin Mochtar dan Lukman Nur Hakim. Diskusi dengan tema “Perdamaian, Keamanan, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia: Pendekatan Interseksional.” Dia membawa topik bertajuk “Dimensi Gender dalam Perdamaian dan Sumber Daya Alam (SDA)”.
Beberapa garis besar yang penulis tangkap, ia menyampaikan tentang ketidakadilan sosial-ekologis konflik SDA dan gender. Lalu ketegangan karakteristik kolonial masih ada dalam praktik industrialisasi. Tren manusia mengubah planet mengakibatkan kerusakan alam.
Aktivisme sipil meningkat karena sadar dan respon dari trauma kolektif, karena kekerasan pencemaran lingkungan dan polusi udara bagian dari praktik kolonisasi, serta merawat sebagai resolusi konflik SDA—melalui brokohan maupun selametan.
Dewi Candraningrum, kelahiran Boyolali yang mendedikasikan sebagai pengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun UIN Sunan Kalijaga. Dia mengajar di Konsentrasi Islam dan Kajian Gender, menjadi salah satu figur kunci populerkan ekofeminisme di Indonesia. Yakni melalui berbagai jalur: Pertama, penyusunan dan penyuntingan buku-buku seri Ekofeminisme.
Kedua, kerja intelektual di berbagai kampus dan jejaring advokasi melalui Jurnal Perempuan/Indonesian Feminist Journal, serta; Ketiga, produksi narasi publik melalui ceramah, pameran, maupun wawancara—yang menyulam pengalaman perempuan akar rumput dengan kritiknya terhadap kapitalisme-ekstraktif dan patriarki.
Keseluruhan dalam pengalamannya membentuk kerangka ekofeminis khas Candraningrum, yang berbasis pada kearifan lokal Nusantara. Peka terhadap spiritualitas-komunial, namun kritis terhadap struktur kuasa modern yang merusak ekologis dan memarginalkan perempuan.
Seri “Ekofeminisme” sebagai Arsip Epistemik
Seri “Ekofeminisme” yang disunting Candraningrum bekerja sebagai “arsip epistemik”—yang menghimpun telaah lintas bidang. Misalnya;
Ekofeminisme I
Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi dan Budaya, melihat bagaimana dialektika teori-praksis, relasi antara perempuan dan alam (environment) dipengaruhi struktur kekuasaan. Seperti patriarki, kapitalisme, serta bagaimana agama dan budaya menjadi sarana kritik terhadap krisis ekologis.
Dalam seri tersebut, berupaya menghadirkan integrasi pemikiran agama, pendidikan, ekonomi dan budaya dalam pembacaan yang tidak terpisah, sebagai ruang kajian lokal Indonesia. Konsep ekofeminisme yang seringkali dibahas dalam diskursus global, dapat kita terjemahkan dalam kondisi sosial budaya Indonesia.
Kemudian mendorong pembacaan kritis terhadap pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi dan modernitas yang abai terhadap relasi gender dan lingkungan. Selain itu mendorong usulan alternatif yang lebih adil ekologis dan perspektif gender.
Ekofeminisme II
Narasi Iman, Mitos, Air dan Tanah, secara umum berupa eksplorasi relasi antara perempuan dan alam dalam narasi keimanan, mitos serta unsur elemen alam seperti air dan tanah. Selain itu, tema besar mengkaji mitos, ritual, agama, kepercayaan lokal dan pengalaman kehidupan perempuan di daerah dilihat dalam lensa ekofeminisme.
Seperti narasi keagamaan, mitos tradisional, dan relasi tanah dan air dalam konteks Indonesia saling bertaut dengan pengalaman perempuan dan alam. Studi kasus konkretnya, perempuan dalam industri batik rumahan, pengetahuan perempuan Tengger terhadap tanah, air dan hutan, serta relasi perempuan dengan alam di lereng gunung, dll.
Ekofeminisme III
Tambang, Perubahan Iklim dan Memori Rahim, menjelaskan seputar aktivitas pertambangan, penguasaan SDA, dan konflik agraria melibatkan perempuan beserta dampaknya terhadap lingkungan dan tubuh/peran perempuan. Perubahan iklim bukan hanya menyoal isu lingkungan fisik, melainkan gender. Yakni menyoal perempuan lebih rentan, respon dan adaptasi bisa berbeda.
Kemudian memori rahim, merujuk kepada pengalaman tubuh perempuan—secara biologis, kultural, reproduktif, sebagai tempat memori, penderitaan, harapan, kerusakan dan perlawanan. Rahim sebagai metafora sekaligus realitas yang mengalami dampak dari kerusakan lingkungan dan pembangunan yang tidak adil.
Ekofeminisme IV
Tanah, Air, dan Rahim Rumah, secara umum menjelaskan pembangunan dan industrialisasi mempengaruhi tanah dan air sebagai bagian dari ruang hidup perempuan. Perempuan seringkali tidak memiliki akses maupun kontrol atas sumber daya seperti tanah dan air, sekaligus bagaimana mereka paling terdampak oleh kerusakan lingkungan dan polusi.
Selain itu ide rumah bukan hanya ruang fisik, melainkan pengalaman, memori, relasi, rasa aman, dan representasi tubuh/rahim (metafora dan nyata) perempuan. Rahim rumah sebagai simbol serta kenyataan keintiman, reproduksi, pemeliharaan dan perlindungan.
Ekofeminisme V
Pandemi Covid-19, Resiliensi, dan Regenerasi Kapitalisme, secara umum menjelaskan pandemi covid-19 sebagai krisis yang tidak netral gender dan ekologis—berdampak untuk perempuan, kerentanan dan ketidakadilan terungkap dan diperburuk dalam konteks kesehatan, ekonomi dan sosial.
Selain itu, resiliensi, menempatkan bagaimana perempuan dan komunitas lokal mengembangkan strategi adaptasi, ketahanan hidup, solidaritas, dan cara kreatif untuk melawan dampak pandemi. Terutama dalam aspek ekonomi, sosial, kerja dan ketahanan pangan.
Ekofeminisme VI
Planet yang Berpikir: Iman Antroposen, Polutan, Ekosida, dan Krisis Iklim, menjelaskan tentang Antrposen—memotret zaman dimana aktivitas manusia menjadi kekuatan geologis yang mengubah sistem Bumi secara global.
Polutan—fokus pada polusi udara, air, tanah, limbah plastik, bahan kimia, polusi industri mempengaruhi manusia dan alam, dan berdampak pada perempuan dan anak. Ecosida—merujuk pada kerusakan lingkungan skala besar dianggap sebagai kejahatan terhadap alam. Misalnya degradasi habitat, deforestasi, pencemaran sistem air, pelepasan gas rumah kaca, hilangnya biodiversitas.
Lanjutnya, menyinggung soal Krisis Iklim—berdampak nyata di berbagai skala lokal, nasional dan global, serta dampak secara langsung terhadap perempuan, komunitas miskin, masyarakat adat lebih rentan. Iman/Spiritual/Etika—refleksi keimanan dan spiritualitas (Islam dan Tradisi Lokal) sebagai landasan etika hubungan manusia-alam, terkhusus transformasi ekologis dari pesantren, interpretasi agama dan spiritualitas perempuan sebagai praktik perlawanan terhadap degradasi lingkungan.
Resiliensi dan Adaptasi Lokal. Menempatkan perempuan dan komunitas di daerah berupaya tetap bertahan (ketahanan pangan, pengelolaan sampah, tradisi, manufaktur lokal dan praktik budaya) sekaligus menolak/merespon polusi dan kerusakan ekologis.
Sebagai editor, Candraningrum menghimpun tulisan sekaligus mengkurasi sudut pandang. Baik dari teologi dan fikih sosial, etnografi gunung-pesisir, sampai pengalaman sekolah rentan bencana yang dibaca melalui kacamata gender.
Kecenderungan kuratorial ini menolak oposisi biner “alam vs budaya” dan justru menunjukkan bahwa krisis relasi manusia-alam merupakan krisis historis yang diciptakan oleh tatanan patriarkal, kolonial, dan kapitalistik.
Politik Pengetahuan dan Jaringan Sosial: Ekofeminisme sebagai Teori-Praksis
Sebagai pemimpin redaksi Jurnal Perempuan/Indonesian Feminist Journal pada 2014-2016, Candraningrum mengemban peran ganda. Produser pengetahuan dan penghubung gerakan.
Posisi ini terlihat dalam terbitan IFJ yang membedah politik representasi dan tubuh perempuan di panggung elektoral 2014, sekaligus merawat tradisi kajian feminis kritis di Indonesia. Oleh karena itu, ekofeminisme bukan “sub-bidang” yang terpisah, melainkan lensa yang merembet ke isu-isu representasi, hukum, ekonomi hingga kebudayaan.
Jejak kuratorial juga meluber ke praktik artistik dan ruang komunitas. Dalam profilnya di berbagai lembaga independen, dari jejaring seni hingga forum riset ekstraktivisme, menunjukkan bagaimana ia memadukan arsip riset, seni-aktivisme, dan pemberdayaan komunitas (misalnya Jejer Wadon/”Womb Document” di Jawa Tengah).
Kontribusi paling nyata Dewi Candraningrum, menyuarakan kisah-kisah ekologi-politik perempuan akar rumput sebagai teori-praksis. Studi kasus Kendeng, para “Kartini Kendeng” menolak tambang semen dengan kidung dan aksi tubuh (menyemen kaki).
Alih-alih sebagai “simbolisme”, Candraningrum membacanya sebagai wacana tandingan terhadap ekstraktivisme—menghadirkan kembali tanah sebagai ibu, ritual sebagai politik, dan suara perempuan sebagai otoritas ekologis.
Studi kasus merapi, pembacaan atas mitos lokal dan praktik keseharian (sekolah, rumah, pemaknaan bencana) menyingkap relasi kuasa yang berlapis. Negara-korporasi, maskulinitas pembangunan, hingga epistemologi modern yang menyingkirkan pengetahuan lokal. Di bawah lensa ekofeminisme, “mitos” bukan takhayul, melainkan mode of knowing. Cara komunitas merumuskan etika terhadap tanah, air, dan risiko.
Dengan demikian, ekofeminisme Candraningrum memadukan semiotika tubuh (aksi ritual, nyanyian, dan lukikas), politik ruang (lahan ulayat, sumber air, ruang hidup pesisir/lereng), dan ekonomi politik (rantai pasok semen, sawit, dan tambang). Kerja intelektual mencari titik temu iman-adat-sains—bukan mengganti sains, melainkan menuntut sains yang rendah hati terhadap kosmologi lokal dan keadilan gender.
Etos Gerak, Kritik Struktur, dan Kontribusi Teoritis
Di tingkat pernyataan publik, Candraningrum konsisten menggarisbawahi dua hal. Pertama, feminisme harus melampaui slogan. Bekerja membangun ruang aman, memulihkan ekologi, dan merobohkan struktur yang timpang. Wawancaranya dengan Balairung (2017) menegaskan bahwa ekofeminisme merupakan dialektika konsep-praksis untuk menjawab krisis relasi manusia-alam. Gerakannya perlu menubuh dalam komunitas, bukan berhenti pada jargon.
Kedua, perempuan paling rentan terhadap krisis iklim bukan karena “kodrat”, melainkan akibat struktur sosial-ekonomi dari akses lahan hingga kerja reproduksi, timpang. Karena itu, kebijakan iklim yang adil gender adalah keharusan.
Dalam forum akademik-publik, ia sering menekankan kesetaraan manusia-non-manusia dalam horizon etis ekofeminisme. Menempatkan air, batu, tanah bukan hanya suatu objek, melainkan bagian dari jejaring kehidupan yang “berpikir” dan menuntut tanggung jawab. Narasi ini bukanlah romantisasi, melainkan metode dekolonisasi pengetahuan, mengeluarkan alam dari status “benda netral” dalam ekonomi modern.
Kontribusi teoretis, penulis menangkap tiga poin. Pertama, ekofeminisme sebagai kritik ekstraktivisme plus pemulihan kosmologi lokal. Candraningrum memadukan kritik atas kapitalisme-ekstraktif dengan kosmologi bukanlah nostalgia, melainkan politik pengetahuan untuk menata ulang relasi manusia-alam secara setara dan berkeadilan gender. Kerja-kerja editorial menyodorkan venue epistemik agar pengalaman lokal—Kendeng, Merapi, pesisir utara Jawa—masuk ke arus ilmu pengetahuan.
Kedua, dialektika antara iman, mitos, dan sains. Seri Ekofeminisme II mengajak untuk melihat iman dan mitos sebagai instrumen kritis. Iman membangun etika laku (merawat bumi). Mitos menyimpan memori ekologis-politik, sains memberi perangkat analitik—ketiganya dalam praksis komunitas. Dengan cara ini, Candraningrum menghindari jebakan esensialis (yang melabeli perempuan “alami”) tanpa memutus hubungan historis perempuan dengan bumi sebagai ruang reproduksi sosial.
Ketiga, seni sebagai metode pengetahuan. Melalui lukisan, instalasi dan pameran menjadi cara Candraningrum mematerialkan gagasan ekofeminisme dalam membacakan tubuh, memori, dan lanskap yang terluka. Jaringan Despite Extractivism dan ruang-ruang seni lokal, karyanya menggambarkan semiotika kritik perlawanan: visual menembus tembok teknokratis yang sering menutup telinga pada kisah perempuan.
Dialog dan Perbandingan: Implikasi Kebijakan dan Kritik Ketegangan
Secara global, diskursus ekofeminisme kerap menjadi perdebatan antara arus spiritual (Vandana Shiva) dan materialis (Mies-Warren). Candraningrum hadir menyulam keduanya, menerima nilai spiritual-komunal (kidung, dewi-dewi, tanah-ibu) tanpa menutup mata pada materalitas ketimpangan (akses lahan, kekerasan struktural, dan oligarki energi). Dari sinilah terlihat upaya “membumikan ekofeminisme”, kosmologi lokal berjumpa kritik ekonomi politik, dan bergerak dalam takaran komunitas (desa, lereng, pesantren dan ruang seni).
Sejauh penelusuran penulis, pemikiran Candraningrum hadir memberikan tawaran berupa implikasi kebijakan, seperti halnya: Pertama, urusan tanah-air sebagai hak sosial perempuan. Kebijakan lahan dan air mesti mengakui perempuan sebagai subjek hak (akses, kontrol, dan manfaat) bukanlah penerima dampak. Kasus kendeng memperlihatkan bahwa partisipasi substantif perempuan mengubah keputusan tata ruang.
Kedua, pengetahuan lokal sebagai evidence. Kidung, ritual, dan mitos sebagai data pengetahuan yang memuat etika relasional. Proses AMDAL dan konsultasi publik harus mengadopsi metode yang mengakui memori ekologis-komunal. Ketiga, iklim berkeadilan gender. Perempuan memikul beban berlapis dalam krisis iklim, seperti pangan, air, dan perawatan membutuhkan program adaptasi. Mitigasi harus mengarusutamakan gender, termasuk dukungan ekonomi perawatan dan jaminan sosial.
Perempuan Lebih Dekat ke Alam
Sejumlah kritik klasik pada ekofeminisme, risiko esensialisasi perempuan sebagai “lebih dekat ke alam” juga menghantui pembacaan atas kosmologi lokal. Pendekatan Candraningrum berupaya menggeser esensialisme dengan menempatkan kosmologi terbaca sebagai politik pengetahuan dan strategi resistensi, bukanlah kodrat.
Namun pekerjaan sehari-hari dalam memperluas basis riset kuantitatif-kualitatif (data kesehatan, ekonomi dampak ekstraktivisme), menguji kebijakan alternatif, dan memastikan suara kelompok rentan (buruh tani migran, perempuan adat muda, difabel) hadir setara.
Dengan memadukan arsip buku-jurnal, jejaring seni-komunitas, dan narasi publik yang kuat, Candraningrum menawarkan model ekofeminisme yang berakar, interdisipliner, dan partisipatoris. Ia mengubah kisah perempuan lereng, pesisir, dan desa menjadi teori hidup yang menantang ekstraktivisme dan menata ulang relasi manusia-alam.
Di tengah krisis iklim dan demokrasi ekologis, model ini memberikan pembelajaran penting bahwa pengetahuan yang berpihak pada yang rentan, pada bumi—bukanlah kebetulan moral, melainkan pilihan politik yang lahir dari mendengar, mengarsip, dan bergerak bersama. []