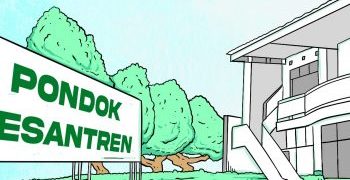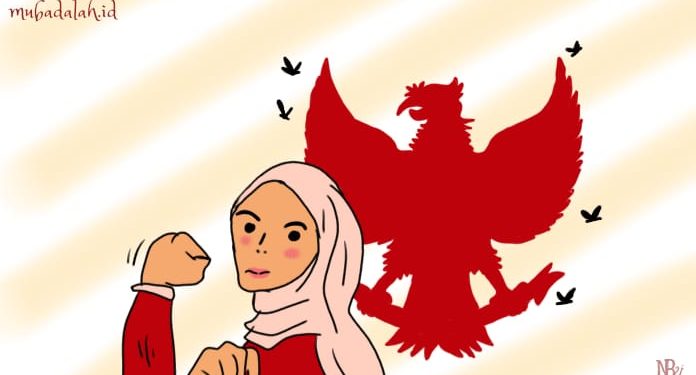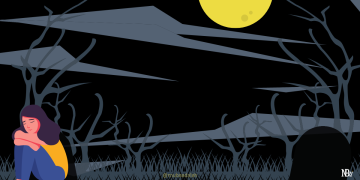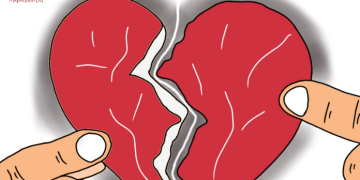Mubadalah.id – Pada masa orde baru, Pancasila menjadi asas tunggal dalam perpolitikan dan organisasi masyarakat. Pada masa ini tidak boleh ada definisi lain dari pancasila selain apa yang menjadi instruksi pemerintah. Konon katanya kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah perpecahan bangsa, terutama pasca gejolak politik tahun 1965.
Implementasi Pancasila sebagai asas tunggal salah satunya dengan diwajibkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang disingkat P4. P4 menjadi instrumen pendidikan ideologi yang tertanamkan secara sistematis kepada seluruh eleman bangsa, mulai dari pelajar, birokrasi hingga masyarakat sipil.
Namun yang menjadi persoalan adalah realitas politik saat itu menunjukkan ketidaksesuaian antara asas ideologi yang digaungkan dengan praktik yang terjadi di pemerintahan. Rezim orde baru membangun sistem politik yang sentral, kebebasan berpendapat terbatasi dan kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Sehingga pancasila pada masa ini cenderung menjadi alat legitimasi kekuasaan ketimbang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
Pancasila dalam bayang-bayang orde baru
Dalam konteks ini, Pancasila kehilangan daya transformasinya sebagai ideologi yang membebaskan, karena lebih terposisikan sebagai instrumen kontrol sosial. Nilai-nilai luhur seperti keadilan sosial, demokrasi permusyawaratan, maupun kemanusiaan yang beradab justru tereduksi dalam praktik birokrasi yang represif dan eksklusif.
Dengan kata lain, Pancasila yang sejatinya dimaksudkan untuk menjadi ideologi pemersatu bangsa telah menyempit maknanya oleh kepentingan politik rezim, sehingga menjauh dari esensi filosofisnya.
Ironinya, indoktrinasi P4 yang seharusnya membangun kesadaran kritis justru menumbuhkan kepatuhan buta, di mana rakyat terpaksa menerima tafsir tunggal tanpa ruang untuk menafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman. Hal ini menimbulkan warisan problematis: Pancasila kita pandang lebih sebagai simbol formal negara ketimbang sebagai etika publik yang menghidupi praktik demokrasi dan keadilan sosial.
Setelah orde baru berakhir, pemaknaan terhadap Pancasila mengalami pergeseran yang progresif. Orde reformasi telah membuka ruang kebebasan lebih luas bagi masyarakat dalam menginterpretasikan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila tidak lagi bermakna tunggal seperti yang penafsiran orde sebelumnya yang terkontrol negara. Pancasila kembali mendapatkan tempatnya sebagai ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai filosofisnya.
Dinamika Multitafsir Pancasila
Pada dasarnya, Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara memiliki makna dan nilai yang universal bagi kehidupan manusia. Nilai yang kita maknai bersama yang mencerminkan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Perlu kita sadari juga bahwa nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sendiri juga memiliki pemahaman yang universal tergantung perspektif dalam menilainanya.
Multitafsir Pancasila membawa dua konsekuensi. Pertama, multitafsir bisa menjadi ancaman jika Pancasila terpelintir untuk kepentingan kelompok atau rezim tertentu. Misalnya, ketika Pancasila hanya kita jadikan simbol legitimasi politik, nilai-nilainya justru tereduksi dan kehilangan makna substantif.
Kedua, multitafsir pancasila bisa menjadi peluang jika kita lakukan dengan cara yang inklusif dan kontekstual. Justru sifat terbuka inilah yang membuat Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman, mulai dari tantangan globalisasi, pluralisme agama, hingga kemajuan teknologi digital.
Pancasila sejatinya bukan ideologi yang kaku, melainkan dasar filosofis yang hidup bersama masyarakat. Oleh karena itu, multitafsir pancasila harus kita pandang sebagai bagian dari dinamika bangsa, dengan catatan tidak menghilangkan esensi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Tidak ada tafsir yang keliru tentang pancasila, tapi yang ada tafsir yang sesuai atau tidak dengan kepentingan bangsa. Bahkan tafsir terhadap kepentingan bangsa pun sering berbeda-beda sesuai kepentingan penguasa. setiap kita berhak menafsirkan pancasila untuk kemaslahatan bersama, bukan kepentingan segelintir orang yang menamakan diri sebagai bagian dari bangsa. Kadang yang baik bukan berarti yang terbanyak, tetapi yang memberi dampak untuk kebaikan bersama
Pancasila sebagai Nilai Universal untuk Kemaslahatan Bangsa
Meski kebebasan reformasi menghadirkan beragam tafsir yang lebih kaya, tantangan berupa politik identitas, radikalisme, dan polarisasi tetap menguji eksistensi Pancasila. Karena itu, Pancasila harus kita tempatkan bukan hanya sebagai slogan atau simbol seremonial, melainkan sebagai pedoman etis yang hidup dalam kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta praksis sosial, agar benar-benar mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila memiliki kedudukan yang unik sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa Pancasila tidak pernah bebas dari multitafsir. Pada masa Orde Baru, Pancasila lebih banyak terposisikan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan, sehingga nilai-nilainya sering kali tidak terwujudkan dalam realitas. Multitafsir terhadap Pancasila dapat menjadi ancaman jika hanya menguntungkan kepentingan penguasa, tetapi juga bisa menjadi kekuatan jika kita tafsirkan secara inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, Pancasila tetap relevan sepanjang masa karena nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Pancasila menjadi jalan tengah yang dapat menyatukan keberagaman dan menjadi pedoman moral dalam membangun bangsa. Dengan pemahaman yang benar dan penerapan yang konsisten, Pancasila mampu mewujudkan kemaslahatan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi benteng kokoh menghadapi tantangan zaman. []