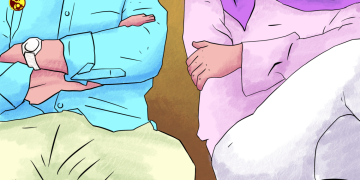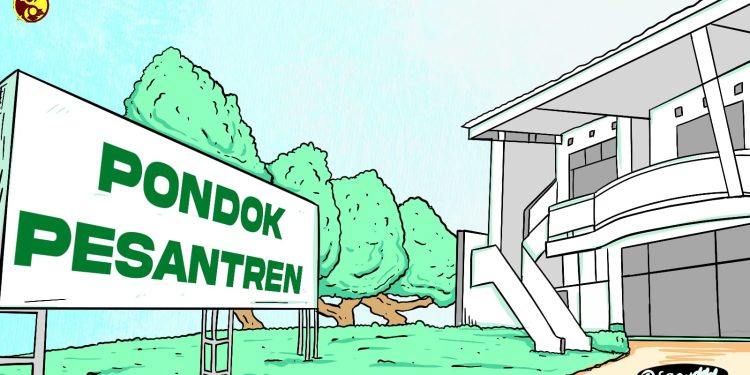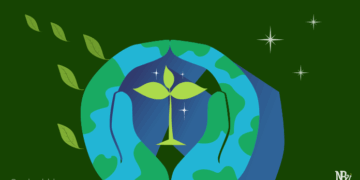Mubadalah.id – Di dua pertiga Agustus, saya menghadiri gelaran bedah buku Nanam, Ngaji, Ngelmu: Pesantren dan Politik Ekologi Pascakolonial (2025) karya Mardian Sulistyati dan Dewi Candraningrum di Warung Sastra Yogyakarta. Sementara, seorang pengajar sosiologi dari UIN Sunan Kalijaga, Bernando J. Sujibto, terdapuk sebagai pembedahnya.
Usut punya usut, embrio buku ini berawal dari tesis yang Mardian Sulistyati garap tatkala menempuh pendidikan di prodi Interdisiplinary Islamic Studies konsenrasi Kajian Islam dan Gender di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2023 silam. Pada awalnya, tesis itu berjudul “Nanam, Ngaji, Ngelmu Pesantren Ekologi Ath-Thaariq Garut: Politik Agraria Ekofeminisme Pascakolonial” tak jauh beda ketika terkonversikan menjadi buku.
Bilamana melihat sepintas judulnya, buku gubahan Mardian dan Dewi tersebut mencoba mempertautkan antara lingkungan dan agama—dalam hal ini, Islam. Oleh karena singgungan keduanya, saya ingat pendapat K.H. Husein Muhammad dalam buku Islam: Cinta, Keindahan, Pencerahan, dan Kemanusiaan (2021) bagaimana manusia mendapat kepercayaan (amanat) sebagai wakli-Nya (khalifah) untuk mengelola alam.
Alam yang sedemikian luas dan jamak ini terancang mengandung pelbagai potensi dan ketersediaan bahan bagi keperluan makhluk hidup. Akan tetapi, Buya Husein melanjutkan, pada sisi berbeda manusia juga memiliki tanggung jawab kosmis terhadap kehidupan nabati dan hewani. Sebuah kebebasan sekaligus tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam memanfaatkan sekaligus menjaga alam.
Secara tradisi, pesantren merupakan institusi pendidikan Islam. Oleh karena itu, tak heran jika mendiang Gus Dur mengatakan pesantren sebagai subkultur. Sebagai institusi, pesantren lazimnya memiliki elemen-elemen pendukung.
Zamakhsyari Dhofir dalam buku Tradisi Pesantren (1985) membabarkan elemen-elemen utama itu ialah; pondok, masjid, santri, dan kiai. Konstruksi hari ini pesantren kerap terpaku pada kiai sentris dan hierarki. Inilah yang menjadi alasan berbagai studi mengreinterpretasikan kiai sebagai seorang pemimpin/pimpinan pesantren, yang berarti bisa lelaki, juga perempuan—dengan sebutan nyai.
Pesantren sebagai Subkultur dan Agensi
Buku Nanam, Ngaji, Ngelmu hadir sebagai monumen pertemuan Mardian dengan salah satu elemen tersebut, yakni Nyai Nisa Wargadipura. Seorang perempuan yang menahkodai Pesantren Ekologi At-Thariq di Garut, Jawa Barat.
Nisa memaknai pesantren sebagai agensi lingkungan, yang memusatkan manusianya—santrinya—dengan alam. Selain mengaji, para santri juga belajar bertani dengan model ekologi, maksudnya memelihara pelbagai habitat dan ekosistem yang saling terkait di dalamnya.
Tahun 2009, tatkala pesantren ini berdiri, seakan memberi perspektif tak biasa (baru) dalam dunia kepesantrenan. Betatapun mulanya pesantren berangkat dari nadi tradisi keislaman tapi pesantren yang Nisa bangun tak hanya memokuskan pada rumpun keilmuan Islam semata. Ada poros, atau bahkan keluputan, yang jarang terambil pesantren pada umumnya untuk menaruh peduli akan ilmu kealaman.
Buku Nanam, Ngaji, Ngelmu: Pesantren dan Politik Ekologi Pascakolonial (2025) sedikit-banyak, yang saya tangkap, membayankan ruang sosial dan kultural pesanren dalam merespon krisis ekologi kontemporer. Terikuti dengan refleksi mendalam sang penulis ihwal keterhubungan antara iman, ilmu, dan ekologi dalam kanta tradisi pesantren.
Nanam sebagai laku menaruh bibit atau benih ke tanah sebagai upaya wujud pertumbuhan. Menghayati apa saja yang bisa kit tanam bakal membuahkan pohon pengetahuan, proses ngaji. Lantas keduanya tercakup dalam konsep ngelmu, pengetahuan batin dan spiritual lewat penghayatan dan lelaku.
Menabur Kepedulian
Bilamana tiap-tiap insan menyadari tiga konsep sederhana tersebut yang, sejatinya saling berkaitan dan memberi manfaat, niscaya segala nestapa seperti kemiskinan struktural dan konflik agraria tak terjadi dalam masyarakat agraris.
Manusia, sebagaimana telah Buya Husein jelaskan di atas, memiliki kebebasan mengelola sekaligus menjaga alam. Potensial keduanya bisa terjadi: memanfaatkan atau mengeksploitasi. Kondisi ini mengingatkan kita pada lagu “Pergi” gubahan Hutan Tropis. Penggalan liriknya mengalun: Kami makan apa yang kami tanam/ Di tanah kami menari/ Jangan kau ganggu dengan mimpimu/ Mimpi tambang, mimpi eksploitasi.
Kita tidak ingin kondisi Indonesia terus-menerus diceraikan oleh alam, oleh lingkungan. Alam menumpahkan amarah lewat pelbagai bencana, akibat manusia keterlaluan mengekploitasinya. Jalan yang Dian dan Dewi tuliskan lewat konsep nanam, ngaji, dan ngelmu seperti yang lebih dulu para santri Pesantren Ekologi At-Thariq amalkan bisa kita jadikan nutrisi bacaan menjali kehidupan hari ini dan mendatang.
Pepatah masyhur “apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai” jika terkontekstualisasikan dengan bahasan ini tampaknya sedikit menyentil kita semua. Kita seringnya berlomba-lomba menuai tanpa sedikit pun berusaha dan berpayah-payah menanam.
Maksud inilah yang boleh jadi menjadi satu dari sekian sorotan terhadap politik ekologi pascakolonial. Bermacam warisan kolonialisme berbentuk eksploitasi alam, kapitalisme agrarian, dan hegemoni epistemik masih dan terus manusia pertahankan.
Yang dituju adalah keinstanan dalam mengeruk segala yang alam berikan, bukan memikirkan bagaimana alam terjaga bagi generasi-generasi mendatang. Nah, Pesantren Ekologi At-Thariq menjadi satu ruang bagaimana pesantren sebagai institusi pendidikan berusaha membangun peradaban ekologis berkelanjutan. Bukan saja berpatron pada nilai keislaman semata melain sungguh-sungguh menabur kepedulian terhadap lingkungan.
Ekofeminisme Spiritual
Nyai Nisa Wargadipura, meminjam perspektif Mardian Sulistyati dan Dewi Candraningrum, sebagai garis depan pesantren ekologi ini tergambarkan sebagai skema ekofenisme ala pesantren. Ekofeminisme spiritual. Memokuskan sakralitas manusia dengan alam lewat penekanan nilai-nilai kepedulian serta kasih sayang.
Pemaknaan Nisa dan para santrinya terhadap lingkungan bukan melulu sebagai ruang manusia berpijak-hidup. Konsep hablum minal alam betul-betul mereka sebagai pertautan sesama makhluk ciptaan Allah Swt. Pesantren Ekologi At-Thariq, Nyai Nisa Wargadipura, dan santri-santrinya melihat alam sebagai wujud subjek mutualistis dengan manusia. Menafikannya dari subjek eksploitatif, kanon kezaliman, serta kesempatan penindasan.
Sebagai penutup, kita bisa menghayati puisi Ibu-ibu Kendeng yang menolak penambangan semen di pegunungan Kendeng tempat mereka mukim. Ibu-ibu Kendeng memakai metafora Ibu Bumi sebagai penggambaran relasi perempuan dengan alam. Baitnya demikian: “Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili.” artinya ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, ibu bumi yang mengadili. []